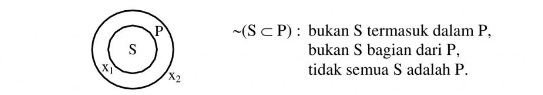DAFTAR ISI
TINJAUAN MATA KULIAH
MODUL 1 : PENGENALAN LOGIKA
MODUL 2 : DASAR-DASAR PENALARAN
MODUL 3 : ANALISIS DAN DEFINISI
MODUL 4 : PROPOSISI KATEGORIK
MODUL 5 : PENYIMPULAN LANGSUNG
MODUL 6 : SILOGISME KATEGORI
MODUL 7 : PROPOSISI MAJEMUK
MODUL 8 : SISTEM NILAI KEBENARAN
MODUL 9 : PENYIMPULAN DAN PEMBUKTIAN
TINJAUAN MATA KULIAH
Menyajikan materi yang berhubungan dengan peranan logika sebagai teori penyimpulan dengan menggunakan bahasa sebagai sarana dalam mengungkapkan konsep.
Materi didalamnya disajikan secara tematis dalam pengertian bahwa konsep-konsepnya dikaitkan dengan proses dalam melakukan penyimpulan.
Pembahasan juga mencakup pengertian dan sejarah logika, berbagai mancam konsep dan term, prinsip-prinsip penalaran, berbagai proposisi seperti proposisi kategorik, proposisi hipotetik, proposisi disjungtif, proposisi konjungtif, termasuk disjungsi dan konjungsi.
Selain itu membahas pula mengenai penalaran hipotetik, penalaran oposisi, penalaran eduksi, berbagai prinsip penyimpulan yang meliputi silogisme beraturan, silogisme tak beraturan, silogisme majemuk, serta penyimpulan nonsilogisme.
MODUL 1 :
PENGENALAN LOGIKA
Perkembangan logika pada saat ini sangat pesat sekali dan hampir setiap saat ada teori-teori baru logika yang tidak dapat diuraikan keseluruhan dalam modul ini.
Logika pada dasarnya dibedakan antara logika deduktif dan logika induktif, adapun yang akan diuraikan dalam kesatuan beberapa modul ini hanya logika deduktif, dan yang berlaku pada saat sekarang ini bukan logika selogistik atau juga bukan logika tradisional, yang sering disebut dengan logika modern atau logika simbolik. Logika modern menggunakan teori himpunan sebagai pangkal dan sekaligus sebagai bentuk penalarannya.
Logika sebagai teori penyimpulan menggunakan bahasa sebagai ungkapan konsep maupun pendapat karena pendapat yang terdiri atas hubungan dua konsep tidak dapat diketahui oleh orang lain sehingga membutuhkan bahasa sebagai ungkapannya, baik bahasa alami maupun bahasa ilmiah.
Fungsi bahasa salah satu, diantaranya logika dan komunikatif, serta fungsi inilah ilmu pengetahuan dapat berkembang dengan pesat sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia.
Bahasa yang digunakan dalam logika adalah berbentuk kalimat yang dapat dinilai benar atau salah, yang disebut juga dengan kalimat berita.
Kalimat ini hanya dua kemungkinan nilainya, benar atau salah yang berdasar pertimbangan akal, tidak ada penilaian setengah benar atau setengah salah.
Selanjutnya, untuk mendukung pengenalan terhadap logika ini perlu juga dikemukakan sejarah ringkas logika sehingga dapat diketahui bentuk logika yang bagaimana perkembangan saat sekarang ini karena jika belajar logika sekarang berarti logika yang dikembangkan sekarang ini bukan logika tradisional atau logika selogistik, sama halnya jika belajar matematika adalah matematika yang berlaku saat ini bukan matematika tradisional.
Dalam logika selogistik atau logika tradisional banyak kelemahan-kelemahannya,bahkan hukum-hukum yang dikemukakan setyelah diterapkan dengan menggunakan teori-teori yang terbaru banyak yang tidak tepat.
KEGIATAN BELAJAR 1 :
PENGERTIAN LOGIKA
Logika berasal dari kata Yunani "logos" yang berarti "kata", "uraian pikiran" atau "teori". Istilah logika secara etimologis dapat diartikan "ilmu tentang uraian pikiran".
Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis berpangkal pada penalaran, dan sekaligus juga sebagai dasar filsafat, oleh karena itu untuk berfilsafat yang baik harus dilandasi logika, supaya penalarannya logika dan kritik.
Disamping itu, logika juga juga sebagai sarana ilmu, sama halnya matematika dan statistik karena semua ilmu harus didukung oleh penalaran logika dan sistemik yang merupakan salah satu syarat sifat ilmiah. Dengan demikian, logika berfungsi sebagai "dasar filsafat dan sarana ilmu".
Syarat sifat ilmiah salah satu diantaranya "harus sistemik" yang dimaksudkan adalah mempunyai susunan menurut aturan tertentu yang bagian-bagiannya saling berhubungan untuk mencapai maksud atau peranan tertentu serta tidak mengandung kontradiksi di dalamnya.
Dengan fungsi sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu maka logika merupakan "jembatan penghubung" antara filsafat dan ilmu, yang secara terminologi logika didefinisikan : 'teori tentang penyimpulan yang sah" atau juga didefinisikan "sistem penalaran yang menelaah tentang prinsip-prinsip penyimpulan yang sah". Penyimpulan yang dimaksudkan adalah bagian dari pemikiran dan tidak semua pemikiran merupakan penyimpulan, seperti menghitung, mengingat-ingat, bukanlah pembahasan logika.
Penyimpulan pada dasarnya bertitik tolak dari suatu pangkal pikir tertentu yang kemudian ditarik suatu kesimpulan, misalnya.
Dari pangkal-pikir "setiap benda di alam semesta ini semula tidak ada kemudian menjadi ada dan tidak ada lagi", dan "dari tidak ada kemudian menjadi ada dan tidak ada lagi dapat dinyatakan mengalami perubahan", dengan demikian "setiap benda di alam semesta ini selalu mengalami perubahan".
Rangkaian inilah yang disebut dengan penyimpulan. Jadi, ada pangkal-pikirnya dan ada kesimpulannya. Contoh lain yang sederhana, misalnya :
"semua rakyat Indonesia harus ber-Pancasila", berarti "semua yang tidak diharuskan ber-Pancasila bukan Rakyat indonesia".
Dalam contoh kedua ini sebagai pangkal-pikirnya adalah "semua rakyat Indonesia harus ber-Pancasila", yaitu yang sebagai titik tolak penyimpulan sehingga dapat dinyatakan sebagai kesimpulannya "semua yang tidak diharuskan ber-Pancasila bukan rakyat Indonesia".
Dalam logika yang ditelaah adalah penyimpulan yang sah, artinya sesuai dengan pertimbangan akal dan runtut sehingga dapat dilacak kembali. Sah dalam penyimpulan yang akan dibicarakan di sini sekaligus juga benar.
Dalam logika tradisional dinyatakan penyimpulan yang sah belum tentu benar ; Dalam arti dari pangkal-pikir yang benar dapat disimpulkan suatu pernyataan yang salah, demikian juga dari pangkal-pikir yang salah dapat disimpulkan pernyataan yang benar. Inilah yang terjadi dalam logika selogistik atau sering juga disebut dengan logika tradisional sebagaimana yang diikuti dalam buku Logika dasar (R.G. Soekadijo). Dalam logika tradisional ada hukum penyimpulan yang dirumuskan sebagai berikut :
Apabila pangkal-pikirnya salah kesimpulan penalaran dapat benar dapat salah, sebaliknya apabila kesimpulannya benar pangkal-pikir penalaran dapat benar dapat salah.
Misal (contoh dalam Logika Dasar) :
Malaikat itu benda fisik : salah
Batu itu malaikat : salah
Jadi : Batu itu benda fisik : benar
Ingat ini logika tradisional, logika yang akan dibahas di sini adalah logika modern karena jika mengatakan logika saat sekarang ini ya logika yang dikembangkan sekarang, bukan logika tradisional. Sama halnya matematika, jika menyatakan matematika saat sekarang ini ya matematika modern bukan matematika tradisional.
Kesalahan contoh penalaran diatas adalah terletak pada pernyataan yang sebagai pangkal-pikir yang keduanya masing-masing tidak ada hubungan yang sebebnarnya tidak dapat dipastikan kesimpulannya. Konsep "malaikat" dengan konsep "benda mati" tidak ada hubungan yang dirangkai dengan pernyataan positif, demikian juga konsep "batu" dengan konsep "malaikat" juga tidak ada hubumngan yang dirangkai dengan pernyataan positif. Kesimpulan penalaran diatas seharusnya dirumuskan sebagai berikut :
Malaikat itu benda fisik : salah
Batu itu malaikat : salah
Jadi : ? (tidak dapat disimpulkan)
Di samping logika tradisional, dalam matematika pun jjuga terjadi dua konsep yang tidak ada hubungan dinyatakan dalam satu pernyataan positif, yaitu implikasi. Dalam implikasi dibenarkan juga dua komponennya tidak ada hubungan asalkan keduanya benar, misal :
Jika Jakarta ibu kota Indonesia maka Barrack Obama Presiden Amerika.
Contoh tersebut menurut logika bukan implikasi karena implikasi dalam logika dua komponennya harus mempunyai hubungan ketergantungan antara bagia pertama dan bagian kedua. Jika contoh tersebut diakui sebagai implikasi, berarti dapt disimpulkan dalam bentuk kontraposisi, sebagai berikut :
Jika Jakarta Ibu Kota Indonesia maka Barrack Obama Presiden Amerika, berarti jika Barrack Obama bukan Presiden Amerika maka Jakarta bukan ibu kota Indonesia.
Penyimpulan tersebut berarti pangkal-pikirnya benar tetapi kesimpulannya kurang tepat atau salah karena Jakarta Ibu kota Indonesia bukan tergantung Barrack Obama jadi presiden atau tidak, kedua bagiannya tidak ada hubungan, padahal dalam bentuk kontraposisi keduanya sudah benar karena sudah memenuhi aturan penyimpulan bentuk kontraposisi.
Untuk menghindari ketidaktepatan seperti penalaran tersebut maka pangkal-pikir sebagai titik tolak penalaran antar bagiannya harus berhubungan, jika tidak ada hubungan tidak dapat digunakan sebagai pangkal-pikir penalaran.
Dengan demikian, hubungan dua komponen atau dua konsep atau juga dua bagian merupakan syarat utama dalam penyimpulan yang sah dan tepat, tanpa ada hubungan tidak dapat dijamin kesimpulannya sesuai dengan materi yang terkandung di dalam penalaran tersebut.
Logika modern yang diuraikan dalam modul logika ini tidak akan membenarkan hal-hal yang tidak logika baik bentuk maupun isinya. Logika modern berpangkal pada keluasaan konsep atau disebut juga berpangkal pada himpunan karena setiap kata, setiap istilah, dan setiap pernyataan pada dasarnya mengungkapkan suatu himpunan, yaitu menunjuk pada suatu kelompok dengan ciri-ciri tertentu. Jika adaistilah atau konsep yang tidak menunjuk pada sesuatu hal itu pun juga disebut dengan himpunan, yaitu himpunan kosong, himpunan yang tidak mempunyai anggota sama sekali.
A. DASAR LOGIKA MODERN
Setiap hal yang ada diungkapkan dengan kata atau istilah sebagai tanda dari hal tersebut sehingga setiap kata atau istilah mempunyai himpunan, mempunyai keluasan. Misal, istilah "manusia", yang ditunjuk adalah semua hal yang dapat disebut dengan manusia sehingga ini merupakan suatu hal kumpulan yang mempunyai ciri-ciri kemanusiaan, yaitu berakal, jika tidak berakal bukanlah manusia. Kumpulan yang mempunyai ciri berakal ini yang disebut dengan himpunan manusia.
Himpunan inilah yang menjadi dasar logika modern, dan himpunan didefinisikan "suatu kumpulan hal yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang sama".
Dengan dasar himpunan maka semua unsur penalaran dalam logika pembuktiannya menggunakan diagram himpunan merupakan pembuktian secara formal jika diungkapkan dengan diagram himpunan sah dan tepat maka sah dan tepat pula penalaran tersebut.
Demikian juga jika pembuktiannya benar maka benar pula penalran tersebut sehingga dapat dikatakan kebenaran bentuk adalah sesuai dengan isi. Ini yang perlu diketahui perkembangan logika saat sekarang, Jika benar bentuknya tidak sesuai dengan isi untuk apa belajar logika, tidak ada gunanya. Logika yang dipelajari sekarang adalah benar bentuk juga benar isi, Misalnya :
Pangkal-pikir pertama : Semua organisme mengalami perubahan
Pangkal-pikir kedua : Semua manusia adalah organisasi
Kesimpulan : Semua manusia mengalami perubahan.
Penyimpulan tersebut untuk membuktikan sah tidaknya kesimpulan yang diturunkan diungkapkan dengan diagram himpunan , yakni lingkaran-lingkaran untuk melukiskan hubungan masing-masing konsep yang diperbandingkan.
Pangkal-pikir pertama; "semua organisme mengalami perubahan"
Pernyataan tersebut diperbandingkan antara himpunan "organisme" dengan himpunan "yang mengalami perubahan", mana yang lebih luas. Ternyata konsep "yang mengalami perubahan" yang lebih luas, himpunan "organisme" bagian dari himpunan "yang mengalami perubahan" atau himpunan "yang mengalami perubahan", meliputi himpunan "organisme" sehingga dapat dinyatakan "tidak semua yang mengalami perubahan adalah organisme".
Pernyataan "semua organisme mengalami perubahan" jika "organisme" disimbolkan dengan "B" dan "yang mengalami perubahan" disimbolkan dengan "C" maka dapat diungkapkan dalam diagram himpunan bahwa "B bagian dari C", di tulis "B c C".
Pangkal-pikir kedua; "semua manusia adalah organisme". Pernyataan ini pun juga diperbandingkan antara himpunan "manusia" dengan himpunan "organisme" apakah sama atau ada yang lebih luas. Ternyata konsep "organisme" lebih luas, himpunan "manusia" bagian dari himpunan "organisme" atau himpunan "organisme", meliputi himpunan "manusia" sehingga dinyatakan "tidak semua organisme adalah manusia". Pernyataan "semua manusia adalah organisme" jika "manusia" disimbolkan dengan "A" dan "organisme" tetap disimbolkan dengan "B" maka dapat diungkapkan dalam diagram himpunan bahwa "A bagian dari B" atau "B, meliputi A", ditulis "A c B".
Kesimpulan; hubungan dua pangkal-pikir diatas, dapat diungkapkan "semua B adalah C" dan "semua A adalah B" karena ada konsep yang sama, yaitu "B" atau "organisme" maka dapat disimpulkan bahwa "semua A adalah C", yaitu "semua manusia mengalami perubahan".
Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka penyimpulan : "semua organisme mengalami perubahan, dan semua manusia adalah organisme maka semua manusia mengalami perubahan", dapat dirumuskan sebagai berikut :
Pertama-tama yang melukiskan luas konsep atau luas pengertian dalam bentuk diagram himpunan adalah seorang ahli logika dan matematika Swiss bernama Leonhard Euler, selanjutnya dikembangkan oleh John Venn seorang ahli logika Inggris sehingga bentuk-bentuk duagram yang untuk melukiskan luas pengertian disebut dengan "diagram Venn". Perkembangan selanjutnya dan juga dalam modul ini diagram luas konsep atau luas pengertian cukup disebut dengan istilah "diagram himpunan" karena bukan John Venn yang pertama kali mengemukakannya.
Bentuk diagram himpunan ini dapat berupa lingkaran-lingkaran maupun bentuk-bentuk lain yang dapat digunakan untuk menghimpun suatu kelompok dalam satu konsep atau satu kelompok yang berdasarkan ciri pembeda yang sama.
B. LOGIKA DEDUKTIF DAN LOGIKA INDUKTIF
Berdasarkan proses penalarannya dan juga sifat kesimpulan yang dihasilkannya, logika pada umumnya dibedakan antara logika deduktif dan logika induktif. Kedua bentuk logika ini sering dinyatakan deduktif adalah dari umum ke khusus dan induktif dari khusus ke umum. Hal seperti ini tidak tepat karena deduktif belum tentu dari umum ke khusus, dapat juga dari umum ke umum. Perbedaan pokok antara keduanya adalah terletak pada sifat kesimpulannya. Logika deduktif sifat kesimpulannya pasti, sedang logika induktif sifat kesimpulannya boleh jadi atau bersifat kemungkinan.
Logika deduktif adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah berdasarkan bentuknya serta kesimpulan yang dihasilkan sebagai kemestian diturunkan dari pangkal-pikirnya. Dalam logika ini yang terutama ditelaah adalah bentuk dari kerjanya akal jika telah runtut dan sesuai dengan pertimbangan akal yang dapat dibuktikan tidak ada kesimpulan lain maka proses penyimpulannya adalah tepat dan sah. Misal :
Logam dipanaskan memuai
Emas adalah logam
Maka emas dipanaskan memuai.
Contoh diatas berpangkal dari pernyataan yang sudah dianggap benar sebagai titik tolak penalaran, yaitu "logam dipanaskan memuai". Kemudian pernyataan kedua merupakan sesuatu bagian dari logam yaitu emas sehingga dirumuskan "emas adalah logam". Pernyataaan ketiga merupakan kesimpulan yang dapat ditarik dari hubungan dua pernyataan tersebut, yaitu "emas dipanaskan memuai".
Bentuk dalam pernyataan yang dimaksudkan adalah bentuk logika, yaitu struktur dari suatu pernyataan meskipun berbeda materinya dapat juga struktur logikanya sama, misal beberapa pernyataan berikut :
Bangsa Indonesia berketuhanan Yang Maha Esa.
Semua manusia berakal budi
Setiap warga negara sama kedudukannya dalam pemerintahan
Indonesia adalah negara berdasar atas hukum.
Kesimpulan pernyataan di atas materinya tidak akan sama, akan tetapi struktur logikanya adalah sama, yaitu :
" Bangsa Indonesia BerkeTuhanan Yang Maha Esa", diabstraksikan menjadi "semua A adalah B". "Semua manusia berakal budi", diabstraksikan juga "semua A adalah B', "Setiap warga negara sama kedudukannya dalam pemerintahan", diabstraksikan juga sama "semua A adalah B", "Indonesia adalah negara berdasar atas hukum", diabstraksikan juga sama yaitu "semua A adalah B".
Berdasarkan struktur logika sebagaimana diuraikan tersebut maka contoh penalaran deduktif di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :
Semua B adalah C
Semua A adalah B
Maka semua A adalah C.
Logika deduktif karena berbicara tentang hubungan bentuk-bentuk pernyataan saja yang utama terlepas isi apa yang diuraikan maka logika deduktif sering disebut pula logika formal. Sering juga hanya disebut dengan logika, Jadi, jika hanya logika berarti logika deduktif atau logika formal.
logika induktif adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Logika ini sering disebut juga logika material, yaitu berusaha menemukan prinsip-prinsip penalaran yang bergantung kesesuaiannyadengan kenyataan, oleh karena itu kesimpulannya hanyalah kebolehjadian, dalam arti selama kesimpulannya itu tidak ada bukti yang menyangkalnya maka kesimpulan itu benar, dan tidak dapat dikatakan pasti, Misal :
Emas adalah logam, besi adalah logam, perak adalah logam.
Emas besi dan perak dipanaskan memuai
Maka logam dipanaskan memuai
Contoh tersebut berpangkal pada sejumlah hal khusus, yaitu dari tiga materi yang berupa logam, besi, dan perak. Oleh karena berpangkal pada materi maka tepat jika disebut dengan logika material dan kesimpulannya bersifat kemungkinan atau kebolehjadian, boleh jadi benar boleh jadi tidak benar.
Logika induktif merupakan pokok bahasan metodologi ilmiah, atau dengan kata lain metodologi ilmiah merupakan perluasan dari logika induktif sehingga logika induktif disebut juga "Metode-metode ilmiah".
Keseluruhan modul logika ini termasuk logika deduktif yang menggabungkan antara pola penalaran logika selogistik dan logika simbolik secara praktis sehingga dapat disebut dengan "Logika Praktis", yaitu terdiri atas tiga bagian, yaitu Unsur-unsur penalaran, Penalaran kategori, dan penalaran majemuk.
Ketiga bagian logika praktis ini membahas penalaran khusus mengenai penyimpulan yang memperhatikan ketepatan bentuk sesuai dengan isi. Jadi bukan hanya berbicara tentang bentuk-bentuk saja. Dengan demikian, Logika Praktis didefinisikan :
"Teori tentang prinsip-prinsip serta metode-metode penyimpulan yang sah dengan memperhatikan kesesuaian bentuk dan isi"
Logika praktis lebih banyak uraiannya tentang hal-hal sebagai sarana ilmu secara umum bukan hanya bermain simbol-simbol saja sehingga semua pembahasannya selalu didasarkan atas pembuktian dengan diagram himpunan, yang sesuai dengan kenyataan dalam penerapannya.
KEGIATAN BELAJAR 2 :
BAHASA DAN LOGIKA
Berpikir sebagai proses bekerjanya akal dalam menelaah sesuatu merupakan ciri hakiki dari manusia dan hasil bekerjanya akal ini tidak dapat diketahui oleh orang lain jika tidak dinyatakan dalam bentuk bahasa,
Bahasa adalah sistem lambang bunyi berartikulasi yang bersifat sewenang-wenang dan konvensional yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk melahirkan perasaan dan pikiran (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Secara sederhana Bahasa adalah merupakan pernyataan pikiran atau perasaan sebagai alat komunikasi manusia.
Bahasa pada dasarnya terdiri dari kata-kata atau istilah-istilah dan sintaksis. Kata atau istilah merupakan simbol dari arti sesuatu, dapat juga berupa benda-benda, kejadian-kejadian, proses-proses atau juga hubungan-hubungan. Sedangkan sintaksis adalah cara untuk menyusun karta-kata atau istilah di dalam kalimat untuk menyatakan arti yang bermakna. Dengan dasar penjelasan sintaksis ini berarti kalimat secara garis besar dibedakan dua macam, yaitu kalimat bermakna dan tidak bermakna.
Kalimat bermakna dibedakan antara kalimat berita dan bukan kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang dapat dinilai benar atau salah, sedangkan kalimat bukan berita ada empat macam yakni kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat seru, dan kalimat harapan.
Dari beberapa bentuk kalimat di atas yang disebut sebagai Bahasa Ilmiah ialah Kalimat berita yang merupakan suatu pernyataan-pernyataan atau pendapat-pendapat. Untuk menelaah bahasa ilmiah perlu dijelaskan tentang penggolongan bahasa dan bagaimana cara menjelaskan istilah-istilah dalam bahasa ilmiah.
A. PENGGOLONGAN BAHASA
Bahasa merupakan alat yang tepat untuk menyatakan pikiran atau perasaan. Oleh karena itu, bahasa merupakan alat terpokok dalam hubungan antar manusia. Bahasa sangat penting juga dalam pembentukan penalaran ilmiah karena penalaran ilmiah mempelajari bagaimana caranya mengadakan uraian yang tepat sesuai dengan pembuktian-pembuktian secara korek dan jelas. Dalam penelaahan bahasa dibedakan antara bahasa alami dan bahasa buatan.
Bahasa Alami adalah bahasa sehari-hari yang biasa digunakan untuk menyatakan sesuatu, yang tumbuh atas dasar pengaruh alam sekelilingnya. Bahasa alami dibedakan dua macam yaitu bahasa isyarata dan bahasa biasa.
1. Bahasa Isyarat; dapat berlaku umum dan dapat pula berlaku khusus. Misalnya, berlaku umum menggelengkan kepala tanda tidak setuju, mengangguk tanda setuju, hal ini tanpa ada persetujuan dapat dimengerti secara umum. Berlaku khusus adalah untuk kelompok tertentu dengan isyarat tertentu pula.
2. Bahasa biasa; bahasa yang dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari. Simbol sebagai pengandung arti dalam bahasa biasa disebut "kata", sedangkan arti yang dikandungnya disebut "makna". Dalam bahasa biasa pemakaian kata dibedakan antara dua hal, yaitu sebagai berikut :
a. Kata tertentu "mengartikan" sesuatu hal sebebanarnya, misal kata "puncak" dalam kalimat : puncak gunung merapi tertutup lahar.
b. Dengan pemakaian (penerapan) kata tertentu, memaksudkan sesuatu lain, atau disebut "arti kiasan", misal kata "puncak" dalam kalimat : Suharto adalah puncak kewibawaan orde baru dalam Negara Indonesia.
Bahasa Buatan adalah bahasa yang disusun sedemikian rupa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akal pikiran untuk maksud tertentu. Kata dalam bahasa buatan disebut "istilah", sedangkan arti yang dikandung istilah disebut "konsep". Bahasa Buatan dibedakan atas dua macam, yakni : Bahasa Istilah dan Bahasa Artifisial
1. Bahasa Istilah ; Bahasa ini rumusannya diambilkan dari bahasa biasa yang diberi arti tertentu, misalnya demokrasi (demos dan kratein), medan, daya, massa (dalam fisika). Dalam bahasa ini, ada sedikit kekaburan. Oleh karena itu, definisi diperlukan untuk menjelaskan arti yang dimaksud.
2. Bahasa Artifisial ; adalah murni bahasa buatan atau sering juga disebut dengan bahasa simbolik; bahasa berupa simbol-simbol sebagaimana yang digunakan dalam logika mayupun matematika. Dalam bahasa ini, tidak ada bentuk kiasan yang mengaburkan, misalnya : [((a = b) ^ (b = c)) ==> (a = c)], [((p ==>q) ^ p) ==> q], bahasa artifisial mempunyai dua macam ciri khusus :
a. Tidak berfungsi sendiri, kosong dari arti, oleh karena itu dapat dimasuki arti apa pun juga.
b. Arti yang dimaksudkan dalam bahasa artifisial ditentukan oleh hubungannya.
Perbedaan antara bahasa alami dan bahasa buatan ialah isi konseptual dalam istilah tertentu lebih sewenang-wenang, sekehendak hati (arbitrer), sedangkan makna dari kata biasa bersifat kebiasaan sehari-hari maka makna tidak perlu didefinisikan. Perbedaan selengkapnya sebagai berikut :
Bahasa Alami :
Antara kata dan makna merupakan suatu kesatuan utuh, atas dasar kebiasaan sehari-hari karena bahasanya :
- Secara spontan
- Bersifat kebiasaan
- Intutif (bisikan hati)
- Pernyataan secara langsung
Bahasa Buatan :
Antara istilah dan konsep merupakan satu kesatuan yang bersifat relatif karena bahasanya :
- Secara spontan
- Sekehendak hati
- Diskursif (tidak berhubungan)
- Pernyataan tidak langsung
Dari uraian tentang bahasa diatas, bahasa buatan inilah yang dimaksudkan bahasa ilmiah, dengan demikian bahasa ilmiah dapat dirumuskan sebagai berikut :
Bahasa buatan yang diciptakan oleh para ahli dalam bidangnya dengan menggunakan istilah-istilah atau lambang-lambang untuk mewakili pengertian-pengertian tertentu.
Bahasa ilmiah ini pada dasarnya merupakan kalimat-kalimat deklaratif atau suatu pernyataan yang dapat dinilai benar atau salah, baik menggunkan bahasa biasa sebagai bahasa pengantar untuk mengomunikasikan karya ilmiah maupun menggunakan istilah-istilah serta simbol-simbol secara abstrak.
Khusus untuk logika supaya uraian penalarannya lebih praktis dan mudah dipahami digunakan bahasa artifisial atau bahasa simbolik, untuk mengabstraksikan semua konsep yang ada dan terlepas dari bahasa kiasan. Logika yang khusus menggunakan bahasa simbolik disebut logika simbolik. Adapun logika yang diuraikan dalam modul logika ini disamping menggunakan bahasa simbolik juga digunakan bahasa biasa untuk sebagai contoh-contoh penalaran serta menggunakan diagram-diagram himpunan sebagai pembuktiannya, belum sampai ke logika simbolik.
B. FUNGSI BAHASA
Bahasa pada dasarnya merupakan pernyataan pikiran atau perasaan sebagai alat komunikasi manusia. Sebagai pernyataan pikiran atau perasaan dan juga sebagai alat komunikasi manusia maka bahasa mempunyai tiga fungsi pokok, yakni fungsi ekspresif atau emotif, fungsi efektif atau praktis, dan fungsi simbolik dan logika. Ketiga fungsi ini diuraikan sebagai berikut :
Fungsi ekspresif atau emotif; tampak pada pencurahan rasa takut serta takjub yang dilakukan serta merta pada pemujaan-pemujaan, demikian juga pencurahan seni suara maupun seni sastra.
Fungsi efektif atau praktis; tampak jelas untuk menimbulkan efek psikologis terhadap orang lain dan sebagai akibatnya memengaruhi tindakan-tindakan mereka ke arah kegiatan atau sikap tertentu yang dinginkan.
Fungsi simbolik; dipandang dalam artinya yang luas, meliputi juga fungsi logik serta komunikatif karena arti itu dinyatakan dalam simbol-simbol bukan hanya untuk menyataklan fakta saja melainkan juga untuk menyampaikan kepada orang lain.
Di antara tiga fungsi bahasa diatas, khusus untuk logika dan juga untuk bahasa ilmiah yang harus diperhatikan adalah fungsi simbolik karena komunikasi ilmiah bertujuan untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan. Agar komunikasi ilmiah ini berjalan dengan baik maka bahasa yang dipergunakan harus logika terbebas dari unsur-unsur emotif.
Komunikasi ilmiah harus bersifat reproduktif, artinya apabila si pengirim komunikasi menyampaikan suatu informasi yang katakanlah x maka si penerima komunikasi komunikasi harus menerima informasi yang berupa x pula, dan jika membutuhkan penalaran juga harus logika. Informasi x yang diterima harus merupakan reproduksi yang benar-benar sama dari informasi x yang dikirimkan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah apa yang dinamakan sebagai suatu salah informasi, yakni suatu proses komunikasi yang mengakibatkan penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan, di mana suatu informasi yang berbeda akan menghasilkan proses berpikir yang berbeda pula. Oleh sebab itu, proses komunikasi ilmiah harus bersifat jelas dan objektif serta logika, yakni terbebas dari unsur-unsur emotif.
Dalam komunikasi ilmiah harus jelas dan objektif. Oleh karena itu, istilah-istilah yang digunakan harus didefinisikan untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh istilah tersebut. Hal ini harus dilakukan untuk mencegah si penerima komunikasi memberi makna lain yang berbeda dengan makna yang dimaksudkan oleh si pemberi informasi, leboh-lebih istilah-istilah yang diangkat dari bahasa biasa ke bahasa ilmiah.
Untuk memberi definisi atau penjelasan yang baik harus jelas dan singkat, serta mudah dipahami, tidak menggunakan bahasa yang berbelit-belit. Oleh karena itu, perlu juga diuraikan bagaimana cara membuat definisi serta macam-macam definisi, dan juga syarat-syarat apa yang harus diikuti supaya definisinya baik.
Mengadakan uraian dengan menunjukkan definisi dalam bidang ilmiah adalah perlu, tidak berarti berlebih-lebihan karena memang penjelasan atau definisi dibutuhkan supaya tidak terjadi suatu salah informasi. Untuk bahasa biasa hal tersebut tidak perlu karena dalam bahasa biasa antara kata dan makna merupakan kesatuan utuh atas dasar kebiasaan sehari-hari.
Definisi adalah sangat penting dalam ilmu, sesuai dengan hakikat ilmu itu sendiri. Ilmu adalah bentuk pengetahuan yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu dan telah ditentukan batas-batasannya sehingga jelas batas antara ilmu satu dengan ilmu yang lain.
Ilmu memburuhkan formalisasi atau bahasa formal yang khas. Maksud dari formalisasi adalah untuk menyederhanakan hingga semua lebih skematis, lebih jelas meskipun menjadi lebih abstrak.
C. BAHASA DALAM LOGIKA
Pemikiran manusia dapat diungkapkan dalam bentuk bahasa, meskipun tidak semua yang terpikirkan manusia dapat diungkapkan dengan tuntas. Dalam penalaran yang merupakan salah satu wujud pemikiran, bahasa merupakan bentuk yang tepat untuk menunjukkan langkah-langkah yang harus dilalui dalam penalaran itu. Bahasa ini terdiri atas kata-kata dan sintaksis.
Kata-kata merupakan simbol-simbol dari arti, dan dapat menjadi hubungan. Sintaksis adalah cara untuk menyusun kata-kata dalam bentuk kalimat untuk menyatakan arti yang bermakna.
Berdasarkan pengertian sintaksis di atas mengandaikan juga bahwa kalimat itu ada yang bermakna dan ada juga yang tidak bermakna atau berarti dan tidak berarti. Selanjutnya, dapat diuraikan lagi bahwa kalimat yang bermakna itu dibedakan antara lima jenis yakni sebagai berikut :
Kalimat Berita
Kalimat Pertanyaan
Kalimat Perintah
Kalimat Seru
Kalimat Harapan.
Di antara lima jenis kalimat ini yang digunakan dalam logika adalah kalimat berita, karena kalimat berita dapat dinilai benar atau salah, sedang jenis-jenis kalimat yang lain tidak dapat dinilai benar atau salah.
Kalimat berita atau disebut juga dengan kalimat deklaratif di dalam logika dinamakan pernyataan. Penilaian benar atau salah dalam pernyatan atau kalimat deklaratif dihubungkan dengan situasi yang ditunjuk, jika sesuai berarti benar dan jika tidak sesuai berarti salah.
Disamping itu ada juga penilaian benar atau salah dalam logika didasarkan atas pertimbangan akal. Uraian tentang kalimat dan pernyataan ini lebih jelasnya lihat pada skema pembagian kalimat :
Penilaian benar atau salah dalam pernyataan, keduanya berbalikan penuh, dalam arti benar adalah tidak salah (B = ~S) atau salah adalah tidak benar (S = ~B), tidak mungkin setengah benar atau setengah salah. Misalnya, pernyataan berikut ini :
Semua rakyat Indonesia berkeTuhanan Yang Maha Esa;
Indonesia adalah negara berdasar atas hukum;
Ada mahasiswa Universitas Terbuka tidak rajin belajar.
Contoh pertama jika terbukti "semua berketuhana Yang Maha Esa" dinyatakan benar dan jika "ada salah satu rakyat Indonesia yang tidak berkeTuhanan Yang Maha Esa", bukan berarti setengah benar akan tetapi pernyataan tersebut adalah salah.
Pernyataan atau kalimat deklaratif jika ditinjau berdasarkan isinya dapat dibedakan menjadi dua macam , yaitu pernyataan analitik dan pernyataan sintetik.
1. Pernyataan analitik; ialah suatu kalimat deklaratif yang predikatnya telah terkandung dalam subjek, yakni isinya hanya menyajikan arti yang memang telah terkandung dalam suatu pengertian dari subjek, pernyataan analitik ini selalu benar, misalnya semua lingkaran adalah bulat.
2. Pernyataan sintetik; ialah suatu kalimat deklaratif yang predikatnya tidak terkandung dalam subjek, yakni predikatnya menyatakan sesuatu tentang subjek pernyataan, artinya tidak terkandung pada subjek, pernyataan sintetik ini belum tentu benar, misalnya anak itu terpelajar.
Pernyataan (statement) dalam logika ditinjau dari segi bentuk hubungan makna yang dikandungnya, pernyataan itu disamakan juga dengan proposisi, walaupun ada sedikit perbedaan namun pada umumnya sama. Oleh karena itu, dalam logika kedua istilah itu tidak dibedakan. Proposisi adalah rangkaian pengertian, dan Pernyataan adalah rangkaian kata-kata. Dalam logika, pengertian hanya terdapat dalam proposisi sehingga Proposisi adalah makna yang dimaksud oleh suatu pernyataan yang dapat dinilai benar atau salah. Proposisi atau pernyatan ini berdasarkan bentuk isinya dibedakan antara tiga macam, yakni proposisi tunggal, proposisi kategori, dan proposisi majemuk.
1. Proposisi tunggal; ialah pernyataan sederhana yang hanya terdiri atas satu konsep atau satu pengertian sebagai unsurnya.
Misal : Sekarang hari Minggu,
Indonesia merdeka,
Semua peserta kuliah logika,
Kebudayaan nasional,
Kesenian Indonesia modern,
Semua rakyat Indonesia.
2. Proposisi kategori; ialah pernyataan yang terdiri atas hubungan dua konsep sebagai subjek dan predikat
Misal : Bangsa Indonesia berKetuhanan Yang Maha Esa,
Rakyat Indonesia tidak boleh mengikuti ajaran komunis,
Sebagian rakyat Indonesia keturunan asing,
Ada mahasiswa Universitas Terbuka tidak belajar logika,
Ideologi komunis adalah tidka fleksibel,
Semua peserta kursus logika mendapat sertifikat.
3. Proposisi majemuk; ialah pernyataan yang terdiri atas hubungan dua bagia yang dapat dinilai benar atau salah
Misal : Barang siapa memalsu uang atau menyimpan uang palsu akan dituntut di muka Hakim,
Bung Karno adalah seorang proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia,
Barangsiapa menggelapkan uang negara diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun,
Koento Wibisono adalah guru besar universitas Gadjah Mada yang pernah menjabat rektor
Universitas Sebelas Maret.
Tiga macam proposisi atau pernyataan diatas yang sebagai dasar penalaran adalah proposisi kategori untuk penalaran kategori dan proposisi majemuk untuk penalaran majemuk. Adapun proposisi tunggal atau proposisi simpel hanya merupakan bagian dari proposisi majemuk, tidak dapat diadakan penalaran secara terperinci, hanya dalam pengolahan sederhana, seperti negasi, misalnya "ini buku logika" dinegasikan menjadi "ini bukan buku logika". Disamping itu juga diadakah pengolahan pernyataan tunggal, yakni dalam penalaran kategori, yang sifat penalarannya sederhana sekali. Jadi, propoisisi tunggal ini pengolahannya dapat masuk dalam penalaran kategori dan dapat juga masuk dalam penalaran majemuk, tidak dibahas dalam bentuk penalaran tersendiri.
KEGIATAN BELAJAR 3 :
SEJARAH PERKEMBANGAN LOGIKA
Logika sebagai teori berpikir pertama kalai dipelajari dan dikembangkan oleh ahli pikir Yunani yang bersifat tradisional atau penalarannya bersifat selogistik, sebagai suatu teori kemudian masuk ke dunia Arab pada zaman Islam.
Di dunia Arab, teori berpikir dipelajari juga dan dikembangkan sehingga terkenal dengan nama ilmu mantiq. Kemudian logika dikembangkan di barat sampai puncaknya yang terkenal dengan nama logika simbolik. Logika di Indonesia pertama kali yang masuk adalah dari dunia Arab yang dipelajari di pesantren-pesantren atau madrasah-madrasah.
A. ALAM PIKIRAN YUNANI
Logika pada awal pertumbuhannya adalah dirumuskan dan dikembangkan oleh ahli pikir Yunani. Penyusun logika pertama adalah Aristoteles (384 - 322 SM), sebagai sebuah ilmu tentang hukum-hukum berpikir guna memelihara jalan pikiran dari setiap kesalahan. Logika yang dimaksudkan di sini untuk membimbing dan menuntun seseorang supaya berpikir teliti.
1. Buah Karya Aristoteles
Aristoteles merupakan ahli pikir Yunani yang terbesar, yang memperoleh gelar Guru-Pertama dalam dunia ilmu pengetahuan sampai masa kini. Keistimewaan yang terutama dan terbesar sekali dari Aristoteles ialah, bahwa tanpa ada yang mendahuluinya dan hampir seluruhnya bergantung oleh kekuatan pemikirannya.
Ia menciptakan logika sebagai ilmu baru pada waktu itu, yang disebut dengan nama "analitika" dan "dialektika" . Analitika untuk memberi nama sistem penalaran yang bertitik tolak dari pernyataan yang sudah dianggap benar, sedangkan dialektika untuk memberi nama sistem penalaran yang bertitik tolak dari pernyataan yang belum tentu benar.
Kumpulan karya tulis Aristoteles mengenai logika terdiri atas lima buku, dan buku ketiga terbagi atas dua bagian sehingga semua terdiri atas enam bagian. Oleh murid-muridnya pada masa belakangan digabungkan menjadi satu dan diberi nama Organon. Enam bagian tersebut terdiri atas berikut ini :
1. Categoriae; berisikan penambahan tentang cara menguraikan sesuatu objek dari sepuluh kategori (pengertian umum)
2. De Interpretatione; berisikan pembahasan bentuk-bentuk pernyataan dan penyimpulan langsung, bagian ini biasa disebut Perihermenias.
3. Analytica Priora; berisikan pembahasan tentang bentuk-bentuk silogisme atau susunan pikir yang dipergunakan dalam penalaran.
4. Analytica Posteriora; berisikan pembahasan tentang pelaksanaan dan penerapan pemikiran silogistik dalam pembuktian ilmiah
5. Topica; berisikan pembahasan tentang perbincangan yang berdasarkan pada premis-premis yang boleh jadi benar
6. Sophistict Elenchi; berisikan pembahasan tentang sifat dasar dan penggolongan sesat pikir.
Itulah enam bagian karya tulis Aristoteles mengenai logika, dan dengan karya tulis tersebut, Aristoteles telah menemukan dan menyusun sesuatu yang terpandang amat besar gunanya bagi menuntun cara menalar yang runut.
2. Sumbangan Theoprastus
Seorang murid Aristoteles yang terbesar dalam bidang logika ialah Theoprastus (371-287 SM), yang menggantikannya mengepalai aliran Peripatetik dan berjasa di dalam penyempurnaan logika yang diwariskan oleh gurunya.
Sumbangan Theoprastus yang terbesar ialah penafsirannya tentang pengertian yang mungkin dan juga tentang sebuah sifat asasi dari setiap kesimpulan. Pengertian yang mungkin menurut tafsirannya ialah "yang tidak mengandung kontradiksi di dalam dirinya" dan setiap kesimpulan menurut asas yang dirumuskannya, mestilah mengikuti unsur terlemah dalam pangkal-pikir.
3. Kaum Stoik dan Megaria
Logika kemudian mencapai puncaknya pada tulisan-tulisan kaum Stoik dan Megaria. Aliran Megaria ini didirikan mula-mula oleh Euclid, salah seorang murid Sokrates, hidup pada abad ke-3 SM. Di antara muridnya yang terkenal ialah Eubulides yang melahirkan Liar Pradox (Paradox si Pembohong) di dalam logika dan Ichtyas yang menggantikan Euclid mengepalai aliran Megaria, serta Trasymachus dan Korinte yang menjadi guru Stilpo. Salah seorang murid yang termasyur dari Stilpo ialah Zeno (350-260 SM), pembangunan aliran Stoik.
Penyambung aliran Zeno yang teramat harum namanya sampai kini ialah Clenthes (abad ke-3 SM) dan Chrysippus (280-206 SM). Chrysippus adalah seorang ahli logika yang teramat tajam dan teramat produktif sehingga ada pemeo "jika Chrysippus tidak ada niscaya kaum Stoa akan tidak ada.
Para komentator lainnya dalam bidang logika pada tingkatan masa ini ialah Appolinus Cronus, Diodorus Cronus, dan Philo. Philo adalah seorang ahli pikir Yahudi di Iskandariah pada awal abad masehi teramat harum namanya, diantaranya Sextus Empricus, Diogenes Laertius, Cicero (106-43 SM), Gellius, Galenus (130-200 M), Lucius Apuleus (abad ke-2 M), Origen, Proclus, Stobaeus, Epictetus (awal abad masehi), Seneca (meninggal tahun 65 M), dan beberapa ahli pikir lainnya.
Pada masa ini logika lebih banyak mengarah kepada pembahasan susun kata sebagai penjelmaan pikiran dan masalah yang terhangat pada tingkat masa ini ialah masalah-masalah Paradox. Mengenai Paradox saja Chrysippus konon menyususn 28 buku, dan Philetos dari Cos sampai mendadak meninggal dunia karena siang malam terlampau memikirkan penyelesaian masalah-masalah paradox. Paradox yang termasyhur sekali pada masa itu ialah Liar Paradox yang dilahirkan mula-mula oleh Eubulides.
4. Sumbangan Porphyrius
Porphyrius (233-306 M), seorang ahli pikir di Iskandariah yang amat terkenal dalam bidang logika, ia tercatat jasanya menambahkan satu bagian baru dalam pelajaran logika. Bagian baru ini disebut Eisagoge, yakni sebagai pengantar Categoriae. Dalam bagian baru ini, dibahas lingkungan-lingkungan zat dan lingkungan-lingkungan sifat di dalam alam yang biasa disebut dengan klasifikasi.
Pada masa Porphyrius alam pikiran Yunani (Grik) telah memperoleh pusat perkembangannya pada empat tempat ytiu, Athena, Iskandariah, Antiokia, dan Roma.
5. Sidang Besar Nicae
Konstantin (272-337 M) Kaisar Romawi yang pertama-tama memeluk agama Nasrani dan berkuasa sampai tahun 337 M, dan memindahkan ibukota dari Roma ke Konstantinopel. Pada tahun 325 M berlangsung Sidang Besar Gereja di Nicae, yang merupakan sidang gereja pertama-tama di dunia, dihadiri oleh para Bishop dan Patriarch atas undangan Kaisar Konstantin.
Sidang Besar ini bertujuan menyelesaikan pertentangan-pertentangan pendirian dan keyakinan di dalam dunia Kristen. Pertentangan keyakinan terhebat masa itu ialah antara aliran Arius dan Iskandariah yang berpendirian bahwa Yesus memiliki zat yang berbeda dari zat Tuhan (heter-ousius) dan aliran Alexander dari Konstantinopel yang berpendirian bahwa kedua-duanya memiliki zat yang serupa (homo-ousius).
Selain penyelesaian pertentangan, dalam sidang Besar Nicae memutuskan juga penghapusan beratus-ratus ragam injil yang tersebar masa itu dan meresmikan empat injil saja (Matius, Lukas, Markusm Yahya) ditambah dengan Kisah Rasul-Rasul. Disamping itu, keputusan yang lain lagi ialah menghapuskan pelajaran alam pikiran Yunani pada dua pusat, yaitu Athena dan Antiokia. Pusatnya di Iskandariah diberikan kelonggaran karena di situ lebih berpengaruh filsafat Plotinus (204-270 M) yang kira-kira dapat sesuai dengan ajaran Nasrani, dan filsafat plotinus ini lebih terkenal dengan sebutan Neo-Platonism.
Kemudian keputusan yang lain lagi ialah membatasi pelajaran logika hanya sampai bagian Perihermenias saja dan bagian-bagian selanjutnya dinyatakan "bab-bab terlarang".
6. Komentator Terakhir di Roma
Putusan Sidang Besar Nicae itu sangat hebat pukulannya bagi alam pikiran Yunani dan bagi Logika. Komentator terakhir dalam bidang Logika pada masa itu bernama Manlius Severinus Boethius (480-524 M) yang juga terpandang ahli pikir Roma terakhir. Ia menyalin Logika dari bahasa Grik ke dalam bahasa Latin, dan itulah buku logika yang pertama-tama berbahasa Latin dan di dalamnya termasuk sebagian dari "bab-bab terlarang". Boethius ini kemudian dijatuhi hukuman mati pada tahun 524 M. Dengan kematian Boethius turut mati dan padam pula pelajaran logika di dunia Barat dalam masa lebih seribu tgahun lamanya. Masa yang panjang ini terkenal di Barat dengan sebutan Zaman Gelap atau Dark Ages.
B. LOGIKA PADA ZAMAN ISLAM
Pada awal abad ke-7 masehi agama Islam lahir dan menjelang penghujung adab ke-8 kekuasaan Islam sudah terbentang sejak dari pegunungan Pirenia di Barat sampai ke perbatasan Tiongkok di Timur. Pada pertengahan abad ke-8 itu bermula kegiatan penyalinan buku-buku Grik Tua dan Parsi serta Sanskrit ke dalam Bahasa Arab, terutama pada masa Khalif Al-Makmun dari dinasti Abbasiah di Bagdad, dan Khalif Abdul-Rahman dari dinasti Umaiyah di Cordova. Perkembangan ilmu dan filsafat masa itu mencapai zaman gemilang pada dua pusat, Bagdad di Timur dan Cordova di Barat.
1. Penyalinan Buku-Buku Logika
Penyalinan yang pertama-tama mengenai logika dilakukan oleh Johana bin Patrik (lahir 815 M) bernama Kategori karangan Aristo (Maqulatul-Asyrat li-Aristu). Lalu disusul oleh penyalinan bagian-bagian lainnya oleh berbagai penulis. Ibnu Sikkit Jakub Al-Nahwi (803-859 M) memberi komentar dan beberapa tambahan didalam bukunya Perbaikan dalam Logika (Ishlah fil=Manthiqi). Jakub bin Ishak Al-Kindi (791-863 M) menyalin bagian-bagian logika dan memberi komnetar satu per satu. Penyalinan bagian-bagian logika dibelahan Timur ini pada masa itu belum melampaui "bab-bab terlarang" yang berlaku dalam dunia Kristen.
Penyalinan-penyalinan logika di belahan Barat telah lebih jauh dari bagian-bagian yang terpandang "bab-bab terlarang", Ishak bib Hunain (meninggal 911 M) menyalin Categoriae dan De Interpretatione bernama Maqulat li-Aristu dan Kitabu Aristhathalis: Bari-arminus. Said bin Jakub Al-Dimsyiki (meninggal 914 M) menyalin Eisagoge dan Topica bernama Isaguji wa Tupiqa Aristu. Abubisyri Matta Al-Mantiqi (meninggal 940 M) menyalin Analytica, yang tadinya disalin ke dalam bahasa Siryani oleh Ishak bin Hunain, bernama Kitabul-Nurhan.
Penyalinan pada masa itu masih bagian demi bagian. Kelemahan lainnya lagi ialah penggunaan istilah-istilah pada setiap penyalinan itu sering kali kurang cermat. Kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan ini diperbaiki dan disempurnakan oleh Abu-Nasar Muhammad bin Muhammad bin Ozluq bin Thurchan Al-Farabi (873-950 M) yang terkenal mahir dalam bahasa Grik-Tua.
Al Farabi menyalin seluruh karya tulis Aristoteles dalam berbagai bidang ilmu dan karya tulis ahli-ahli pikir Grik lainnya. Al-Farabi ini pada masa-masa kebangunan kembali Eropa dikenal dengan gelar Guru-Kedua karena ulasang-ulasannya atas setiap buah tangan Aristoteles. Karya tulis Al-Farabi dalam bidang logika ada empat buku yaitu sebagai berikut :
a. Kutubul Manthiqil-Tsamaniyat;
Menyalin dan memberi komentar atas tujuh bagian logika dan menambahkan satu bagian baru sehingga menjadi delapan bagian.
b. Muqaddamat Isaquji Allati Wadha'aha Purpurius;
Memberikan komentar atas bagian klasifikasi yang diciptakan oleh Porphyrius.
c. Risalat fil-Manthiqi, al-qaulu fi Syaraitil-yaqini;
Membahas tentang beberapa bagian logika terutama tentang kontradiksi dan merumuskan syarat-syarat kontradiksi.
d. Risalat fil-Qias, fushulun yuhtajju ilaiha fi Shina'atil-manthiqi;
Membahas tentang bentuk-bentuk silogisme dan merumuskan syarat-syarat setiap bentuk berdasarkan hukum Aristoteles.
Tokoh logika yang lain pada masa ini ialah Abu Abdillah Al-Khwarizmi (meninggal 997 M), yang dipandang penyususn dan pencipta Aljabar, memberi komentar lagi atas keseluruhan logika dalam bukunya yang bernama Mafatihul-Ulum fil-Manthiqi.
Komentar logika yang lain ialah Abu Ali Al-Husain bin Abdillah Ibnu Sina (980-1037 M). Ibnu Sina banyak memberi komentar atas karya tulis Al-Farabi, Aristoteles, Plato, Hyppocrate, Euclid. Bukunya yang bernama Kitabul-Syiffa terpandang semacam ensiklopedia terdiri atas 18 jilid tebal, naskah tersimpan di perpustakaan Oxford, telah berkali-kali dicetak dalam bahasa latin, diantaranya cetakan tahun 1495 M di Venezia. Salah satu bagian dari buku raksasa ini adalah pembahasan tentang logika.
Di balik itu, ada lagi karya tulis Ibnu Sina yang khusus mengenai Logika bernama Isyarat wal Tanbihat fil-Manthiqi dan bukunya ini disalin oleh Napier ke dalam Bahasa Prancis pada tahun 1658 M, dan sebagai akibat penyalinan ini lahir logika aliran Port Royal di Kota Paris, yang menjadi standar pelajaran logika di Barat sejak abad ke-17.
Abu Ali Muhammad bin Hasan bin Al-Haitsam (965-1039 M), yang di Eropa dikenal dengan sebutan Al-Hazem, menulis dua byuku mengenai logika, yaitu sebagai berikut :
a. Talchisu Muqaddamati Purpurius wa Kutubi Aristhathalis
b. Muchtasharul Manthiqi
Literatur logika ini berkembang terus di tangan komentator-komentator lainnya, seperti Al-Ghazali (1059-1111M), Al-Tibrizi (meninggal 1109 M), Ibnu Bajah atau Avempas (1100-1138 M), Ibnu Rasyid atau Averroes (1126-1198 M), Al-Sakkaqi (meninggal 1228 M), Al-Asmawi (1198 - 1283 M), Al-Samarkandi (meninggal 1291 M), dan Al-Abhari (meninggal 1296 M).
2. Logika pada Masa Kemunduran Islam
Menjelang abad ke-14 sebetulnya sudah ada reaksi-reaksi terhadap pelajaran logika karena dipandang terlampau memuji akal di dalam mencari kebenaran sehingga melahirkan paham-paham yang ekstrim, disusul dengan tuduhan-tuduhan zindiq dan ilhad dan kufur terhadap penganut paham-paham tersebut.
Reaksi ini baru mencapai puncaknya pada abad ke-14, seiring dengan kemunduran kekuasaan Islam, dan pada masa inilah Taqiuddin Ahmad Ibnu Taimiah (1263-1328 M) menentang pelajaran logika dengan sengit dan mengarang buku bernama Fashihtu ahlil-Imam fil-raddi 'ala Manthiqil Yunani (ketangkasan pendukung Keimanan menangkis logika Yunani). Hal ini disusul oleh karya tulis Saaduddin Al-Taftazani (1322-1389 M) dengan bukunya bernama Tahzibul-Manthiqi wal-Qalam, dan di dalam bukunya ini ia menjatuhkan hukum haram bagi mempelajari logika.
Menjelang penghujung abad ke-14 itu kegiatan ilmiah mulai padam, sejalan dengan terhentinya kegiatan pembahasan logika, ditambah pula oleh jatuhnya Andalusia ke tangan Ferdinand dan Isabella pada pertengahan abad ke-15. Semenjak saat itu sampai menjelang awal abad ke-20 hanya beberapa biji buku saja pernah lahir yang dapat dikatakan berarti. Ibnu Kaldun (1332-1406 M) menyiarkan dasar-dasar logika bernama Al-manthiq termuat dalam bukunya Muqaddamah yang terkenal itu.
Muhammad Al-Duwani (lahir 1428 M) memberi komentar tentang premis mayor dan premis minor, yakni pangkal-pikir besar dan pangkal-pikir kecil, di dalam bukunya Kubra wal-Shugra fil-Manthiqi.
Abdurrahman Al-Akhdhari (abad ke-16 M) menyusun dasar-dasar pelajaran logika dalam bentuk sajak, bernama Sullam fil-Manthiqi. Buku ini sampai sekarang, beserta komentar-komentar yang muncul merupakan buku dasar bagi pelajaran logika di berbagai negeri dalam dunia Islam, termasuk Indonesia.
Muhibullah Al-Bisyari Al Hindi (meninggal 1707 M), berasal dari Peshawar, mengarang tentang logika bernama Sullamul-Ulum fil-Manthiqi. Bukunya ini lahir dan tersebar pada zaman kebesaran imperium Moghul di India.
Ahmad Al-Malawi (abad ke-18) memberi komentar atas karya tulis Al-Alkhdhari bernama Sjahrul-Sullam fil-Manthiqi. Ulasannya yang lebih lebar panjang dan lebih luas bernama Sjarhul-Kabir atau Komentar Terbesar.
Muridnya Muhammad Al-Shubban (abad ke-18) memberi ulasan lagi atas komentar gurunya itu dalam bukunya yang bernama Hasyiat 'ala syarhil-Sullam.
Pada awal abad ke-20 muncul gerakan pembaharuan dalam dunia Islam dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh dan sejalan dengan itu kegemaran terhadap logika muncul kembali di tanah Mesir dan gerakan ini cepat meluas di seluruh dunia Islam.
C. PERKEMBANGAN LOGIKA DI BARAT
Setelah menderita zaman gelap gulita hampir seribu tahun lamanya, Eropa pada abad kedua belas mulai menggali pelajaran logika. Peter Abelard (1079-1142 M) adalah yang pertama-tama menghidupkan kembali pelajaran logika pada perguruan tinggi yang dibangunkannya di Kota Paris.
1. Ars Vetus atau Logika Tua
Pelajaran logika pada masa itu masih tetap terbatas di luar "bab-bab terlarang", yakni terbatas sekitas Categoriae, Eisagoge, dan De Interpretatione saja. Akan tetapi, justru karena kesungguhan Abelard menggali naskah-naskah tua maka akhirnya ditemukannya juga naskah peninggal Cicero tentang Topica dan komentar Apuleus tentang Perihermenias dan buah tangan Boethius tentang De Syllogismo Hypothetico dan De Syllogismeo Categorico dan sebuah komentar tentang De Interpretatione.
Himpunan seluruhnya itulah yang disebut pada masa itu dengan Ars Vetus atau Logika Tua. Hal ini disebabkan bagian-bagian lainnya dari logika belum ditemukan, bahkan tidak pernah diketahuiorang pada masa itu. Sekalipun begitu hasil karya Abelard ini dipandang telah melewati batas-batas yang terlarang. Hingga hukuman kucil yang dijatuhkan Gereja terhadap dirinya pada masa kemudian, bukan disebabkan peristiwa skandalnya dengan Heloise, akan tetapi lebih banyak disebabkan oleh karena logika yang disusunnya dan dihidupkannya kembali. Ia mendapat tantangan sengit dari St. Bernard yang menyusun buku Odiusum me reddit mundo logica.
Murid Abelard bernama John Sallisbury menyusun buku dalam bidang logika bernama Et quia logicae suscepi patrocnium. Muridnya Adam de Panto menyusun buku Ars Dialectica mengenai Topica.
Pada masa itu, hanya beredar dua belas jenis buku saja dalam bidang logika ini dan isi satu per satunya hampir bersamaan belaka dan tak satu pun pad masa kemudian dipandang ornag bernilai untuk dicetak secara luas.
2. Ars Nova atau Logika Baru
Karya Aristoteles tentang logika dalam buku Organon dikenal di dunia Barat selengkapnya ialah sesudh berlangsung penyalinan-penyalinan yang sangat luas dari karya-karya sekian banyak ahli pikir Islam ke dalam bahasa Latin. Al-Farabi diberi gelar Guru-Kedua dan Ibnu Sina diberi gelar Guru Ketiga.
Beberapa bagian dari karya tulis Ibnu Sina mengenai Logika disalin ke dalam bahasa latin pada penghujung abad ke-12. Akan tetapi, salinan yang lebih sempurna dan lebih lengkap ialah himpunan komentar Ibnu Rasyid (Averroes) mengenai logika, disalin pada awal abad ke-13, dan sengaja diedarkan secara serentak masa itu di Kota Paris (Perancis) dan di kota oxford (Inggris). Ini mengakibatkan aliran baru di Eropa yang terkenal dengan sebutan Kaum Averroists. Kedua kota perguruan tinggi itu merupakan pusat kegiatan ilmiah di sepanjang abad ke-13 dan abad-abad berikutnya.
Penyalinan-penyalinan yang luas itu membukakan masa dunia Barat kembali akan alam pikiran Grik Tua. Mereka menyambut keseluruhan Organom itu dengan kegembiraan yang tiada terkira karena kini segenap bagian-bagian logika beserta tambahan-tambahannya dari ahli-ahli pikir Islam telah ditemukan, dan himpunan seluruhnya itulah yang pada masa itu disebut dengan Ars Nova atau Logika Baru.
Bahan-bahan baru ini menghasilkan karya yang sangat tebalnya dari Albertus Magnus (1206-1280 M) dalam bidang logika. Beberapa orang komentator yang semasa dengan Albertus Magnus memberikan sumbangan penting bagi perkembangan logika kembali di Barat, diantaranya dapat dicatat ialah Robert Grosseste (meninggal 1253 M) memberikan ulasan tentang Analytica Posteriora, St. Thomas Aquinas (1225-1274 M) yang memberikan komentar terpenting tentang Perihermenias, dari muridnya Giles of Rome (meninggal 1316 M) memberikan komentar lengkap tentang kesleuruhan Organon.
Komentar-komentar lainnya pada masa itu dijumpai lagi pada karya tulis Robert Kildwarby (meninggal 1279 M) seorang pengikut aliran Dominican dan lawan utama dari Thomas Aqunas, dan juga dari Duns Scotus (meninggal 1305 M) serta dari seorang yang digelari Avveroist bernama Boethius of Dacia (meninggal 1285).
Semenjak itu, literatur mengenai logika berkembang cepat di Barat, Petrus Hispanus (meninggal 1277 M) yang kemudian menjabat Paus dengan gelar Paus John XXI menyususn pelajaran logika berbentuk sajak, seperti Ali-Akhdari dalam dunia Islam, dan bukunya itu menjadi buku dasar bagi pelajaran logika sampai abad ke-17. Petrus Hispanus inilah yang mula-mula mempergunakan berbagai nama untuk sistem penyimpulan yang sah dalam perkaitan bentuk silogisme kategori dalam sebuah sajak berbunyi :
Barbara, Celarent, Darii, Ferioque, Prioris;
Cesare, Camestres, Festino, Baroko, Secundae;
Tertia: Darapti, Disamis, Datisi, Felapton,
Bocardo, Ferison, habet, Quarta insuper addit,
Bramantip, Camenes, Dimaris, Fesapo, Fresison.
Kumpulan sajak Petrus Hispanus mengenai logika ini bernama Summulae. Buku ini banyak diberi komentar dan ulasan kembali oleh penulis-penulis belakangan seperti Jean Buridan (1295-1366 M), Johannes Magistri (meninggal 1400 M), Johannes de Monte (meninggal 1450 M), Petrus Tartaritius (seorang rektor di Paris meninggal 1490 M), dan Chrysostom Javellus (meninggal 1538 M).
Penulis-penulis lainnya mengenai logika dari golongan Oxford tercatat nama Roger Bacon (meninggal 1292 M), Thomas Sutton (meninggal 1300 M), William of Ockham (1300-1349 M), Walter Burleight (1275-1345 M), William Heystesbury Richard Swineshead (yang karya tulisnya sangat dipuji oleh Karl Leibniz pada masa kemudian), John Dumbleton, Ralph Strode, dan Richard Ferabrich.
Dari golongan Paris tercatat Jean Buridan (1295-1366 M), Albert of Saxony (1316-1390 M), John of Cornwall (Preudo-Scotus), Raimon Lull (1323-1315 M), dan St. Vincent Ferrer (meninggal 1372 M)
3. Kemunduran Logika Kaum Scholastik
Menjelang penghujung abad ke-14 pengaruh logika kaum scholastik mulai mengalami kemundurannya karena telah lebih banyak memperdebatkan hal-hal yang tidak berarti antara kaum Nominalis dan kaum Realis sehingga logika kehilangan jiwanya yang dinamik. Logika makin lama makin dirasakan sebagai sesuatu yang hampa dan kosong untuk dipergunakan sebagai alat berpikir. Hal ini mulai menimbulkan muak pada sebagian orang.
Francis Bacon (1561-1626 M) melancarkan serangan sengketa terhadap logika dalam bukunya Novum Organum dan buku-bukunya yang lain dan menganjurkan penggunaan sistem induksi secara lebih luas. Serangan Bacon terhadap logika ini memperoleh sambutan hangat dari berbagai kalangan di Barat dan kemudian mata serta perhatian lebih ditujukan kepada penggunaan sistem induksi.
Dengan penggunaan sistem induksi ini penemuan-penemuan baru dalam bidang fisika banyak dijumpai si sepanjang abad ke-17 dan abad berikutnya. Kebangkitan gerakan reformasi secara hebat ini terutama pada abd ke-17, menyebabkan pengaruh logika kaum scholastik lenyap sama sekali.
4. Logika Golongan Port Royal
Pada tahun 1658 karya tulis Ibnu Sina selengkapnya mengenai logika disalin oleh Napier ke dalam bahasa Perancis. Pengaruh Ibnu Sina ini kelihatan pada kebangkitan logika kembali di tangan tokoh-tokoh yang terkenal dengan sebutan Golongan Port Royal.
Pada tahun 1662 terbit buku La Logique ou I'art de Pencer disusun oleh Antoine Arnauld dan Pierre Nicole dibantu oleh beberapa penulis lainnya. semuanya dari golongan Port Royal. Bukuini membawa pembaruan sehingga melahirkan kesegaran baru dalam pelajaran logika kembali.
Pembaruan logika di Barat berikutnya disusul oleh lain-lain penulis, di antaranya Gottfried Wilhem von Leibniz pada tahun 1666, yang menerbitkan buku Dissertatio de Arte Combinatoria disusul dengan berbagai buah tangannya yang lain dalam lapangan logika. Ia menganjurkan penggantian pernyataan-pernyataan dengan simbol-simbol agar lebih umum sifatnya dan lebih mudah melakukan analisis.
Giovanni Girolamo Saccheri, seorang ahli logika Italia, menerbitkan buku Logika Demonstrativa pada tahun 1501, dan dalam buku tersebut terlihat pengaruh ahli-ahli logika Arab teramat kuatnya terbukti dari dua masalah yang sangat ditekankannya sekali yang merupakan keistimewaan dari bukunya ini di depan mata ahli-ahli logika Barat, yaitu ;
(a) metode untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan dengan menonjolkan lawannya yang mengingkari dan hal ini kemudian dikenal dalam lapangan logika simbolik dengan Hukum-Clavius;
(b) perbedaan antara definisi nominalis dengan definisi realis bahwa yang pertama itu cuma melukiskan arti sesuatu dan yang kedua itu melukiskan wujud sesuatu.
Leonhard Euler, seorang ahli matematika dan logika Swiss menerbitkan bukunya Lettres a une princesse d'Allegmane pada tahun 1770, dan didalam kumpulan surat menyuratnya ia melakukan pembahasan tentang term-term dan mempergunakan lingkaran-lingkaran untuk melukiskan hubungannya; dan caranya ini terkenal kemudian dengan sebutan sirkel-Euler.
George Wilhelm Friedriech Hegel menerbitkan bukunya Wissenschaft der Logik, di antara tahun 1812 dan 1816 dan ia menentang proyek Leibniz untuk menggantikan pernyataan-pernyataan itu dengan simbol-simbol serta menganggapnya dangkal dan tidak berarti. Begitu juga ia menentang sistem calculus yang disusun oleh Plouquet, ahli logika Perancis. Hegel sendiri kemudian memperkembangkan suatu cara yang disebutnya dengan Dialektika; yakni dari sebiah kenyataan yang ada (thesis), ditemukan lawan kenyataan itu (anthithesis), guna memperoleh satu paduan yang lebih laras (sintesis). Dialektika yang dirumuskan Hegel ini kemudian menjadi alat utama di tangan Karl Marx (1818-1883) untuk menyusun filsafat komunis.
Bernard Bolzano pada tahun 1837 menerbitkan bukunya Wissenschoftlehre dan pengaruhnya barulah belakangan kelihatan, yaitu sesudah muncul perkembangan Logika-Simbolik.
John Stuart Mill pada tahun 1843 menerbitkan bukunya A system of Logic dan menyempurnakan perkembangan Logika-Formal (nama yang diberikan terhadap logika yang biasa guna membedakannya dari Logika Simbolik) dan mendamaikan pertentangan yang sekian abad lamanya antara pemuja induksi dengan pemuja deduksi. Setiap pangkal-pikir besar di dalam deduksi menurut Mill memerlukan induksi dan sebaliknya induksi itu memerlukan deduksi bagi penyusunan pikiran mengenai hasil-hasil eksperimen dan penyelidikan itu. Jdi kedua-duanya bukan merupakan bagian-bagian yang saling terpisah tetapi sebetulnya saling bantu-membantu. Mill sendiri merumuskan metode-metode dalam sistem induksi, dan rumusannya terkenal dengan sebutan Four-Methods, yaitu Metode Kausal.
D. PERKEMBANAG LOGIKA SIMBOLIK
Logika Formal sesudah masal Mill meneruskan perkembangannya lahirlah sekian banyak buku-buku baru dan ualsan-ulasan baru tentang logika, Dan sejak pertengahan abad ke-19 mulai lahir satu cabang baru yang disebut dengan Logika-Simbolik.
1. Gagasan Logika-Simbolik
Pelopor Logika Simbolik pada dasarnya sudah dimulai oleh Leibniz. Ia mengusulkan suatu teknik yang disebut ars combinatoria untuk menurunkan pengertian-pengertian yang rumit dari penggabungan sejumlah kecil konsep sederhana yang dijadikan pangkal. Diusulkannya pula suatu program pembaruan yang menyangkut bahasa dan penalaran dalam segenap ilmu.
Program ini meliputi pengembangan sebagai berikut :
a. Characteristica universalis (Bahasa Semesta); Bahasa ini yang khusus diciptakan dengan sejumlah simbol dasar dan berdasarkan suatu teknikpenggabungan direncanakan untuk dapat mengungkapkan semua buah pikiran sehingga dapat dipergunakan oleh segenap ilmuwan dan filsuf.
b. Calculus ratiocinator (Logica Mathematica); Ini adalah suatu sistem penalaran yang dengan simbol-simbol ideografis dan berdasarkan aturan-aturan yang cermat diharapkan dapat melakukan deduksi apa pun dalam semua bidang keilmuan.
Dua proyek dasar ini sayang Leibniz tidak mengembangkjan lebih lanjut gagasan-gagasannya itu secara lengkap maka tulisan-tulisannya dilupakan orang dan bahkan terpendam selama 2 abad lebih, demikian ia meletakkan landasan yang pertama bagi pertumbuhan Logika-Simbolik.
2. Pelopor dan Tokoh Logika-Simbolik
Logika simbolik bertujuan menjabarkan logika agar menjadi sebuah ilmu pasti. Setiap pengertian, setiap pernyataan, setiap hubungan digantikan dengan simbol-simbol. Gagasan ini dicetuskan mula-mula oleh Leibniz dan barulah pada pertengahan abad ke-19 memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh.
Langkah pertama dimulai dengan penjabaran lingkungan golongan (algebra of classes) dengan munculnya buah tangan George Boole dan Augustus de Morgan dengan serentak pada tahun 1847. Boole menerbitkan buku The Mathematical Analysis of Logic dan De Morgan mengeluarkan buku Formal Logic.
Buku Boole secara sistematik dengan memakai simbol-simbol yang cukup luas dan metode analisis menurut matematika mulai memperkembangkan logika simbolik. Oleh karena Boole menggunakan rumus-rumus seperti aljabar dalam mengungkapkan hubungan-hubungan logika maka pada permulaannnya sistem penalarannya itu dinamakan algebraic logic atau algebra of logic (aljabar dari logika)
Augustus De Morgan (1806-1871) merupakan seorang ahli matematika Inggris memberikan sumbangan besar kepada logika simbolik dengan pemikirannya tentang relasi dan negasi. Hasil pemikirannya mengenai pengingkaran dan pernyataan-pernyataan majemuk menjadi kaidah-kaidah logika simbolik yang disebut dengan namanya, yakni De Morgan's laws (Hukum De Morgan) atau terkenal dengan kependekannya DM. Kemudian muncul lagi penjabaran hubungan (algebra of relations) dalam karya tulisnya Syllabus of a Proposed System of Logic terbit tahun 1860.
Tokoh logika simbolik yang lain ialah John Venn (1834-1923), ia menulis buku Symbolic Logic (1881) dan berusaha menyempurnakan analisis logik dari Boole dengan merancang diagram lingkaran-lingkaran yang kini terkenal sebagai diagram Venn (Venn's diagram) untuk menggambarkan hubungan-hubungan dan memeriksa sahnya penyimpulan dari silogisme. Untuk melukiskan hubungan merangkum atau menyisihkan diantara subjek dan predikat yang masing-masing dianggap sebagai himpunan.
Sebagai pelopor kedua setelah Boole adalah (Friedrich Ludwig) Gottlob Frege, seorang ahli matematika dan logika dari Jerman. Oleh para ahli logika dewasa ini ia dianggap sebagai ahli logika terbesar dari abad ke-19 karena dengan karya tulisnya Begriffschrift (1879) ia mengubah aljabar logika dari Boole sehingga benar-benar menjadi logika simbolik yang di formalkan. Dalam karya tulisnya itu, pertama kalinya dibahas logika proposisi, ungkapan ubahan, pembilang, dan aturan-aturan penyimpulan.
Seorang ahli matematika Jerman Ernst Schroeder (1841-1902) memberikan sumbangan penting terhadap pertumbuhan logika simbolik dalam karya tulisnya Vorlesungen uber die Algebra der Logik yang terdiri atas 3 jilid terbit dalam jangka 5 tahun (1890-1895) menyempurnakan simbolisme dari Boole, mensistematikan dan menyatupadukan karya-karya para ahli yang terdahulu. Ia juga memberikan sumbangan mengenai masalah ungkapan ubahan dan logika relasi.
Sumbangan terhadap pertumbuhan logika simbolik diberikan pula oleh filsuf Amerika Serikat Charles Sanders Peiree dalam karya tulisnya The Grand Logic disamping menjadi editor dari Studies in Logic (1883). Hasil pemikirannya dalam logika proposisi menelurkan dalil yang kini disebut Peirce's Law dan mengembangkan juga logika relasi.
Perkembangan logika simbolik mencapai puncaknya pada awal abad ke-20 dengan terbitnya 3 jilid karya tulis dua filsuf besar dari Inggris Alfred North Whitehead dan Bertrand Arthur William Russell berjudul Principia Mathematica (1910-1913) dengan jumlah 1992 halaman. Dalam karya tulis tersebut mereka secara sangat luas dan terperinci membuktikan bahwa logika adalah masa muda dari matematika dan matematika adalah masa dewasa dari logika. Karya tulis Russell-Whiterhead Principta Mathematica memberikan dorongan yang besar bagi pertumbuhan logika simbolik.
Penelaahan yang lebih luas, lebih mendalam, dan lebih teknis dalam logika ini dilakukan oleh berbagai ahli logika. Tokoh-tokoh yang memberikan sumbangan penting bagi perkembangan logika-simbolik ini, diantaranya Emil Post (lahir 1897), Ludwig Josef Johann Wittlgenstein (1889-1951), Clarence Irving Lewis (1883-1964), Rudolf Carnap (lahir 1891), Henry Maurice Sheffer, Alfred Tarski (lahir 1902), Willard Van Orman Quine (lahir 1908), Kurt Goedel (lahir 1906). Tokoh-tokoh logika Polandia, misalnya Kazimierz Ajdukiewiez, Jan Lukasiewicz, dan Stanislaw Lesniewski. Di berbagai negara dewasa ini banyak terbit berkala yang khusus untuk pembahasan-pembahasan Logika-Simbolik.
E. KEADAAN LOGIKA DI INDONESIA
Pada mulanya keadaan logika di Indonesia dapat dikatakan menyedihkan. Logika tidak pernah menjadi mata pelajaran pada perguruan-perguruan umum. Pelajaran logika cuma dijumpai pada pesantren-pesantren Islam dan perguruan-perguruan Islam dengan mempergunakan buku-buku berbahasa Arab.
Pada tahun 1950 terdapat buku logika berbahasa Jawa dengan menggunakan huruf Arab Melayu, yaitu Ilmu Manthiq yang merupakan terjemahan dari kitb nadhom As-Sullamul-Munauroq karya Abdurrahman Al-Akhdhari (Abad ke-16 M), disusun oleh K.H.Bisyri Musthofa Rembang, dan sejak tahun 1953 Penerbit Menara Kudus menerbitkan buku tersebut dan beredar luas tidak hanya di Jawa saja, tetapi juga di luar Jawa seperti di Lampung. Buku terjemahan tersebut merupakan buku logika yang pertama di Indonesia yang dipelajari di pesantren-pesantren dan juga di beberapa Madrasah Aliyah yang berbasis buku-buku berbahasa Arab, seperti di Madrasah Mathaliul Falah Kajen Pati, Ilmu Manthiq termasuk mata pelajaran pokok.
Pada tahun 1954 penerbit W. Versluys N.V. di Jakarta menerbitkan buku Logika dan Ilmu Pikir, hasil karya Joesoef Sou'yb, agaknya itulah buku logika yang pertama dalam Bahasa Indonesia. Sekaligus juga merupakan buku logika yang kedua di Indonesia setelah buku Ilmu Manthiq.
Pada masa sekarang ini logika di Indonesia sudah mulai berkembang sejalan dengan dibukanya Fakultas Filsafat di Universitas Gadjah Mada tahun 1967. Logika yang dikembangkan di Fakultas Filsafat mengikuti juga perkembangan teori-teori terakhir logika yang beriringan juga dengan berkembangnya teori himpunan. Logika dikembangkan juga di Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam yang dikaitkan juga dengan teori himpunan.
Teori himpunan merupakan landasan dikembangkannya logika saat sekarang ini, dan logika erat hubungannya dengan matematika, yang oleh Bertrand Russel dinyatakan secara kiasan bahwa : "logika merupakan masa muda matematika, dan matematika merupakan masa dewasa logika". Logika dinyatakan masa muda matematika karena pada dasarnya kaidah-kaidah matematika yang begitu kompleks dapat disederhanakan dalam kaidah-kaidah dasar logika.
MODUL 2 :
DASAR-DASAR PENALARAN
Dasar penalaran pada umumnya adalah konsep atau ide atau sering juga disebut dengan pengertian, tanpa ada konsep atau ide tidak dapat diadakan penalaran karena konsep merupakan komponen terkecil dalam penalran.
Konsep atau ide diungkapkan dalam bentuk bahasa disebut dengan istilah term. Konsep dan term mempunyai konotasi dan denotasi atau disebut juga mempunyai isi dan luas, isi term merupakan suatu pengertian yang terkandung didalamnya dan luas term merupakan suatu himpunan.
Jadi, term pada dasarnya ada pengertiannya dan ada himpunannya dan tidak mungkin ada term yang tanpa pengertian dan himpunan walaupun kosong tidak ada yang ditunjuk tetap sebagai suatu himpunan, yaitu himpunan kosong.
Term maupun konsep sebagai dasar penalran perlu dipelajari dan diketahui juga pengelompokannya sehingga dapat diketahui apa fungsi masing-masing kelompok term tersebut dalam penalaran. Term secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu atas dasar isi yang terkandung dalam term, atas dasar luas atau himpunannya, atas dasar cara beradanya sesuatu, dan atas dasar cara menjelaskan sesuatu.
Di antara empat kelompok ini yang langsung berhubungan dengan perkembangan logika adalah term yang ditinjau atas dasar luas atau cakupannya yang mewujudkan adanya suatu himpunan, yang kemudian himpunan merupakan bentuk logika suatu konsep atau term, yang selanjutnya dapat untuk membuktikan sah tidaknya suatu penalaran.
Disamping konsep dan term sebagai unsur dasar penalara perlu juga dipelajari prinsip-prinsip penalaran atau sering juga disebut dengan aksioma penalaran. Prinsip-prinsip penalaran merupakan dasar semua penalaran baik di bidang ilmiah atau di bidang-bidang yang lain. Dalam menalar apapun pada dasarnya sudah melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, hanya tahu atau tidak karena prinsip-prinsip penalaran tersebut bersifat alami bagi pemikiran.
Prinsip-prinsip penalaran ini pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Yunani, yaitu Aristoteles, yang kemudian mengalami perkembangan. Prinsip-prinsip penalran di antaranya pada awal perkembangan teori himpunan merupakan juga sebagai prinsip dasar himpunan, yaitu prinsip kedua dan ketiga. Di dalam perkembangan logika pada saat sekarang ini prinsip-prinsip penalaran yang juga menjadi dasar teori himpunan tetap sebagai prinsip yang paling dasar yang harus diikuti dalam penalaran.
KEGIATAN BELAJAR 1 : KONSEP DAN TERM
Hasil tangkapan akal manusia mengenai suatu objek, baik material maupun nonmaterial disebut ide atau konsep. Ide berasal dari kata Yunani "eidos" yang artinya gambar, rupa yang dilihat. Akal budi manusia menangkap sesuatu objek melalui bentuk gambarnya. Oleh karena itu, representasi atau wakil objek yang terdapat di dalam akal itu disebut dengan istilah "idea".
Konsep berasal dari kata Latin "concipere", artinya mencakup, mengambil, menangkap. Dari kata concipere muncul kata benda conceptus yang berarti tangkapan. Kata konsep diambil dari kata conceptus tersebut.
Jadi, konsep sebenarnya berarti tangkapan. Akal manusia apabila menangkap sesuatu terwujud dengan membuat konsep. Dengan demikian, buah atau hasil dari tangkapan itu disebut dengan istilah "konsep". Jadi, idea dan konsep dalam logika adalah sama artinya.
Idea atau Konsep dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan istilah pengertian, yakni makna yang dikandung oleh sesuatu objek. Dalam modul ini yang digunakan adalah istilah "konsep" walaupun demikian mungkin sering digunakan juga istilah "pengertian". Konsep atau ide atau juga pengertian adalah bersifat kerohanian dan dapat diungkapkan ke dalam bentuk kata atau istilah atau juga beberapa kata.
Ungkapan pengertian dalam bentuk kata atau istilah disebut dengan "term", baik berupa istilah-istilah dalam bahasa buatan maupun kata-kata biasa dalam bahasa sehari-hari. Sebagai contoh, dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Dalam bahasa buatan;
Istilah "demokrasi", Istilah demokrasi yang dibentuk dari dua rangkaian kata Yunani demos dan kratein. Pengertian yang terkandung dalam rangkaian dua kata itu disebut konsep atau apa yang dimaksudkan oleh istilah demokrasi itulah yang disebut konsep atau pengertian. Sedang istilah "demokrasi" itu adalah term.
2. Dalam bahasa biasa;
Kata "manusia". Dengan adanya kata ini di dalam akal pikiran terbayangkan suatu gambaran tentang apa yang ditunjuk dengan kata manusia itu. Gambaran dalam akal inilah yang disebut dengan konsep atau pengertian. Sedang kata "manusia" adalah term.
Term sebagai ungkapan konsep atau pengertian jika terdiri atas satu kata atau satu istilah maka term ini dinamakan term sederhana atau term simpel, misalnya manusia, gajah, negara, demokrasi, politik.
Jika terdiri atas beberapa kata maka term itu dinamakan term komposit atau term kompleks, misalnya penyair modern, reaktor atom, kesenian daerah modern, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik stratesi nasional, paham integralistik Indonesia. Term komposit ini walaupun masing-masing bagian mempunyai pengertian sendiri-sendiri, tetapi jika digabungkan hanya menjadi satu konsep atau satu pengertian.
Kata atau istilah untuk mengungkapkan suatu konsep disebut juga simbol dari konsep atau pengertian. Dengan demikian, dapat dirumuskan juga bahwa :
Term adalah simbol atau kesatuan beberapa simbol yang dapat untuk menyatakan suatu konsep atau pengertian
Kata sebagai suatu simbol untuk menyatakan konsep atau pengertian dibedakan antara dua macam, yaitu kategorimatis dan kata sinkategorimatis.
Kata kategorimatis ialah kata yang dapat mengungkapkan sepenuhnya suatu pengertian yang berdiri sendiri tanpa bantuan kata lain, meliputi nama diri (misal Saddam Husain), kata sifat (misal berakal), istilah yang mengandung pengertian umum (misal manusia).
Kata sinkategorimatis ialah kata yang tidak dapat mengungkapkan suatu pengertian yang berdiri sendiri jika tidak dibantu oleh kata lain, misal seperti kata adalah, jika, semua, maka, dan sebagainya.
Selanjutnya dalam perbincangan-perbincangan dapat juga konsep dinyatakan dengan bentuk simbol-simbol tertentu secara abstrak, hal ini untuk memudahkan kedudukan konsep dalam suatu struktur penalaran, yang akhirnya simbol-simbol itu terlepas dari konsep-konsep atau pengertian-pengertian yang dikandungnya, misalnya :
A adalah B, dan B adalah C maka A adalah C.
Simbol-simbol A, B, dan C ini simbol abstrak yang terlepas dari isinya, simbol-simbol tersebut mempunyai makna jika dihubungkan dengan yang lain.
Setelah menelaah term, selanjutnya penting juga diketahui tentang konotasi dan denotasi term. Konotasi dengan istilah lain adalah intensi atau isi, sedang denotasi dengan istilah lain adalah ekstensi atau luas. Setiap term atau istilah pasti ada isi yang dimaksudkan oleh term dan juga ada luas sebagai cakupan yang ditunjuk. Konotasi dan denotasi term ini merupakan hal yang mutlak untuk penalaran karena term maupun pengertian adalah unsur konstitutif dalam proses penalaran.
A. KONOTASI
Setiap term mempunyai konotasi atau isi. Konotasi adalah keseluruhan arti yang dimaksudkan oleh sutu term. Keseluruhan arti yang dimaksudkannya adalah kesatuan antara unsur dasar atau term yang lebih luas dengan sifat pembeda yang bersama-sama membentuk suatu pengertian.
Jadi, apabila ingin menguraikan konotasi suatu term tidak jarang harus menggunakan banyak kata untuk mengungkapkannya. Dengan menggunakan bahasa yang mudah dapat juga dinyatakan bahwa konotasi tidak lain adalah isi atau apa yang termuat dalam suatu term, misal term manusia :
Konotasi term "manusia" adalah "hewan yang berakal budi" atau secara terurai dapat dirumuskan "substansi (unsur dasar) yang berbadan berkembang berperasa dan berakal (sifat-sifat pembeda)".
Konotasi ini secara singkat dapat juga dinyatakan merupakan suatu uraian tentang pembatasan arti atau definisi. Dengan demikian, definisi "manusia" dapat disusun dari hewan (substansi, berbadan, berkembang, dan berperasa) sebagai unsur dasar atau jenisnya, dan berakal sebagai sifat pembeda, yakni untuk membedakan manusia dengan yang lain dalam genus hewan.
Jadi, dapat dinyatakan bahwa "manusia adalah hewan yang berakal", atau juga manusia adalah makhluk yang berakal. Di sini jelaslah bahwa konotasi term adalah suatu definisi karena menunjukkan genus (jenis) dengan sifat pembeda. Akan tetapi, tidak semua definisi adalah konotasi term karena ada definisi yang didasarkan atas asal mula istilahnya. Definisi yang berhubungan dengan konotasi disebut definsis konotatif atau definisi esensial metafisik, hal ini akan dibicrakan secara jelas dalam pembahasan definisi. Contoh lain misalnya term demokrasi dan hukum :
Konotasi term "demokrasi" adalah suatu bentuk pemerintahan (sebagai unusr dasar atau jenisnya atau term yang lebih luas) yang berdasarkan atas tuntutan dari rakyat dipertimbangkan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat (sebagai sifat pembedanya).
Konotasi term "hukum" adalah peraturan (sebagai unsur dasar atau jenisnya atau term yang lebih luas dari hukum) yang bersifat memaksa (sebagai sifat pembeda atau pemisahnya).
Konotasi term "politik" adalah: pengetahuan (sebagai unsur dasar atau ketatanegaraan (sebagai sifat pembeda atau pemisahnya).
Konotasi term "sosialisme" adalah paham kenegaraan (sebagai unsur dasar atau jenisnya atau term yang lebih luas) yang berusaha supaya harta benda, industri, dan perusahaan menjadi milik negara (sebagai sifat pembedanya).
Dalam penalaran, apabila telah mengerti konotasi dari sesuatu hal atau sesuatu istilah, berarti sebenarnya telah memiliki suatu bagian, atau ikhtisar mengenai hal yang akan dibicarakan. Dengan kata lain, telah mengetahui definisinya. Kemudian yang perlu dikerjakan selanjutnya ialah membentangkan atau menguraikan, membuat analisis, dan memberi penjelasan lebih lanjut. Akan tetapi, memang tidak dapat disangkal bahwa untuk memiliki konotasi sesuatu term , sering kali harus belajar banyak.
B. DENOTASI
Setiap term mempunyai denotasi atau lingkungan. Denotasi adalah keseluruhan hal yang ditunjuk oleh term, atau dengan kata lain keseluruhan hal sejauh mana term itu dapat diterapkan. Denotasi atau lingkungan atau sering juga disebut dengan luas adalah mencakup semua hal yang dapat ditunjuk atau lingkungan yang dimaksudkan oleh term. Tiga contoh diatas yakni manusia, demokrasi, dan hukum, denotasinya adalah sebagai berikut :
Denotasi term "manusia" yang didefinisikan sebagai hewan yang berakal, dapat diterapkan pada Bangsa Indonesia, Bangsa Cina, Bangsa Yahudi, dan sebagainya yang dapat ditunjuk atau disebut oleh term manusia.
Denotasi term "demokrasi" yang didefinisikan suatu bentuk pemerintahan berdasarkan atas tuntutan dari rakyat dipertimbangkan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat, dapat diterapkan pemerintahan di Amerika Serikat, Republik Indonesia, dan bentuk-bentuk pemerintahan demokrasi yang lain.
Denotasi term "hukum" yang didefinisikan sebagai peraturan yang bersifat memaksa, dapat diterapkan pada hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum lingkungan, hukum laut internasional, hukum waris, serta bentuk-bentuk hukum yang lain.
Denotasi term "politik" yang didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan, dapat diterapkan pada sistem p[emerintahan, dasar-dasar pemerintahan maupun bentuk-bentuk pengetahuan mengenai kenegaraan yang lainnya.
Denotasi term "sosialisme" yang didefinisikan pahak kenegaraan yang berusaha supaya harta benda, industri, dan perusahaan menjadi milik negara, dapat diterapkan pada negara Cina, negara Korea Utara, negara Vietnam, negara Cuba maupun bentuk-bentuk negara yang berpaham sosialis.
Denotasi term ini menunjukkan adanya suatu himpunan karena sejumlah hal-hal yang ditunjuk itu menjadi satu kesatuan dengan ciri tertentu (sifat-sifat tertentu). Dengan adanya sifat-sifat yang diuraikan oleh konotasi (isi term) maka dapatlah dihimpun beberapa hal tertentu menjadi satu kesatuan. Dengan menunjukkan beberapa hal maka denotasi berhubungan juga dengan kuantitas.
Dengan dasar sifat-sifat tertentu sebagai ciri pemisah atau ciri pembeda, dapat untuk membedakan hal-hal lain yang tidak termasuk dalam himpunannya, misalnya "himpunan manusia". yang berada dalam himpunan itu adalah hal-hal yang memenuhi syarat definisi manusia tau mempunyai ciri-ciri sebagai manusia, yang tidak memenuhi syarat berarti berda diluar himpunan.
Jadi, jelaslah setiap term apapun pasti ada himpunannya, dan jika term tersebut tidak ada anggotanya walaupun pengertiannya ada tetap dikatakan mempunyai himpunan, yang disebut dengan himpunan kosong, apalagi yang emmpunyai satu anggota atau hanya menunjuk pada satu hal tertentu. Himpunan yang menunjukkan denotasi term, dapat dilukiskan dalam bentuk lingkaran-lingkaran atau bentuk-bentuk lain yang berupa diagram suatu himpunan.
Pertama-tama yang melukiskan denotasi term ke dalam bentuk diagram himpunan ini ialah ahli matematika Swis bernama Leonhard Euler (1707-1783 M). Selanjutnya, dikembangkan oleh John Venn seorang ahli logika Inggris (1834-1923 M) sehingga bentuk-bentuk diagram untuk melukiskan denotasi term disebut dengan "diagram Venn".
Perkembangan selanjutnya diagram-diagram itu secara sederhana disebut dengan istilah "diagram himpunan", sebagaimana yang digunakan dalam teori himpunan , dan dalam modul ini digunakan juga istilah "diagram himpunan". Bentuk diagram himpunan dapat berupa lingkaran-lingkaran maupun bentuk-bentuk lain yang dapat digunakan untuk menghimpun suatu kelompok dalam satu term, atau satu kelompok yang berdasarkan ciri pembeda yang sama.
C. HUBUNGAN KONOTASI DAN DENOTASI
Konotasi dan denotasi term, keduanya terdapat suatu hubungan yang erat tidak dapat terlepaskan, berbentuk hubungan berbalikan (dasar-balik); jika yang satu bertambah maka yang lain akan berkurang, demikian sebaliknya.
Dalam hal ini, terdapat empat kemungkinan, yakni :
1. makin bertambah konotasi makin berkurang denotasi;
2. makin berkurang konotasi makin bertambah denotasi;
3. makin bertambah denotasi makin berkurang konotasi;
4. makin berkurang denotasi makin bertambah konotasi.
Sebagai contoh, term "demokrasi" jika hanya "demokrasi" maka denotasinya yang ditunjuk sangat luas, baik demokrasi yang dikembangkan di Amerika Serikat, demokrasi yang dikembangkan di Inggris, demokrasi yang dikembangkan di Iran maupun demoikrasi yang dikembangkan di Republik Indonesia. Jika ditambah dengan ciri pembeda "Pancasila", dalam arti "demokrasi Pancasila" maka hanya dapat diterapkan di negara yang berdasrkan Pancasila saja.
Contoh term "negara", misalnya term "negara" ini sebagai konotasinya adalah "organisasi masyarakat dalam suatu wilayah yang bertujuan kesejahteraan umum dan tunduk pada satu pemerintahan pusat" maka denotasinya ialah semua negara-negara yang ada di dunia sejak dahulu sampai sekarang. Jika pada konotasi term "negara" ini ditambahkan dengan "tunduk pada satu pemerintahan pusat yang dipilih oleh rakyat" maka penambahan ini melahirkan pengertian "negara demokrasi". Dengan demikian, denotasi tidak memasukkan negara-negara yang bukan negara demokrasi.
Contoh lain, istilah "persatuan"; Istilah persatuan yang dimaksudkan misalnya "usaha ke arah bersatu dalam satu kesatuan keseluruhan" maka yang ditunjuk luas sekali, dapat usaha bersatu seluruh rakyat, usaha bersatu suatu kelompok tertentu atau juga usaha bersatu dalam satu negara dengan cita-cita yang sama atau juga yang lainnya.
Jadi, kalau hanya persatuan ini penggunaannya luas sekali, tetapi jika ditambah dengan kata "Indonesia", menjadi "persatuan Indonesia" maka yang dimaksudkan adalah khusus usaha ke arah bersatu dalam satu kestuan rakyat Indonesia.
Hubungan yang berbalikan antara konotasi dan denotasi term, untuk lebih jelasnya dapat dicontohkan dengan menggunakan klasifikasi alam semesta yang dikemukakan oleh Porphyry (nama Yunani: Porphyrios) seorang ahli pikir Iskandariah (212-304 M). Dari golongan yang paling luas ke golongan hal yang paling sedikit lingkungannya. Dari "substansi" sebagai term yang paling luas yang meliputi semua genus disebut dengan summum-genus, ke term "manusia" yang lebih sempit sebagai spesies yang terakhir disebut infima-spesies.
| Term |
Konotasi |
Denotasi |
| Substansi |
Substansi (1) |
Benda-benda gas, badan-badan mati,
tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia (5) |
| Badani |
Substansi, berbadan (2) |
Badan-benda mati, tumbuh-tumbuhan,
binatang, manusia (4) |
| Organisme |
Substansi, berbadan,
berkembang (3) |
Tumbuh-tumbuhan, binatang,
Manusia (3) |
| Hewan |
Substansi, berbadan,
berkembang, berindra (4) |
Binatang, manusia (2) |
| Manusia |
Substansi, berbadan,
berkembang, berindra,
Berakal (5) |
Manusia (1) |
Dalam contoh di atas jelaslah, makin banyak sifat-sifat yang ditambahkan dalam konotasi, semakin sempit lingkungan yang ditunjuk oleh term itu, sebaliknya semakin banyak hal-hal yang ditambahkan dalam denotasi, semakin berkurang sifat-sifat yang dinyatakan itu.
KEGIATAN BELAJAR 2 : MACAM-MACAM TERM
Term merupakan konsep yang terkandung di dalamnya banyak sekali macam, demikian juga pembagiannya. Namun, dalam modul ini term dan pembagiannya itu hanya akan dibedakan atas empat macam atau empat kelompok, yakni pembagian term menurut konotasinya, pembagian term menurut denotasinya, pembagian menurut cara beradanya sesuatu, dan pembagian menurut cara menerangkan sesuatu.
A. TERM BERDASARKAN KONOTASI
Berdasarkan konotasi term atau isi yang dikandung oleh term itu maka dapat dibedakan antara term konkret dan term abstrak. Disamping itu, keduanya ada yang berada dalam lingkungan hakikat dan ada yang berada dalam lingkungan sifat. Term konkret dan Term Abstrak ini hanya dijumpai dalam perbincangan sehari-hari maupun dalam bidang ilmu.
Dalam logika perlu diperhatikan bagaimana memandang suatu realitas dengan menggunakan term yang mengandung konsep konkret dan term yang mengandung konsep abstrak. Suatu realitas merupakan keseluruhan, realitas berdiri sebagai subjek dan mempunyai berbagai sifat.
Sebelum sampai pada pengertian term konkret dan term abstrak yang berada dalam lingkungan hakikat maupun lingkungan sifat, perlu diuraikan terlebih dahulu beberapa contoh untuk mempermudah pengertian.
Pertama-tama diuraikan contoh tentang term "wanita cantik" sebagai term konkret. Jika melihat seorang wanita kemudian berkata wanita cantik maka hal ini menunjukkan pada suatu realitas, yaitu wanita dengan sifat wajahnya yang cantik. Konsep atau pengertian yang terkandung dalam term "wanita cantik" ini konkret, artinya dengan langsung memperlihatkan realitas sebagai subjek yang mempunyai diri. Perlu dijelaskan di sini bahwa pengertian diri menurut logika bukan sesuatu yang berjasad saja, tetapi yang tidak berjasad pun dapat disebut diri jika memiliki kepribadian dengan sifat-sifat tertentu, misalnya negara. Negara ini tidak mempunyai jasad yang dapat ditangkap dengan pancaindra.
Selanjutnya, diuraikan juga contoh tentang term "kecantikan" sebagai term abstrak, dengan memberikan perhatian dan minat yang istimewa pada sifat cantik secara terpisah dari wanita, yang disendirikan dan dipandang seolah-olah sebagai suatu substansial. Hal ini menunjuk sifat tanpa subjeknya, yang merupakan salah satu ciri term abstrak.
Dari uraian diatas dapatlah dinyatakan bahwa secara garis besar konotasi term dapat dibedakan antara lingkungan hakikat dan lingkungan sifat atau term yang masuk hakikat dan term yang masuk sifat, yang masing-masing juga terdiri atas term konkret dan term abstrak sehingga uraian tentang term-term ini dapat dijelaskan ada empat hal, yaitu hakikat abstrak, hakikat konkret, sifat abstrak, dan sifat konkret, yang masing-masing diuraikan sebagai berikut :
1. Lingkungan hakikat; yaitu term yang mempunyai persamaan satuan dalam suatu makna tanpa ada perbedaan tingkatan menurut hakikatnya, misalnya "manusia". Pengertian manusia ini baik yang berkulit putih maupun hitam sama dalam arti kemanusiaannya. Term dalam lingkungan hakikat ada dua macam yaitu sebagai berikut :
a. Hakikat konkret; yaitu menunjuk ke "hal" nya suatu kenyataan atau apa saja yang berkualitas, seperti bentuk, berat, rupa dan bereksistensi, seperti waktu tertentu, tempat tertentu, mempunyai hubungan dengan objek lain, misalnya manusia, kera.
b. Hakikat abstrak; menyatakan suatu kualitas yang tidak bereksistensi tertentu atau kualitas yang terlepas dari eksistensi, misalnya kemanusiaan, kebenaran.
2. Lingkungan sifat; yaitu term yang didalam halnya itu ada perbedaan tingkatan, misalnya "berbadan", arti yang dikandung dalam term ini terdapat suatu perbedaan kekuatan dan kelemahan, yaitu berbadannya manusia lain dengan berbadannya binatang, tumnuh-tumbuhan, dan lain pula dengan berbadannya benda mati. Term dalam lingkungan sifat ada dua macam yaitu sebagai berikut :
a. Sifat konkret; yaitu menunjuk pen"sifatan"nya suatu kenyataan atau apa saja yang berkualitas dan bereksistensi, misalnya berbadan, merah, persegi, berindera.
b. Sifat abstrak; yaitu menyatakan persifatan yang terlepas dari eksistensi tertentu, misalnya kerasionalan, kebijaksanaan.
B. TERM BERDASARKAN DENOTASI
Berdasarkan denotasi term, dapat dibedakan term yang bersifat umum disebut term umum dan term yang bersifat khusus disebut dengan term khusus.
1. Term Umum; yaitu dapat mencakup keseluruhan hal-hal yang ditunjuk tiada terkecualinya. Term umum ini dibedakan antara dua macam yaitu sebagai berikut :
a. Universal; Sifat umum yang berlaku didalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, misalnya organisme, manusia, kemanusiaan, mahasiswa, persatuan, hewan.
b. Kolektif; Sifat Umum yang berlaku didalamnya menunjuk suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan, misalnya Rakyat Indonesia, Bangsa Cina, persatuan Indonesia, mahasiswa UGM, mahasiswa indonesia.
2. Term Khusus; yaitu hanya menunjuk sebagian dari keseluruhan sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal. Term khusus juga dibedakan antara dua macam yaitu sebagai berikut :
a. Partikular; sifat khusus yang berlaku didalamnya hanya menunjuk sebagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan, misalnya sebagian manusia, ada mahasiswa, sebagian yang dapat hidup di air, beberapa pejabat pemerintah. Khusus partikular disebut juga eksistensial.
b. Singular; sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk pada satu hal atau suatu himpunan ayang mempunyai hanya satu anggota, misalnya presiden pertama Republik Indonesia, seorang proklamator yang menjadi presiden. Khusus singular sering juga disebut dengan individual.
Term umum dan term khusus atau term umum dengan term umum yang lain jika keduanya berhubungan maka sifatnya relatif, maksudnya term umum dapat dinyatakan khusus dan term khusus dapat juga dinyatakan umum.
Term umum dapat menjadi khusus jika dibandingkan dengan term-term keseluruhan yang mencakupnya, misalnya term "manusia" yang bersifat umum dibandingkan dengan term "organisme" maka term manusia ini menjadi khusus.
Jika dibandingkan dengan term-term bagian yang ada di lingkungannya maka term yang dinyatakan khusus tadi dapat menjadi umum, misalnya term "manusia" tadi dibandingkan dengan term "bangsa indonesia" maka term manusia ini menjadi umum. Contoh lain antara perbandingan dua macam term tersebut :
Berdasarkan denotasi dua macam term yang berhubungan dapat dilukiskan dalam bentuk diagram himpunan untuk menunjukkan perbedaan luas lingkungannya atau luas denotasinya antara term umum dan term khusus. Misalnya, antara term "manusia" dan "bangsa indonesia". Kedua term ini termasuk term umum dan keduanya berhubungan sehingga dilukiskan dalam diagram himpunan sebagai berikut (lihat diagram).
Dalam diagram tersebut, term "manusia" sebagai term umum atau term yang lebih luas denotasinya, meliputi term "bangsa indonesia" sebagai bagiannya, dan term "bangsa indonesia" berada dalam lingkungan term "manusia".
Contoh selanjutnya dapat dikemukakan tentang klasifikasi alam semesta yang dikemukakan oleh Porphyry, klasifikasi tersebut dilukiskan dalam bentuk diagram himpunan sebagai berikut :
Substansi meliputi badani, badani meliputi organisme, organisme meliputi hewan, dan hewan meliputi manusia. Dapat pula dinyatakan : " manusia termasuk dalam pengertian hewan, hewan termasuk dalam pengertian organisme, organisme termasuk dalam pengertian badani, dan badani termasuk dalam pengertian substansi ".
Dengan melihat diagram himpunan term-term umum di atas yang saling berhubungan, jelaslah bahwa term umum dapat juga dinyatakan sebagai term khusus jika dihubungkan dengan term umum yang meliputinya. Oleh karena itu, keduanya saling berhubungan maka term umum dan term khusus sifatnya relatif, tetapi jika keduanya tidak ada titik hubungannya tidak dapat ditentukan.
Term umum dan term khusus keduanya merupakan dua hal yang berbalikan. Umum kebalikannya khusus dan khusus kebalikannya umum. Istilah "umum" biasanya menunjuk pada universal dan istilah "khusus" biasanya menunjuk pada eksistensial. Konsep ini ada kesamaan baik untuk logika, matematika, maupun filsafat. Dalam bidang logika maupun matematika konsep umu dan khusus ditandai dengan simbol-simbol sebagai berikut.
∀x atau Ax : dibaca; "untuk semua x", "untuk semua x berlakulah".
Huruf A (berasal dari ucapan Inggris "for All x it holds true that") yang selalu disertai dengan x menunjukkan sifat universal, dan simbol ∀x disebut dengan "kuantor universal".
∃x atau Ex : dibaca ; "ada x", "sebagian x", "terdapatlah suatu x sedemikian"
Huruf E (berasal dari ucapan Inggris "there Exist an x such that") yang selalu disertai dengan x menunjukkan sifat partikular atau eksistensial, dan simbol ∃x disebut dengan "kuantor eksistensial".
C. TERM BERDASARKAN PREDIKAMEN
Predikamen yang dimaksudkan ialah cara beradanya sesuatu. Dalam menghadapi sesuatu yang masih asing dan ingin mengetahui lebih dalam lagi maka pertama yang perlu ditempuh ialah mengadakan penguraian secara kategori. Hal ini merupakan proses penalaran yang pertama-tama ke arah pembentukan konsep atau pengertian yang lengkap.
Penguraian secara kategori adalah pemerincian menurut cara beradanya sesuatu, yang pembagiannya ada sepuluh kategori. Sepuluh kategori ini merupakan pembagian term universal yang melingkupi keseluruhan aspek sesuatu.
Perlu diketahui, term "ada" atau term "yang ada" adalah term transendental yang terdasar, dan merupakan term yang paling luas himpunannya tidak ada term yang lebih luas dari term "yang ada". Term "ada" selanjutnya dibagi dalam dua macam, yaitu sebagai berikut :
1. Ada yang tidak terbatas, yang mewujudkan sebuah term, dan menunjuk suatu Realita yang Khas, yakni Tuhan.
2. Ada yang terbatas (atau adanya ciptaan), yang mewujudkan genus pertama dan tertinggi, dapat dikatakan tentang banyak hal.
Ada yang terbatas menunjuk setiap "ada yang tersusun dari ese dan esnsia". Berkat ese-nyalah maka ada tadi berada. Ese menunjukkan prinsip eksistensi. Berkat esensia-nyalah, sesuatu ada yang terbatas adalah "hanya sesuatu tertentu itu": kucing, burung, manusia, dan lain-lain.
Setiap esensia yang terbatas terdiri atas sebuah ubsur dasar yang disebut substansi predikamental dan sejumlah unsur pelengkap yang disebut aksidensia fisik. Dengan istilah yang lain sesuatu yang ada terbatas pasti ada unsur hakikat dan unsur sifat, dua unsur ini berhubungan, hakikat tanpa sifat tidak akan ada, dan sifat tanpa hakikat tidak akan terwujud sehingga dinyatakan :
Sesuatu yang ada (ada terbatas) pasti ada unsur hakikat dan unsur sifat, atau menurut filsafat dinyatakan secara singkat terdiri atas substansi dan aksidensia.
Dengan dasar urain tersebut, pembagian sepuluh kategori atau predikamen yang dimaksudkan di atas dan menunjukkan cara beradanya yang paling umum, dibedakan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut :
1. Predikamen substansi; yakni hakikat zat terdapat dalam diri yang dapat berdiri sendiri.
2. Predikamen aksidensia; yakni peserta zat sebagai pemberi bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri.
Penjelasan predikamen substansi dan predikamen aksidensia pembagiannya secara terperinci adalah sebagai berikut :
1. Predikamen substansi; Predikamen substansi merupakan hakikat zat, yang dijelaskan sebagai berikut.
Substansi; hakikat sesuatu yang adanya terdapat di dalam diri sendiri sebagai pendukung sifat-sifat. Termasuk predikamen "substansi" ialah : manusia, hewan, pohon, yaitu semua pengertian atau predikat, yang dinyatakan dalam kata yang dalam gramatika umumnya disebut kata-kata substantif.
2. Predikamen aksidensia; Predikamen aksidensia merupakan kumpulan sifat zat, yang ada sembilan sifat, yang dijelaskan sebagai berikut.
a. Kuantitas; besaran atas sekian banyak hal ataupun satu diri yang mempunyai besaran, seperti besar, kecil, panjang, lebar, dalam, berat, dan sejenisnya.
b. Kualitas; sifat perwujudan sebagai ciri atau tanda pengenal, seperti tangguh, panas, dingin, bagus, baik, terpelajar, keras kepala, dan sejenisnya.
c. Aksi; hal yang dapat memengaruhi sesuatu, dapat juga berupa perbuatan, seperti membangun, mengajar, melahirkan, menekan, menetes, dan sejenisnya.
d. Pasi; akibat atau kesan setelah dipengaruhi sesuatu, seperti dibangun, dilahirkan, mengerti, longsor, banjir, bergelombang, dan sejenisnya.
e. Relasi; hubungan dengan berbagai hal lain, seperti identik, majikan, hamba, guru, murid, bawahan, bagian, keseluruhan, lebih besar, lebih kecil, dan sejenisnya.
f. Ruang; tempat yang menyertai perwujudan dimana sesuatu itu ada, seperti di sini, di rumah, di kamar, ruang terbuka, ruang hampa, dan sejenisnya.
g. Waktu; tempo yang menyertai kapan sesuatu itu ada, seperti sekarang, kemarin, bulan depan, dan sejenisnya.
h. Posisi; kedudukan sesuatu dalam lingkungan tertentu atau berada dalam suatu tempat tertentu, seperti berdiri, berlutut, silang dunia, terjepit, dan sejenisnya.
i. Keadaan; kepunyaan khusus menyertai kedudukan, seperti berpakaian, sehat walafiat, bahagia, berkeluarga, dan sejenisnya.
Jadi, setiap sesuatu mestilah disoroti dari sepuluh kategori ini yang dibedakan antara dua macam, yaitu hakikat zat dan kumpulan sifat-sifat. Oleh karena sesuatu terdiri atas hakikat dan sifat, sikap yang demikian merupakan langkah pertama bagi pembentukan konsep atau pengertian yang lebih jelas dan lebih lengkap tentang sesuatu hal.
Untuk memperjelas dua macam predikamen di atas dapat dicontohkan di sini antara pernyataan "Ahmad manusia" dan "Ahmad terpelajar". Dalam pernyataan "Ahmad manusia" ini, predikat "manusia" menunjukkansesuatu yang berdiri sendiri, yang bukan merupakan sifat hal lain, sebab manusia itu bukan suatu sifat melainkan suatu hal yang memiliki sifat-sifat. Oleh karena itu term manusia itu merupakan predikamen substansi, yaitu hakikat zat. Dalam pernyataan "Ahmad terpelajar", predikat "terpelajar" menunjukkan sesuatu yang ada pada yang lain dan dalam yang lain, sebab menunjukkan adanya ilmu yang dimiliki setelah belajar, bukan sesuatu yang berdiri sendiri melainkan dapat ada dalam diri manusia, oleh karena itu term terpelajar ini merupakan predikamen aksidensia, yaitu salah satu dari sifat yang ada.
D. TERM BERDASARKAN PREDIKABEL
Predikabel yang dimaksudkan ialah cara menerangkan sesuatu. Pembagian sepuluh kategori di atas adalah menurut cara beradanya sesuatu. Uraian selanjutnya, term ditinjau menurut cara menjelaskannya atau cara menerangkannya, hal ini juga berdasarkan term universal. Cara menjelaskan merupakan pengungkapan hubungan berbentuk predikat sebagai penjelasan dari suatu subjek dalam bentuk pernyataan.
Predikabel juga merupakan cara untuk menyatakan diri yang dapat terlepas dari beradanya sesuatu atau cara tertinggi yang dipergunakan oleh predikamen-predikamen untuk menyatakan diri. Sebagai contoh, dapat dikemukakan tiga pernyataan sebagai berikut :
Aristoteles manusia
Aristoteles hewan
Aristoteles berakal
Predikamen-predikamen dalam contoh diatas tidak sama nilainya walaupun ketiga-tiganya adalah predikamen substansi, yakni "manusia", "hewan" dan "berakal", yang menunjukkan beradanya term "Aristoteles", namun masing-masing predikamen tersebut dapat dinyatakan berbeda menurut cara menjelaskannya atau cara menerangkannya.
Cara menjelaskan sesuatu yang baik pada dasarnya harus mengetahui lima kelompok term sebagai predikabel. Predikabel dapat untuk memahami term yang masuk kelompok hakikat dan kelompok sifat yang ditinjau dari segi bagaimana cara menjelaskan sesuatu.
Predikabel dibedakan antara antara lima macam, dua diantaranya mengenai zat, yakni genus (jenis) dan spesies (golongan). Tiga diantaranya mengenai sifat, yakni diferensia (sifat pembeda), proprium (sifat khusus) dan aksiden (sifat kebetulan).
Lima hal ini merupakan term-term universal yang digunakan untuk menjelaskan suatu subjek dari pernyataan. Genus merupakan himpunan yang lebih luas dari himpunan spesies. Oleh karenanya setiap genus terdiri atas himpunan spesies, sedangkan yang memisahkan dan menentukan batas-batas antarspesies adalah sifat-sifat atau ciri pembeda :
1. Genus ; ialah himpunan golongan-golongan menunjukkan hakikat yang berbeda bentuk, tetapi terpadu oleh persamaan sifat, misal term "hewan". Dalam term hewan ini, terhimpun golongan manusia, kera, singa, dan sebangsanya. Satu persatu golongan ini mempunyai perbedaan bentuk, tetapi terdapat sifat-sifat yang dapat menghimpun semua golongan dalam satu himpunan yang lebih luas, yakni sama-sama memiliki indra.
Term genus untuk menjelaskan sesuatu hal merupakan suatu term sebagai predikat yang menyatakan hakikat dari sesuatu hal tetapi belum mengungkapkan secara lengkap hanya menunjukkan bagian dari penjelasan atau merupakan konsep umum yang menjelaskan bagian-bagiannya dalam keseluruhan itu, tetapi belum lengkap, misal konsep "peraturan" sebagai genus dari konsep"hukum" sebagai bagiannya. Konsep "peraturan" belum lengkap untuk menjelaskan konsep konsep "hukum" sehingga perlu membutuhkan konsep lain. Oleh karena itu, harus dilengkapi dengan konsep hakikat yang lain sebagai pembedanya.
2. Spesies ; ialah himpunan sesuatu yang menunjukkan hakikat bersamaan bentuk maupun sifatnya sehingga dapat memisahkan dari lain-lain bentuk maupun sifatnya sehingga dapat memisahkan dari lain-lain golongan, misalnya term "manusia". Setiap diri dalam lingkungan golongan ini memperlihatkan persamaan bentuk , sedangkan persamaan sifat yang memisahkannya dari lingkungan golongan yang lain ialah sifat berakal.
Spesies juga merupakan suatu konsep predikat yang dapat menjadi subjek untuk penjelasan sesuatu, menyatakan hakikat dari suatu hal secara lengkap dan utuh. Contoh seperti konsep "hukum" sebagai term spesies bagian dari konsep "peraturan", dapat dijelaskan bahwa "hukum"adalah "peraturan", tetapi penjelasan ini belum lengkap. Konsep 'hukum" sebagai genus, contoh lain misalnya untuk menjelaskan tentang "Undang-Undang Dasar 1945" mka dapat dinyatakan "Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar negara". Penjelasan ini belum lengkapmaka perlu adanya sifat pembeda atau sifat pemerintah.
3. Diferensia ; ialah sifat pembeda yang menunjukkan hakikat suatu golongan sehingga terwujud kelompok diri. Diferensia merupakan konsep predikat yang menentukan dalam menyatakan hakikat sehingga dapat membatasi dan memisahkan sesuatu spesies dengan spesies lainnya dalam genus yang sama. misalnya "berakal" diperuntukkan manusia, sifat "panas" pada api.
Dalam penjelasan, Diferensia merupakan konsep untuk melengkapi genus supaya lengkap dan utuh, misalnya penjelasan "hukum adalah peraturan", penjelasan ini belum lengkap jika belum ada diferensianyadsehingga dilengkapi konsep "yang bersifat memaksa" sebagai diferensianya, yaitu "hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa", "Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar negara yang tertulis". Konsep "yang tertulis" sebagai diferensia atau sifat pembeda untuk membedakan hukum dasar negara yang tidak tertulis yang disebut dengan konvensi.
4. Proprium ; ialah sifat khusus sebagai predikat yang niscaya terlekat pada hakikat sesuatu diri sehingga dimiliki oleh seluruh anggota golongan. Sifat khusus merupakan kelanjutan dari sifat pembeda yang di luar hakikat, tetapi selalu berhubungan, hubungannya erat sekali sehingga dapat dinyatakan memikirkan sesuatu benda yang terlepas dari sifat khususnya merupakan suatu kontradiksi. Hubungan antara "hakikat" sesuatu benda dengan "sifat khusus" nya merupakan hubungan mesti dan mutlak yang tidak dapat diingkari, misalnya "berpolitik" untuk manusia, rona "putih" pada salju. Sifat khusus ini secara langsung berasal dan sebagai akibat dari hakikat suatu benda, atau dengan kata lain sifat khusus itu adalah berlaku dalam hakikat benda, tetapi bukan merupakan hakikatnya.
Dalam penjelasan tentang manusia misalnya "manusia adalah hewan yang berpolitik", "manusia adalah makhluk yang berekonomi", "manusia adalah makhluk yang pandai menggunakan simbol-simbol", "manusia adalah makhluk sosial". Contoh lain, "jumlah sudut segitiga dalam bidang datar adalah 180⁰", ini merupakan sifat khusus dari setiap segitiga.
5. Aksiden ; ialah sifat kebetulan sebagai predikat yang tidak bertalian dengan hakikat sesuatu diri sehingga tidak dimiliki oleh seluruh anggota golongan. Sifat kebetulan ini merupakan sifat yang dapat ada atau dapat juga tidak ada, tidak ada hubungan langsung dengan hakikat sehingga dapat juga membayangkan sesuatu benda yang tanpa adanya sifat kebetulan yang ada padanya, misalnya "berambut pirang", "berkulit putih" untuk manusia; sifat "cantik" untuk seorang gadis; berwarna "merah" untuk sepeda motor.
Pedoman Praktis Predikabel
Setelah tahu lima term predikabel tersebut maka bagaimana cara menjelaskan sesuatu hal yang baik berdasarkan predikabel di atas. Cara menjelaskan sesuatu yang baik dapat dirumuskan sebagai berikut.
Dalam menjelaskan sesuatu, apa yang dijelaskan tempatkan sebagai spesies, kemudian mencari hubungan genus dan diferensianya, dan jika tidak mendapatkan dicari hubungan genus dengan propriumnya.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas diterapkan pada contoh, misal ingin menjelaskan tentang "hukum".
Hukum sebagai term atau istilah tempatkan sebagai spesies, dan genus istilah hukum adalah "peraturan" yaitu term yang lebih luas dari istilah hukum sehingga istilah "peraturan" mencakup istilah hukum, dan diferensianya adalah "bersifat memaksa".
Genus : peraturan
Spesies : hukum
Diferensia : bersifat memaksa
Dari uraian diatas tersebut, penjelasan hukum dapat dirumuskan secara sederhana dan sulit dipatahkan:
Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa.
Genus untuk menjelaskan sesuatu dapat juga merupakan term yang lebih luas dari term yang dibicarakan. Contoh penjelasan lain tentang filsafat .
Genus : pemikiran kritik dan sistematik
Spesies : filsafat
Diferensia : untuk mencari hakikat atau kebenaran sesuatu
Penjelasan tentang "filsafat" dirumuskan sebagai berikut :
Filsafat adalah pemikiran secara kritik dan sistematik untuk mencari hakikat atau kebenaran sesuatu.
Cara memberi penjelasan tersebut merupakan paling singkat dan tidak mudah ditumbangkan oleh lawan bicara atau orang lain yang ingin menumbangkan. Cara penjelasan tersebut merupakan yang paling baik dan tepat. perlu diingat tidak boleh menjelaskan sesuatu dengan menghubungkan antara genus dan aksiden, hubungan ini tidak akan menjelaskan sesuatu. Oleh karena itu, untuk menjelaskan yang baik perlu ditempuh dengan teori tersebut di atas dan teori itulah yang praktis dan mudah dipahami oleh lawan bicara atau yang membutuhkan penjelasan.
KEGIATAN BELAJAR 3 :
PRINSIP DASAR DAN SESAT PIKIR
Penalaran untuk mencapai suatu kebenaran harus berpegang pada suatu kaidah-kaidah logika sehingga penalaran terhindar dari kesesatan berpikir, dan mudah ditelusuri pangkal pikirnya.
Kaidah-kaidah logika yang paling dasar disebut "prinsip penalaran" dan "prinsip-prinsip penyimpulan" yang dapat menghindari kesesatan berpikir atau "sesatpikir" (fallacy), yang berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika.
Dalam kegiatan belajar ini khusus membicarakan tentang "prinsip penalaran" yang ada empat prinsip, dan "sesatpikir" (fallacy), yang dibedakan tiga kelompok besar bukan secara rinci karena yang terpenting mengikuti kaidah-kaidah logika, yang secara langsung sudah terhindar dari kesesatan berpikir.
A. PRINSIP PENALARAN
Istilah "prinsip' sering diartikan dengan "kaidah" atau "hukum", adapun yang dimaksudkan adalah suatu pernyataan yang mengandung kebenaran universal, yaitu kebenarannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja dapat digunakan.
Untuk hal ini, dibedakan dengan kebenaran yang hanya berlaku pada waktu tertentu atau kebenaran yang hanya berlaku pada tempat tertentu atau juga kebenaran yang hanya berlaku bagi beberapa hal saja dari suatu keseluruhan yang dimaksudkan.
Suatu prinsip jika tidak membutuhkan suatu pembuktian, yang jelas dengan sendirinya karena terlalu sederhana maka prinsip itu disebut dengan "aksioma" atau "prinsip dasar". Dengan demikian, aksioma atau prinsip dasar dapat didefinisikan : "suatu pernyataan mengandung kebenaran universal ysng kebenarannya itu sudah terbukti dengan sendirinya, atau dirumuskan juga, suatu hal diterimanya sebagai kenyataan yang bersifat universal".
Sebagai contoh, salah satu aksioma Euklidus (seorang tokoh Geometrika Iskandariah sekitar tahun 300 SM): "suatu keseluruhan lebih besar dri bagian". Pernyataan ini jelas dengan sendirinya, langsung dapat dimengerti tidak perlu membutuhkan hal-hal lain untuk membuktikan kebenarannya karena memang keseluruhan adalah lebih luas dibandingkan dengan bagian, atau bagian adalah terkandung dalam keseluruhan karena bagian lebih sedikit cakupannya yang berada dalam lingkungan keseluruhan.
Aksioma atau prinsip dasar, setiap ilmu pengetahuan berbeda-beda, namun ada juga suatu aksioma suatu ilmu digunakan juga sebagai aksioma bagi ilmu yang lain. Sebagai contoh, aksioma dari Euklidus diatas, jika diperhatikan ternyata menetapkan suatu ketentuan tentang besaran, suatu masalah yang dihadapi juga di luar Geometrika.
Demikian juga prinsip dasar dalam logika yang akan diuraikan digunakan juga dalam ilmu-ilmu yang lain walaupun tidak dinyatakan tetapi secara langsung sudah melaksanakannya. Prinsip dasar dalam logika sering disebut dengan "aksioma penalaran" atau "prinsip penalaran" dan ada juga yang menyebutnya dengan "prinsip-prinsip pemikiran". Adapun penggunaannya langsung berhubungan dengan menetapkan pernyataan. Oleh karena itu, sebenarnya tepat jika dikatakan "prinsip dasar pernyataan". Prinsip penalaran ini merupakan dasar sifat ilmiah yang harus diikuti.
Prinsip dasar pernyataan atau aksioma penalaran pada dasarnya hanya ada tiga prinsip, yang dikemukakan pertama kali oleh Aristoteles (384-322 SM), adapun prinsip kedua mengalami penyempurnaan dalam menyatakannyadan tanpa mengubah makna yang dimaksudkannya, yaitu prinsip identitas, prinsip nonkontradiksi, dan prinsip eksklusi tertii. Tiga prinsip dari Aristoteles ditambah satu lagi oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) menjadi empat prinsip.
1. Prinsip Identitas
Prinsip Identitas dalam istilah Latin ialah principium identitas (law of identity), merupakan dasar dari semua penalaran, sifatnya langsung analitik dan jelas dengan sendirinya, tidak membutuhkan pembuktian. Prinsip identitas menyatakan : "sesuatu hal adalah sama dengan halnya sendiri".
Dengan kata lain, "sesuatu yang disebut p maka sama dengan p yang dinyatakan itu sendiri bukan yang lain". Secara simbolik dirumuskan sebagai berikut :
Prinsip ini menyatakan bahwa sesuatu benda adalah benda itu sendiri, tidak mungkin yang lain. Dalam suatu perbincangan atau suatu naskah jika sesuatu hal diartikan sesuatu p tertentu maka selama perbincangan itu masih berlangsung atau dalam satu kesatuan naskah tidak boleh diartikan selain p., harus tetap sama dengan arti yang diberikan semula atau konsisten.
Dengan rumusan lain, pengakuan bahwa benda ini adalah benda ini bukan benda lain, dan bahwa benda itu adalah benda itu bukan benda yang lain. Jadi, singkatnya dalam penalaran apa pun harus konsisten.
Contoh dalam suatu sistem filsafat Pancasila jika dinyatakan bahwa "takwa yang sebenar-benarnya" merupakan dasar ajaran moral Pancasila yang terkandung dalam pengamalan sila pertama menjiwai pengamalan sila-sila yang lainnya maka sampai kapan pun harus identik bahwa "takwa yang sebenar-benarnya" adalah dasar moral Pancasila.
Dengan dasar ajaran moral Pancasila tersebut jika mengamalkan sila pertama yang sebenar-benarnya atau murni dan konsekuen pasti secara langsung teramalkan sila-sila yang lain.
Prinsip ini menuntut adanya sifat yang konsiosten dalam suatu penalaran, jika suatu himpunan beranggotakan sesuatu maka sampai kapan pun tetap himpunan tersebut beranggotakan sesuatu tersebut. Sifat ini mendasari dan memperkuat adanya sifat ilmiah yang merupakan dasar penalaran yang pertama, yaitu harus konsisten atau dengan kata lain harus bersifat koheren.
2. Prinsip Nonkontradiksi
Prinsip nonkontradiksi dalam istilah Latin ditulis principium contradictionis (law of contradictions), yakni prinsip kontradiksi. Penyebutan prinsip kontradiksi ini adalah tidak tepat karena yang dimaksudkan adalah tidak adanya kontradiksi dalam suatu pernyataan, bukan kontradiksi itu sendiri yang menjadi prinsip. Prinsip Nonkontradiksi yakni tidak adanya suatu kontradiksi, ayitu menghindari atau mengingkari kontradiksi. Prinsio nonkontradiksi menyatakan: "sesuatu tidak dapat sekaligus merupakan hal itu dan bukan hal itu dalam suatu kesatuan" atau "sesuatu pernyataan tidak mungkin mempunyai nilai benar dan tidak benar pada saat yang sama". Dengan kata lain, "sesuatu tidaklah mungkin secara bersamaan merupakan p dan non p". Secara simbolik dirumuskan sebagai berikut :

Prinsip ini menyatakan juga bahwa dua sifat yang berlawanan penuh (secara mutlak) tidak mungkin ada pada suatu benda dalam waktu dan tempat yang sama. Dalam suatu perbincangan, misal suatu pernyataan "badan benda x ini hidup dan tidak hidup". Kedua term yang sebagai sifat untuk badan benda x itu tidak mungkin diterima kedua-duanya dalam saat yang sama, walaupun benda x itu dapat dibenarkan pada suatu saat hidup dan pada saat yang lain tidak hidup, namun tidak mungkin keduanya bersamaan waktu. Dalam suatu naskah sebagai kesatuan tidak dibenarkan adanya x sebagai p dan sekaligus juga x bukan p sehingga prinsipnya adalah jangan berbuat kontradiksi dalam satu kesatuan penalaran.
Contoh dalam suatu sistem filsafat Pancasila jika doinyatakan bahwa "takwa yang sebenar-benarnya" merupakan dasar ajaran moral Pancasila yang terkandung dalam pengamalan sila pertama menjiwai pengamalan sila-sila yang lain.
Kemudian dalam bagian yang lain dalam kesatuan sistem filsafat Pancasila dinyatakan bahwa "takwa yang sebenar-benarnya" bukan dasar ajaran moral Pancasila. Dalam kesatuan sistem filsafat Pancasila atas dasar dua pernyataan tersebut terdapatlah suatu kontradiksi, prinsipnya janganlah berbuat suatu kontradiksi, akan menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penalaran.
Dalam penalaran himpunan prinsip nonktradiksi sangat penting, yang dinyatakan bahwa sesuatu hal hanyalah menjadi anggota himpunan tertentu atau bukan anggota himpunan tersebut, tidak dapat menjadi anggota dua himpunan yang berlawanan penuh.
Himpunan H dan bukan H merupakan himpunan yang berbalikan tidak mungkin mempunyai anggota yang sama. Jadi, x sebagai suatu anggota tidak mungkin menjadi anggota himpunan H dan juga sekaligus menjadi anggota himpunan nonH. Dengan kata lain: "sesuatu (x) tidaklah mungkin secara bersamaan merupakan p dan non p", p dan nonp adalah kontradiksi.
Prinsip kedua ini memperkuat prinsip identitas, yaitu dalam sifat yang konsisten harus tidak ada kontradiksi di dalamnya. Tidaklah demikian halnya bahwa H dan nonH mempunyai keanggotaan yang sama. H dan nonH adalah kontradiksi. Oleh karena itu, dalam menalar apa pun sebagai kesatuan prinsipnya janganlah berbuat suatu kontradiksi jika ada kontradiksi akan menimbulkan ketidakkonsistenan dalam suatu penalaran, atau dengan kata lain tidak logika, yang berarti tidak sah menurut akal.
3. Prinsip Eksklusi Tertii
Prinsip eksklusi tertii dalam istilah Latin ialah principium exclusi tertii (law of excluded middle), yakni prinsip penyisihan jalan tengah atau prinsip tidak adanya kemungkinan ketiga. Prinsip eksklusi tertii menyatakan: "sesuatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu maka tidak ada kemungkinan ketiga yang merupakan jalan tengah". Dengan kata lain " sesuatu x mestilah p dan nonp tidak ada kemungkinan ketiga".
Kemungkinan ketiga yang dimaksudkan di sini ialah "p" dan "nonp" sekaligus atau "nonp" dan "non-non p" bersamaan, hal ini tidak mungkin, berdasarkan prinsip nonkontradiksi karena "p dan nonp" adalah kontradiksi, dan yang menjadi prinsip adalah "hanya p atau nonp". Prinsip eksklusi tertii merupakan pendukung prinsip nonkontradiksi. Prinsip ini secara simbolik dirumuskan sebagai berikut :

Prinsip ini menyatakan juga bahwa dua sifat yang berlawanan penuh (secara mutlak) tidak mungkin kedua-duanya dimiliki oleh suatu benda. mestilah hanya salah satu yang dapat dimilikinya sifat p atau nonp. Dengan kata lain, dapat dinyatakan juga bahwa salah satu dari dua sifat yang berlawanan penuh mestilah benar bagi salah satu dan tidak benar bagi yang lain, tidak mungkin keduanya benar atau keduanya salah, misalnya benda hidup x ini manusia atau bukan manusia. Jika dinyatakan sebagai manusia dinilai benar, sesuai dengan kenyataannya maka bukan manusia adalah salah karena jelas tidak sesuai dengan kenyatannya, sebaliknya dinyatakan sebagai manusia dinilai salah maka bukan manusia adalah benar, tidak ada kemungkinan ketiga, yaitu keduanya benar atau keduanya salah pada satu benda.
Dalam suatu pola penalaran, jelaslah tidak mungkin ada sesuatu hal yang menjadi jalan tengah atau kemungkinan ketiga antara dua hal yang berlawanan penuh. Antara "manusia" dan "bukan manusia" tidak ada sesuatu makhluk yang berada di antara keduanya, yaitu "manusia yang bukan manusia".
Demikian juga dalam penalaran himpunan dinyatakan bahwa di antara dua himpunan yang berlawanan penuh tidak ada sesuatu anggota berada di antaranya, tidak mungkin ada sesuatu diantyara himpunan H dan himpunan nonH sekaligus.
Contoh dalam suatu sistem filsafat Pancasila, jika dinyatakan bahwa "takwa yang sebenar-nemarnya" merupakan dasar ajaran moral Pancasila, kemudian dalam bagian yang lain dalam kesatuan sistem filsafat Pancasila dinyatakan juga bahwa "takwa yang sebenar-benarnya" bukan dasar ajaran moral Pancasila.
Dalam kesatuan sistem filsafat Pancasila atas dasar dua pernyataan tersebut terdapatlah suatu kontradiksi, yang kedua-duanya tidak mungkin diterima, yang diterima hanyalah salah satu diantaranya dan juga tidak ada kemungkinan ketiga diantara keduanya.
Prinsip ketiga ini memperkuat prinsip identitas dan prinsip nonkontradiksi, yaitu dalam sifat yang konsisten tidak ada kontradiksi di dalamnya dan jika ada kontradiksi maka tidak ada sesuatu diantaranya sehingga hanyalah salah satu yang diterima.
Tidak demikian halnya bahwa H dan nonH mempunyai keanggotaan yang sama, hanya anggota H atau anggota nonH saja. Oleh karena itu, dalam menalar apa pun jika terdapat suatu kontradiksi hanyalah diterima salah satu diantaranya.
4. Prinsip Cukup Alasan
Disamping tiga prinsip yang dikemukakan oleh Aristoteles diatas, seorang filsuf Jerman Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) menambah satu prinsip yang merupaka pelengkap atau tambahan bagi prinsip identitas, yaitu prinsip cukup alasan.
Prinsip cukup alasan dalam istilah Latin disebut dengan principium rationis sufficientis (law of sufficient reason), yang menyatakan: "suatu perubahan yang terjadi pada sesuatu hal tertentu mestilah berdasarkan alasan yang cukup, tidak mungkin tiba-tiba berubah tanpa sebab-sebab yang mencukupi".
Dengan kata lain "adanya sesuatu itu mestilah mempunyai alasan yang cukup, demikian pula jika ada perubahan pada keadaan sesuatu", misalnya jika suatu benda jatuh ke tanah, alasannya ialah karena adanya daya tarik bumi; sedangkan benda itu tidak ada yang menahannya.
Prinsip cukup alasan ini dinyatakan sebagai tambahan bagi prinsip identitas karena secara tidak langsung menyatakan bahwa sesuatu benda mestilah tetap tidak berubah, artinya tetap sebagaimana benda itu sendiri, tetapi jika kebetulan terjadi suatu perubahan maka perubahan itu mestilah ada sesuatu yang mendahuluinya sebagai penyebab perubahan itu.
B. SESATPIKIR
Sesatpikir adalah kekeliruan dalam penalaran beryupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulannya tidak sah.
Sesatpikir ini banyak sekali macamnya yang dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu sesatpikir formal (formal fallacies) dan sesatpikir informal (informal fallacies). Sesatpikir informal ada dua macam kelompok, yaitu sesatpikir pertalian dan sesatpikir kemaknagandaan.
Menurut ahli, logika umumnya dibedakan tiga jenis sesatpikir, yaitu sesatpikir formal (formal fallacies), sesatpikir verbal (verbal fallacies), dan sesatpikir material (material fallacies)
1. Sesatpikir Formal
Sesatpikir formal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesatpikir menurut logika (logical fallacies). Sesatpikir ini banyak ragamnya, salah satu misalnya "mengiyakan suatu pilihan dalam suatu susunanpikir pengatauan yang merangkum".
Susunanpikir pengatauan dapat merangkum yang disebut silogisme disjungsi inklusif. Pangkal pikirnya berupa pernyataan pengatauan yang dapat merangkum yang dirumuskan dalam bentuk p atau q, yang kemudian disusun dalam susunanpikir sebagai berikut :
p atau q
dan, ternyata p
maka, kesimpulannya bukan q
Perbincangan dengan menggunakan cara seperti di atas tidak senantiasa benar, misalnya :
Peserta kursus adalah mahasiswa atau guru,
Dan, ternyata mahasiswa yang kursus,
Berarti, dia bukan guru.
Penyimpulan seperti perbincangan di atas itu meragukan. Sesatpikir demikian ini sering dilakukan orang sebab mirip dengan cara menetapkan salah satu bagian kesimpulannya mengingkari.
2. Sesatpikir Verbal
Sesatpikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni bertalian dengan penggunaan yang salah satau kemaknagandaan dari sesuatu kata, dan dikenal juga sebagai sesatpikir arti kata (semantic fallacies). Sesatpikir ini banyak ragamnya, salah satu misalnya "susunanpikir terdiri atas empat konsep", Aturannya tiga konsep, tetapi konsep pembandingnya bermaknaganda.
Dalam susunanpikir kategori atau silogisme kategori (categorical syllogism) yang sah hanya terdiri tiga konsep, yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, dan konsep tengah yang menjembatani subjek dan predikat tersebut menjadi kesimpulan. Sesatpikir empat konsep ini biasanya terjadi karena dipergunakan konsep yang bermaknaganda bagi konsep tengahnya, misalnya:
Semua rumah mempunyai halaman
Modul logika ini mempunyai halaman
Maka, modul logika ini adalah rumah
Kata "halaman" yang berperan sebagai konsep tengah pada contoh di atas bermaknaganda sehingga susunanpikir tersebut mengandung empat konsep, yakni rumah, mempunyai halaman (pelataran), buku, dan mempunyai halaman (pagina).
3. Sesatpikir Material
Sesatpikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Sesatpikir ini banyakl ragamnya, salah satu misalnya "perumuman yang tergesa-gesa".
Sesaypikir ini terjadi dalam sesauatu perbincangan induksi karena membuat umum sesuatu hal berdasarkan hal-hal khusus atau contoh-contoh yang terlampau sedikit, misalnya:
setelah mengamati sekeranjang apel yang dijajakan di tepi jalan dan melihat sekelompok apel di atas
cukup besar-besar,
Kemudian menyimpulkan bahwa setiap apel dalam keranjang itu besar-besar.
Perumuman yang terlampau luas dari bahan yang ada dan jauh melampaui lingkup bahan pembuktiannya, tergesa-gesa disimpulkan juga termasuk sesatpikir ini.
Penetapan sampel yang jumlahnya sabgat terbatas atau berdasar berita di televisi, misal :
Kita melihat banyak anggota legislatif yang korupsi, kemudian menyimpulkannya, Semua anggota
legislatif adalah korupsi.
Pemilihan sampel yang salah dalam statistik dapat juga menjadi sebab terjadinya sesatpikir ini. Pernyataan, seperti "semua karyawan dan pejabat adalah koruptor".
MODUL 3 :
ANALISIS DAN DEFINISI
Penalaran merupakan pemikiran yang berusaha mencari kesimpulan dari pangkal pikir yang telah ditentukan dan untuk sanggup menalar dengan baik diperlukan analisis untuk menguraikan hal yang menjadi pangkalpikir dan juga perlu mengadakan klasifikasi untuk menentukan pangkal pikir tersebut bersifat umum atau tidak. Analisis maupun klasifikasi atau pembagian maupun penggolongan merupakan salah satu unsur sarana ilmiah yang akan bermanfaat dalam membuat suatu penjelasan atau definisi.
Analisis pada dasarnya merupakan suatu sarana untuk memahami suatu konsep atau sesuatu hal atas dasar sifat, hubungan, dan perananan masing-masing unsur dalam kesatuan konsep tersebut. Analisis merupakan hal yang sangat diperlukan dalam penalaran ilmiah untuk membuktikan konsep yang dibangun tersebut betul-betul didukung oleh bagian-bagian dari konsep tersebut.
Kebalikan analisis adalah klasifikasi yang merupakan pengelompokan sifat, hubungan maupun peranan masing-masing unsur yang terpisah dalam suatu keseluruhan untuk memahami sesuatu konsep universal.
Analisis diperlukan juga untuk membuat suatu definisi atau penjelasan arti yang baik sehingga definisinya betul-betul tepat. Hal ini sangat diperlukan di bidang ilmiah karena bahasa ilmiah membutuhkan suatu definisi supaya yang mendapatkan informasi ilmiah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pemberi informasi untuk menghindari kesalahpahaman. Sebelumnya telah diuraikan salah satu fungsi bahasa adalah fungsi simbolik karena komunikasi ilmiah bertujuan untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan.
Dalam komunikasi ilmiah harus jelas dan objektif, oleh karena itu istilah-istilah yang digunakan harus didefinisikan untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh istilah tersebut. Untuk memberi definisi atau penjelasan yang baik harus jelas dan singkat, serta mudah dipahami, tidak menggunakan bahasa yang panjang lebar dan berbelit-belit. Oleh karena itu, perlu juga diuraikan bagaimana cara membuat definisi serta macam-macam definisi, dan juga syarat-syarat apa yang harus diikuti supaya definisinya baik.
KEGIATAN BELAJAR 1 :
ANALISIS ATAU PEMBAGIAN
Dasar untuk sanggup berpikir ataupun menalar yang baik perlu juga menjalankan prinsip analisisi atau pembagian. Analisis merupakan proses mengurai sesuatu hal menjadi berbagai unsur yang terpisah untuk memahami sifat, hubungan, dan peranan masing-masing unsur.
Tujuan analisis, diantaranya untuk mendapatkan makna terbaru dari hal atau konsep yang sama, selanjutnya dapat dikuasai konsep-konsep atau pengertian-pengertian kemudian diungkapkan dalam bentuk-bentuk term. Konsep dan term inilah sebenarnya yang sebagai unsur dalam penalaran.
Analisis atau pembagian akan diuraikan secara terperinci beserta hukum-hukumnya untuk sebagai landasan penalaran. Disamping itu, perlu juga diuraikan klasifikasi sebagai kebalikan dari analisis.
A. PENGERTIAN ANALISIS
Analisis secara umum, sering juga disebut dengan penguraian atau pembagian. Dalam logika, analisis atau pembagian berarti pemecah-belahan atau penguraian secara jelas berbeda ke bagian-bagian dari suatu keseluruhan.Untuk lebih seksama dapat juga mengadakan subbagian, yakni menguraikan atau memecah belah dari suatu bagian sampai ke unsur dasarnya. Dengan dasar batasan arti tersebut maka yang dapat dianalisis atau diuraikan adalah suatu keseluruhan jika betul-betul tinggal tidak dapat diuraikan ke bagian-bagiannya.
Bagian dan keseluruhan selalu berhubungan. Suatu keseluruhan adalah terdiri atas bagian-bagian, oleh karena itu dapat dipecah-pecahkan dan diuraikan. Bagian merupakan hal-hal yang menyusun suatu keseluruhan maka keseluruhan dapat dibagi-bagi. Sebelum membahas tentang analisis perlu juga dijelaskan terlebih dahulu tentang keseluruhan.
Keseluruhan pada umumnya dibedakan antara keseluruhan logika dan keseluruahn realis. Keseluruhan logika atas dasar konsepnya, sedang Keseluruhan realis atas dasar materinya, misal istilah "manusia" dapat dari segi konsep dan dapat juga dari segi orangnya. Keseluruhan logika adalah keseluruhan yang dapat menjadi predikat masing-masing bagiannya, misalnya "tumbuh-tumbuhan" sebagai suatu keseluruhan, dan "mangga", 'durian", "pepaya" sebagai bagian-bagiannya sehingga dapat dinyatakan mangga adalah tumbuh-tumbuhan, durian adalah tumbuh-tumbuhan, pepaya adalah tumbuh-tumbuhan.
Demuikian juga manusia sebagai suatu konsep yang terdiri atas berbagai bangsa dapat digunakan predikat masing-masing bangsa tersebut, misalnya bangsa Indonesia adalah manusia, bangsa Israel adalah manusia, bangsa Arab adalah manusia. Keseluruhan realis adalah keseluruhan yang tidak dapat dijadikan predikat masing-masing bagiannya, misalnya "rumah" sebagai suatu keseluruhan, dan "kamar" sebagai bagiannya maka tidak dapat dinyatakan bahwa: "kamar adalah rumah".
Demikian juga manusia dari segi materinya atau orangnya tidak dapat digunakan sebagai predikat, misal tangan adalah manusia, badan adalah manusia. Dalam penggunaan biasa yang dimaksudkan dengan suatu keseluruhan adalah keseluruhan realis, sedangkan keseluruhan logika adalah suatu konsep universal dan bagian-bagiannya adalah hal-hal yang tercakup di dalamnya.
B, MACAM-MACAM ANALISIS
Jika keseluruhan dapat dibedakan antara keseluruhan logika dan keseluruhan realis maka analisis atau pembagian dibedakan juga atas dua kelompok, seperti analisis logika, yaitu penguraian atas dasar konsepnya dan analisis realis, yaitu penguraian atas dasar materinya.
1. Analisis Logika
Analisis Logika adalah pemecah-belahan sesuatu ke bagian-bagian yang membentuk keseluruhan atas dasar prinsip tertentu. Pemecah-belahan ini menjelaskan keseluruhan atau himpunan yang membentuk term sehingga mudah dibeda-bedakan.
Analisis Logika selalu merupakan pembagian suatu himpunan ke dalam subhimpunan, bukan merupakan pembagian himpunan ke dalam atribut-atributnya. Analisis Logika dibedakan atas dua macam, yaitu analisis universal dan analisis dikotomi.
a. Analisis Universal
Analisis universal merupakan pemerincian atau penguraian suatu genus dibagi kedalam semua spesiesnya, atau juga dirumuskan pemecah-belahan term umum ke term-term khusus yang menyusunnya, misalnya "hewan" dibagi atas manusia, gorila, kerbau, dan sebagainya. Term "manusia" dibagi atas bangsa Indonesaia, bangsa Amerika, bangsa yahudi, bangsa Cina, dan sebagainya. "Bangsa Indonesia" dipeinci terdiri atas suku Jawa, suku Bali, suku Sumatera' suku Kalimantan, dan berbagai suku di Indonesia. "Rakyat Indonesia keturunan asing" dibagi ata keturunan Cina, keturunan India, keturunan Arab, dan keturunan bangsa-bangsa lain.
Analisis Universal untuk hal-hal yang sederhana lebih tepat diterapkan, akan tetapi untuk hal-hal yang kompleks susunannya, analisis universal mungkin tidak tepat, bahkan untuk hal-hal yang tidak dapat semua diketahui, analisis universal tidak dapat diterapkan karena mungkin ada sesuatu bagiannya yang belum dapat diketahui.
b. Analisis dikotomi
Analisis dikotomi merupakan pemecah-belahan sesuatu dibedakan menjadi dua kelompok yang saling terpisah, yang satu merupakan term positif yang lain term negatif. Analisis dikotomi ini didasarkan atas hukum logika "prinsif eksklusi tertii", yakni prinsip penyisihan jalan tengah (prinsip ini sudah dibahas dalam modul kedua).
Analisis dikotomi harus menentukan suatu diferensia yang dipilih membentuk term positif dan kebalikannya membentuk term negatif. Contoh analisis sebagaimana yang berlaku di Indonesia tentang pembagian ilmu yang pada umumnya dibedakan atas dua macam, yaitu ilmu dibedakan atas eksakta dan non-eksakta. Term "eksakta" adalah term positif, dan term "non-eksakta" adalah term negatif.
Contoh analisis dikotomi yang lain sebagaimana dikemukakan oleh Porphyrios dalam karyanya Isagoge, tentang klasifikasi alam semesta sebagaimana diuraikan dalam modul kedua, yakni dari "summum genus" berupa substansi, ke "infima spesies", yaitu manusia atau juga term yang paling umum ke term khusus yang menyusunnya (lihat pembagian dari term substansi ke term manusia).
Metode analisis dikotomi ini sederhana dan lengkap disamping itu juga tegas, adapun kekurangannya ialah bahwa bagian yang negatif dari dikotomi itu mungkin tidak beranggota (himpunan kosong) dan seandainya mempunyai anggota juga tidak dapat diperoleh kketerangan mengenai anggota-anggota tersebut karena anggota-anggota itu tidak dibagi-bagi lebih lanjut.
2. Analisis Realis
Analisis realis adalah pemecah-belahan berdasarkan atas susunan benda yang merupakan kesatuan atau atas dasar sifat perwujudan bendanya. Analisis Realis dibedakan menjadi dua macam, analisis esensial dan analisis aksidental.
a. Analisis esensial
Analisis esensial merupakan pemecah-belahan sesuatu hal ke unsur dasar yang menyusunnya.
Misalnya :
Manusia dibagi atas jiwa dan raga
Air dibagi atas dua hidrogen dan satu oksigen (H2O)
Rumah dibagi atas kamar, ruang tamu, dan ruang makan
b. Analisis aksidental
Analisis aksidental merupakan pemecah-belahan sesuatu hal berdasarkan sifat-sifat yang menyertai perwujudannya.
Misalnya :
Kucing dapat putih, coklat, hitam, dan warna lain.
Gerak dapat molar, molekular, atau atomis, dan lain-lain.
Manusia dibagi atas warna kulit, yaitu : berkulit putih dan berwarna.
C. HUKUM-HUKUM ANALISIS
Dalam analisis ada aturan-aturan tertentu yang menjadi petunjuk untuk mengadakan analisis secara ideal supaya hasilnya tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan.
1. Analisis atau pembagian harus berjalan menurut sebuah asas tunggal, yakni harus mengikuti prinsip atau sudut pandangan yang sma. Sesuatu asas dapat dipilih sehubungan dengan maksud tujuan anlisis, tetapi apabila sekali telah dipilih maka hendaknya jangan diubah selama proses analisis berlangsung.
Misal :
Jika menganalisis bangunan gedung menurut asas fungsinya tidak boleh beralih menurut gaya arsiteknya selama proses analisis itu berlangsung. Prinsip ini jika dilanggar akibatnya adalah hasilnya tidak teratur.
2. Analisis atau pembagian harus lengkap dan tuntas, yakni spesies-spesies yang merupakan bagian-bagian penyusunnya apabila dijumlahkan harus sama dengan genusnya.
Misal :
Jika menganalisis gedung menurut asas fungsinya, dan lupa untuk memasukkan salah satu di antara spesies yang merupakan bagian dari term "fungsi gedung" seperti tempat tinggal maka ditinjau secara logika analisis itu tidak lengkap. Prinsip ini jika dilanggar maka akibatnya ialah dapat membuat kesalahan yang sangat bersahaja dan mencolok , yaitu mengadakan analisis yang tidak lengkap, dan konsekuensinya yang praktis mungkin akan sangat gawat jika analisis itu merupakan bagian suatu survei atau sensus.
3. Analisis atau pembagian harus jelas terpisah antarbagiannya, yakni spesies-spesies penyusun genus terpisah yang satu dengan yang lain.
Misal :
Jika membagi-bagi gedung menurut gaya arsitekturnya, gaya klasik, gaya gotik, gaya eklektis, gaya fungsionalis, gaya modern maka kesalahannya terletak pada saling melingkupinya gaya fungsionalis dan gaya modern. Prinsip ini jelas jika dilanggar akibatnya ialah bahwa spesies-spesies itu saling melingkupi.
D. SISTEM DIKOTOMI
Dalam analisis yang paling mudah dan yang mengandung kepastian adalah dikotomi, Istilah dikotomi berasal dari dichotomia, sebuah kata dari bahasa Grik, artinya bagi-dua. Istilah dikotomi dalam logika bahwa setiap lingkungan jenis (genus) itu dibagi atas dua golongan (species) saja, yakni dua golongan yang saling berlawanan, yang satu positif dan yang lain negatif sehingga disebut sebagai sistem dikotomi.
Contoh dikotomi selain dalam analiis dikotomi diatas, misal membagi lingkungan penganut aliran-aliran politik, yaitu aliran Marxist dan Nonmarxist. Dalam "Nonmarxist" itu tercakup "keseluruhan" aliran-aliran politik lainnya yang dianut oleh setiap orang di dunia, di mana saja dan waktu kapan pun juga.
Nonmarxist itu dapat dibagi lagi menjadi Nazi dan NonNazi. "Nonnazi" itu dapat dibagi lagi menjadi demokrat dan nondemokrat. "nondemokrat" dapat dibagi lagi menjadi aristrokrat dan non-aristrokrat, begitulah seterusnya.
Pada setiap tahap penguraian atau pembagian itu diperoleh kepastian-kepastian, yang tidak perlu diragukan dan disangsikan. Sistem dikotomi itu lebih umum digunakan dewasa ini. Di Indonesia, kita mengenai sistem penguraian atau pembagian dalam dunia usahawan, yaitu pribumi atau nonpribumi. Kemudian yang pribumi dibagi atas orang Jawa dan Nonjawa, sedang yang nonpribumi dibagi atas ornag Cina dan Noncina.
Pada masa kekuasan Nazi di Jerman sebelum perang dunia kedua (1939-1945), manusia seluruhnya dibagi oleh Diktator Adolf Hitler (1889-1945) atas dua golongan saja, yaitu bangsa Aria dan bukan bangsa Aria. Golongan terakhir ini dipandang rendah sehingga dipastikan tunduk di bawah kekuasaan bangsa Aria.
Dikotomi dijadikan alat politis dan alat psikologis bagi meningkatkan derajat golongan sendiri dan merendahkan derajat golongan-golongan lainnya. Akan tetapi, dalam lapangan ilmiah, dikotomi terpandang sistem penguraian atau pembagian yang lebbih mengandung kepastian. Sistem dikotomi ini didasrkan atas "prinsip eksklusi tertii", yakni prinsip penyisihan jalan tengah (prinsip ini sudah dibahas dalam Modul 2, KB 3).
Sistem dikotomi merupakan suatu proses yang mengandung kesederhanaan, tetapi juga mempunyai sifat logis yang ketat sehingga bersifat kepastian. Jika diterapkan pada alam semesta yang dicontohkan dalam analisis dikotomi bahwa sesuatu jenis (genus) dibagi menjadi dua golongan (spesies) positif dan negatif berdasarkan sesuatu ciri pembeda (diferensi) yang ditentukan, kemudian golongan yang positif dibagi lebih lanjut dalam dua subgolongan, demikian seterusnya sampai tercapai kelompok tersempit. Hal ini berkaitan dengan sistem klasifikasi yang akan diuraikan dalam KB 2 dalam modul ini.
Dikotomi ini suatu ajaran logika yang dikemukakan oleh Porphyrios (233-306 M) dalam karyanya yang berjudul Isagoge, suatu pengantar terhadap categoriae karya tulis Aristoteles, yang digambarkannya suatu bagan yang kini terkenal dengan Pohon Porphyrios dari substansi sebagai summum genus sampai ke manusia sebagai infima spesies.
Pohon Porphyrios dapat juga dimulai dari golongan yang terkecil disebut Infima Spesies, kemudian sejumlah infima spesies dapat dikelompokkan menjadi golongan yang lebih besar disebut proximum genus. Demikianlah seterusnya penggolongan itu dapat dilanjutkan sehingga mencapai golongan yang tertinggi yang disebut summum genus.
KEGIATAN BELAJAR 2 :
KLASIFIKASI ATAU PENGGOLONGAN
Dasar untuk menalar yang baik di samping menjalankan prinsip
analisis sering juga diadakan klasifikasi, yang keduanya berhubungan. Analisis
merupakan proses mengurai sesuatu hal menjadi berbagai unsur yang terpisah
untuk memahami sifat, hubungan, dan peranan masing-masing unsur, sedang
klasifikasi merupakan proses pengelompokan sifat, hubung maupun peranan
masing-masing unsur yang terpisah dalam keseluruhan untuk memahami sesuatu
konsep universal. Dengan dua prinsip ini, selanjutnya dapat dikuasai
konsep-konsep atau pengertian-pengertian kemudian diungkapkan dalam
bentuk-bentuk term sebagai unsur dasar penalaran. suatu
A. PENGERTIAN KLASIFIKASI
Klasifikasi merupakan kebalikan dari analisis sehingga
sering dinyatakan bahwa kedua hal itu saling berhubungan yang hubungannya
dikatakan berbalikan. Analisis atau pembagian dimulai dari suatu keseluruhan
dan melalui proses yang logika bergerak menurun ke dalam unsur-unsur yang
semakin lama semakin kecil sampai tercapainya unsur yang terendah atau terdasar
maka kebalikannya yang bergerak ke arah yang berlawanan disebut klasifikasi
atau penggolongan, yakni dari barang-barang, kejadian-kejadian, fakta-fakta
atau proses-proses alam kodrat individual yang beraneka ragam coraknya, menuju
ke arah keseluruhan yang sistematik dan bersifat umum (dimiliki bersama) sampai
tercapainya genus yang tertinggi. Analisis atau pembagian lebih erat
hubungannya dengan proses yang semata-mata bersifat formal dalam mengikuti prinsip-prinsip
tertentu, sedangkan klasifikasi ata penggolongan lebih bersifat empirik serta
induktif.
Analisis dan klasifikasi keduanya berhubungan erat sekali
dengan definisi, yakni dalam hal bahwa pemahaman yang jelas tentang arti sebuah
istilah atau juga term sangat diperlukan untuk mengetahui apakah sesuatu objek
tertentu itu masuk dalam istilah tersebut atau di luar. Di samping itu. untuk
mengetahui apakah barang sesuatu itu, merupakan sifat hakikat definisi atau
bukan sifat hakikat definisi atau juga berarti dapat menggolong golongkan barang sesuatu itu secara sistematik dalam hubungannya dengan objek-objek yang lain yang tidak termasuk yang dimaksudkan oleh defin
B. MACAM-MACAM KLASIFIKASI
Dalam mengadakan pembedaan macam-macam lasifica penggolongan yang menjadi pedoman ialah sifat bahan-bahan yang dan digolong-golongkan dan maksud yang dikandung oleh orang yang mengadakan penggolongan. Kedua segi itu dapat dipakai untuk mengan pembedaan yang biasanya dinamakan klasifikasi kodni dan Klasifica buatan dan juga klasifikasi gabungan antara keduanya yang disebut dengan klasifikasi perantara atau klasifikasi diagnostik. Ketiga macam in diuraikan sebagai berikut.
J. Klasifikasi kodrati. Klasifikasi kodrati ditentukan oleh susu kodrat sifat-sifat dan atribut-atribut yang dapat ditemukan dari bahan-bahan yang tengah diselidiki. Sebagai contoh, klasifikan kodrati dan tumbuh- tumbuhan akan didasarkan atas sistem philogenetike statem keturunan bersama. Demikian juga penemuan tengkorak bintang pe digolong-golongkan atas dasar bentuk kepalanya Binatang bu digolong-golongkan atas dasar memakan daging serta dapat teng Tumbuh-tumbuhan digolong-golongkan atas dasar dapat menyembucan penyakit kanker
2. Klasifikasi buatan. Klasifikasi buatan ditentukan oleh sesuatu maksad yang praktis dari seseorang, seperti untuk mempermudah penanganannya dan untuk menghemat waktu serta tenaga. Dalam Klasifikasi but misalnya berupa pembuatan daftar nama-nama tumbuh-tumbuhan secar abjad dalam suatu indeks buku pegangan atau katalogus. Menggolong golongkan mahasiswa pada tahun pertama atas dasar indeks prestasinya 3.5 yang akan dipilih mendapat beasiswa. Menggolong-golongkan mahasiswa pada tahun pertama yang belum mencapai 30 siks dem IP $2
3. Klasifikasi diagnostik Klasifikasi diagnostik merupakan gabungan yang tidak sepenuhnya kodrati dan juga tidak sepenuhnya buatan, yang coraknya mungkin dapat dijumpai dalam suatu bidang yang haru atau yang untuk sebagian berkembang seperti ilmu-ilmu sosial. Klasifican disebut juga klasifikasi perantara. Misalnya, seorang petugas kepolisian menggolong-golongkan peristiwa-peristiwa kejahatan yang terjadi di daerah penugasannya hanya berdasarkan atas waktunya, tempatnya, orang-orang yang terlibat, dan sifat-sifat pelanggaran hukumnya, untuk dicatat dalam buku daffar kantor kepolisian setempat untuk dipergunakan di hari depan.
Pembedaan klasifikasi diterapkan pada peristiwa-peristiwa kejahatan contoh di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Jika yang menjadi pedoman klasifikasi adalah maksud untuk mempermudah pekerjaan maka klasifikasinya bersifat buatan. Akan tetapi, seorang petugas dinas soal mungkin mencoba untuk menggolong golongkan peristiwa-peristiwa yang sama berdasarkan atas faktor-faktor penyebab yang untuk sebagian diketahui dan diduga, seperti ketidakseimbangan psikologis dan sosial, untuk mengurangi terjadinya peristiwa-peristiwa semacam itu dengan jalan mengubah atau memperbaiki keadaan-keadaan yang menyebabkannya. Oleh karena bersifat menjajaki dan belum selesai maka klasifikasi ini barangkali harus dipandang bersifat diagnostik. Akan tetapi, apabila riset secara besar-besaran terhadap peristiwa-peristiwa yang bersangkutan dilanjutkan oleh para ahli kriminologi dan antropologi sedemikian rupa sehingga peristiwa-peristiwanya digolong-golongkan menurut asal-usul rasnya, corak darah, bangun kepala, daya tengkorak kepala, dan ciri-ciri susunan tubuh yang lain maka dapatlah dibenarkan jika dipandang klasifikasi ini sebagai klasifikasi kodrati
C.
HUKUM-HUKUM KLASIFIKASI
Klasifikasi atau penggolongan yang merupakan kebalikan analisis atau pembagian, menurut Herbert L. Searles (dalam bukunya LogicandScientificMethods. An IntroductoryCourse) hukum-hukumnya sama dengan hukum- hukum pembagian, namun macam-macam klasifikasi berbeda dengan macam-macam analisis. Tiga hukum yang mengatur analisis secara logika yang telah diuraikan di depan diterapkan pada klasifikasi, meskipun hukum-hukum itu tidak dapat diikuti dengan begitu tegar. Hukum-hukum klasifikasi atau penggolongan yang sama intinya dengan hukum-hukum analisis dapat ditentukan sebagai berikut.
1.
Klasifikasi atau penggolongan harus hanya ada satu asas tertentu. Hukum ini
berlaku juga pada beberapa pengelompokan yang berada dalam satu konsep umum.
Dengan menaati hukum bahwa harus hanya ada satu asas berarti dapat terjamin
diperolehnya susunan yang logika dan menghindari terdapatnya klasifikasi yang bersilang, atau klasifikasi simpang siur antara kelompok satu dengan kelompok lain.
2. Suatu klasifikasi atau penggolongan harus sampai tuntas dan jelas. Hukum bahwa klasifikasi harus sampai tuntas merupakan harapan yang hanya untuk sebagian dapat dipenuhi dalam bidang yang bertambah luas seperti ilmu-ilmu sosial atau di dalam ilmu yang dinamik, seperti biologi, botani, zoologi. Klasifikasi yang tidak lengkap baru merupakan suatu kekurangan yang gawat apabila ilmunya telah menjadi sistematik serta saling berhubungan dan hukum-hukum yang mengatur proses evolusi telah diketahui.
3. Unsur-unsur sebagai bagian untuk menyusun konsep universal harus jelas terpisah satu dengan yang lain. Hukum yang mengatakan bahwa unsur-unsur yang merupakan bagian untuk menyusun konsep universal harus terpisah yang satu dengan yang lain dalam suatu klasifikasi atau penggolongan merupakan suatu harapan yang hanya akan dapat dicapai sejauh sifat-sifat unsur atau spesies dan berhubungan dengan itu anggota-anggota berbagai spesies itu telah diketahui.
Dalam Modul 2 Kegiatan Belajar 2 telah diuraikan tentang term berdasarkan predikubel, yaitu cara menjelaskan atau cara menerangkan sesuatu. Cara menjelaskan sesuatu yang baik pada dasarnya harus mengetahui lima kelompok jenis sebutan (predicable), yaitu genus, spesies, diferensia, proprium, dan aksiden.
Dalam modul ini, lima kelompok jenis sebutan dibicarakan dalam kerangka sistem klasifikasi. Klasifikasi atau penggolongan dimulai dari infima spesies kemudian dari sejumlah infima spesies dapat dikelompokkan menjadi golongan yang lebih besar. Himpunan yang lebih tinggi dari suatu kelompok dinamakan proximum genus yaitu jenis (genus) yang terdekat dari suatu kelompok.
Demikian seterusnya penggolongan itu dapat dilanjutkan sehingga mencapai golongan yang tertinggi yang disebut summum genus. Semua himpunan yang terdapat di antara infima spesies dan summum genus dinamakan subaltern genera. Pengelompokan itu dibahas lingkungan- lingkungan zat dan lingkungan-lingkungan sifat di alam semesta.
Klasifikasi atau penggolongan pertama kali dikemukakan oleh Porphyrios (233-306 M) untuk menguraikan alam semesta dalam karyanya berjudul Eisagoge (telah diuraikan dalam Kegiatan Belajar modul ini yang terkenal dengan nama Pohon Porphyrios.
Di alam semesta hakikatnya berdasarkan satu kesatuan asal, akan terjadi perbedaan-perbedaan bentuk belaka. Disebabkan perbedaan bentuk itu maka terjadilah lingkungan-lingkungan dari segala sesuatunya (HM. JoesoefSouyb, 1983).
Porphyrios menemukan dua lingkungan materi, yaitu lingkungan jenis (genus) dan lingkungan golongan (spesies), keduanya disebut lingkungan zat Faktor yang menentukan lingkungan jenis dan lingkungan golongan atau lingkungan genus dan lingkungan spesies ialah sifat sesuatunya. Porphyrios membagi ada tiga macam, yaitu sifat pembeda atau diferensia (Latin differentia), sifat khusus atau proprium (Latin: proprium), dan sifat kebetulan atau aksiden (Latin: accidens).
1. Genus
Lingkungan genus (penjelasan yang lain) ialah "himpunan berbagai ragam bentuk, tetapi terpadu dalam satu lingkungan disebabkan kesatuan sifat". Contoh pengertian hewan. Di dalam pengertian hewan itu termasuk manusia, orang utan, gorila, simpanse, monyet, singa, harimau, gajah, sampai pada bacil-bacil (bakteri berbentuk batang) paling halus. Satu per satu punya perbedaan bentuk, tetapi semuanya itu terpadu dalam satu lingkungan genus disebabkan kesatuan sifat bahwa sama-sama memiliki nyawa, yakni yang bernyawa.
Lingkungan genus itu punya tingkatan-tingkatan yang dibedakan atas tiga macam yaitu sebagai berikut. a. Genus jauh atau genus tertinggi (Latin: summum genus): genus yang tidak ada genus lain di atasnya dan memuat genus-genus di bawahnya, misalnya "ada yang fana", "substansi", "aljauhar". Genus ini disebut juga "genus hakiki".
b. Genus tengah atau genus perantara (Latin: subalterngenera): genus yang di atasnya ada genus yang lebih umum, dan di bawahnya ada genus yang lebih khusus, misalnya "organisme", "badani", genus di atasnya adalah substansi, genus di bawahnya adalah hewan.
c. Genus dekat atau genus terbawah (Latin: proximum genus): genus yang langsung berada di atas golongan, misalnya "hewan", dalam hubungannya dengan term manusia, "binatang melata", dalam hubungannya dengan ular, buaya, dan ulat.
Tingkatan-tingkatan yang dimaksudkan di dalam lingkungan genus itu dapat dijelaskan pada Pohon Porphyrios seperti di bawah ini:
Hewan merupakan lingkungan genus terbawah bagi manusia, gorila, singa, gajah, dan seterusnya. Oleh karena itu, manusia beserta yang lainnya termasuk genus substansi maka substansi lingkungan genus tertinggi bagi manusia, gorila, singa, gajah, dan seterusnya. Akan tetapi, di antara kedua lingkungan itu dijumpai lingkungan genus perantara, yaitu organisme dan jisim.
Manusia itu pun dapat pula dijadikan lingkungan genus terbawah, yang di dalam lingkungan itu termasuk keturunan Causassoid, keturunan Negroid, dan keturunan Mongoloid. Keturunan Causassoid itu pun dapat pula dijadikan lingkungan genus terbawah, yang di dalam lingkungannya itu termasuk berbagai bangsa tertentu begitulah seterusnya. Pada setiap lingkungan genus itu terdapat kesatuan sifat yang menggabungkannya dalam satu lingkungan, sekalipun berbeda ragam bentuk.
Lingkungan spesies (penjelasan yang lain) ialah "himpunan diri yang bersamaan bentuk dan dipadu dalam satu lingkungan oleh satu sifat yang membedakannya dari lain-lain golongan".
Manusia itu sebuah lingkungan spesies di dalam lingkungan genus hewan. Spesies manusia terdiri atas himpunan diri yang bersamaan bentuk Sifat yang memisahkan spesiesnya dari ragam spesies hewan lainnya ialah kemampuan berpikir, yakni "yang berpikir" Dengan kemampuan berpikir yang mampu menciptakan ragam peralatan bagi kebutuhan hidupnya, tidak
dijumpai pada spesies-spesies hewan yang lainnya. Lingkungan spesies dapat ditemukan pada setiap genus kebendaan maupun setiap genus pengertian. Misalnya, pengertian negara yang di dalam lingkungan itu termasuk republik Indonesia, republik Filipina, kerajaan Jepang, kerajaan Thai, kerajaan Malaysia, dan seterusnya. Setiap republik maupun kerajaan itu dipandang kedirian-kedirian tertentu. Spesies ini ada tiga macam, yaitu sebagai berikut..
a. Spesies jauh atau spesies tertinggi: spesies ini sama dengan genus perantara, yakni term universal yang menghimpun golongan-golongan yang dapat berlaku sebagai genus, misalnya "organisme".
b. Spesies tengah atau spesies perantara: spesies ini sama dengan genus terbawah, yakni term universal yang langsung menghimpun golongan-golongan yang tidak dapat berlaku sebagai genus, misalnya "hewan".
c. Spesies dekat atau spesies terbawah: spesies ini disebut "infima spesies" atau "spesies hakiki", yaitu term universal yang di bawahnya hanya ada satuan khusus yang sangat sempit denotasinya sehingga tidak mungkin menjadi suatu genus, misalnya "manusia" di bawahnya terdapat Umar, Mohammad, Ali, dan sebagainya.
Perlu diperhatikan, genus dan spesies adalah nama-nama himpunan sebagai term universal yang berhubungan, lingkungan spesies merupakan bagian dari lingkungan genus. Misalnya, term "manusia" dan term "hewan". denotasi term manusia lebih sempit daripada denotasi term hewan, dengan demikian denotasi manusia merupakan bagian dari denotasi hewan. Himpunan hewan merupakan genus dan himpunan manusia merupakan spesies. Akan tetapi, janganlah dilupakan bahwa genus dan spesies adalah term-term yang relatif, sama halnya dengan term umum dan term khusus jika keduanya berhubungan maka sifatnya relatif. Himpunan yang lebih luas denotasinya disebut genus terhadap himpunan yang lebih sempit denotasinya yang disebut spesies. Oleh karena genus dan spesies adalah term-term yang sifatnya relatif maka suatu term dapat juga menjadi genus dalam hubungannya dengan himpunan yang lebih sempit denotasinya, di samping ia menjadi spesies dalam hubungannya dengan himpunan yang lebih luas. denotasinya. Hubungan semacam ini menyatakan bahwa jika ditinjau dari segi denotasinya genus meliputi spesies dan jika ditinjau dari segi konotasinya spesies meliputi genus. Hubungan antara keduanya dicontohkan sebagai berikut.

3.
Diferensi
Diferensi (differentia) atau sifat pembeda atau juga sifat pemisah (penjelasan yang lain) ialah "suatu tanda pengenal yang menunjukkan hakikat suatu golongan". Oleh karena sifat tersebut menunjukkan hakikat maka jika sifat tersebut tidak ada maka eksistensi dari golongan itu pun tidak ada. Perwujudan golongan punya kaitan erat dengan perwujudan sifat tersebut. Misalnya, "kemampuan berpikir" pada golongan manusia. Kemampuan berpikir itu merupakan hakikat manusia. Oleh karena itulah, kemampuan berpikir itu dinyatakan sifat pembeda atau sifat pemisah.
Contoh
lain, sifat "panas" pada api, sifat "basah" pada air, sifat
"tumbuh" pada tumbuh-tumbuhan, sifat "bernyawa" pada hewan.
Satu per satu sifat itu menunjukkan hakikat masing-masing lingkungan.
Menemukan sifat pembeda yang menunjukkan hakikat lingkungan itu tidak mudah untuk diperoleh. Makin sederhana bentuk lingkungan yang diselidiki makin sukar untuk memperoleh sifat pembeda. Contoh lingkungan yang sederhana misal menyaksikan "kursi", menyaksikan "bangku", menyaksikan
"balai-balai", semuanya itu tempat duduk, dan punya lingkungan sendiri-sendiri. Silakan temukan hakikat yang membedakan satu per satu lingkungan itu, yakni menemukan sifat pembeda atau sifat pemisah.
Oleh karena menemukan sifat pembeda atau sifat pemisah itu tidak mudah maka sering kali golongan-golongan itu cuma dibedakan dengan sifat khusus atau proprium.
Diferensi disebut juga sebagai sifat pembeda atau sifat pemisah, dibedakan antara berikut ini.
a. Diferensi generik, yaitu sifat pembeda yang membuat genus lebih tinggi menjadi lebih rendah, misalnya substansi "material", badan "berjiwa", organisme "berperasa"
b. Diferensi spesifik, yaitu sifat pembeda yang membuat genus terdekat menjadi spesies, misalnya hewan "berakal budi", hewan "menyalak".
Proprium atau sifat khusus (penjelasan yang lain) ialah "suatu tanda pengenal yang dipunyai setiap diri dalam golongan tertentu tetapi secara perlahan dapat lenyap". Sifat ini tidak menunjukkan hakikat golongan, akan tetapi hanya menunjukkan kekhususan-kekhususan pada suatu golongan Contohnya, "kemampuan berpolitik" pada manusia, kemampuan berbudaya, berekonomi, bertani, berilmu. Contoh lain, bau "harum" pada kasturi, rasa "manis" pada gula, warna "putih" pada salju, Sekalipun sifat khusus itu bukan menunjukkan hakikat golongan, akan tetapi kekhususan pada golongan-golongan tertentu.
Proprium atau sifat khusus tidak bertalian dengan hakikat sesuatu diri, walaupun demikian dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari sifat pemisah Proprium dibedakan atas dua macam, yaitu sebagai berikut.
a. Proprium generik: sifat khusus yang berpangkal pada jenis sesuata, misalnya sifat "dapat mati" yang dihubungkan dengan manusia maka disebut sifat khusus jenis karena secara langsung timbul dari suatu genus atau jenis dari pengertian manusia, yakni "benda hidup" atau "organisme". Dengan demikian, seorang dapat mati, bukan karena dia berakal budi, bukan karena berindra, melainkan karena dia merupakan sesuatu "organisme yang hidup".
b. Proprium spesifik; sifat khusus yang berpangkal pada hakikat yang utuh dari sesuatu, misalnya sifat "berpolitik" yang dihubungkan dengan manusia maka disebut sifat khusus spesies karena secara langsung timbul dari spesies manusia, yakni "manusia" itu sendiri sebagai spesies Dengan demikian, seseorang berpolitik karena dia berakal budi, sesuatu tidak dapat berpolitik jika tidak berakal budi, dan yang adalah manusia. berakal budi adalah manusia.
5. Aksiden
Aksiden (accidens) atau sifat kebetulan atau juga sifat sampiran (penjelasan yang lain) ialah "tanda-tanda yang mendadak muncul dan mendadak lenyap pada sesuatu diri". Sifat kebetulan itu bukan milik khusus sesuatu golongan, akan tetapi bisa dijumpai pada berbagai golongan. Oleh karena itulah, sifat kebetulan tidak mampu membedakan golongan-golongan dalam satu lingkungan genus.
Contoh sifat kebetulan, misalnya kemampuan berlari, melompat, menerjang pada manusia. Contoh lain, kemampuan berayun dan bersiul pada pohon bambu, kemampuan menggelinding pada sesuatu benda.
Aksiden atau sifat kebetulan atau sifat sampiran atau juga sifat umum, Aksiden dibedakan atas dua macam, yaitu sebagai berikut.
a. Aksidenpredikamental: sifat kebetulan yang menyertai cara beradanya sesuatu dan yang melekat pada subjek. Sifat-sifat seperti ini ada sembilan macam, sebagaimana telah dibicarakan dalam predikamenaksidensia yang merupakan pasangan predikamen substansi, misal: sifat "terpelajar", "pendidik", "tinggi-besar" untuk manusia; "panas, "dingin" untuk udara. Sifat-sifat seperti ini adalah ada dengan yang lain.
b. Aksidenpredikabel: sifat kebetulan yang menyertai cara menyatakan sesuatu yang tidak mutlak. Sifat-sifat ini berlawanan dengan sifat khusus, misalnya "berambut pirang" untuk manusia, yakni manusia berambut pirang; "persegi" untuk badan benda, yakni badan benda yang persegi. Sifat-sifat seperti ini adalah tidak mutlak.
6. Ikhtisar Klasifikasi
Klasifikasi
di atas ditinjau dari segi lingkungan zat dan lingkungan sifat maka yang masuk
lingkungan zat adalah genus dan spesies, sedang yang masuk lingkungan sifat
adalah diferensia, proprium, dan aksiden. Berdasarkan uraian tiap-tiap
pengertian di atas dapat ditinjau dari segi substansi dan aksidensia atau
sering juga disebut esensia dan aksidensia maka yang masuk dalam esensia adalah
genus, spesies, dan difenrensia karena ketiga hal itu menyatakan tentang
hakikat sesuatu, sedang yang masuk dalam aksidensia adalah proprium dan aksiden
jika menjadi satu kesatuan cukup dinyatakan "aksiden" saja karena
mengikuti penyebutan yang terlemah. Hubungan antara zat dan sifat, beserta
esensia dan aksidensia dapat dijelaskan dengan diagram tentang klasifikasi
(lihat diagram).

Dalam diagram dapat dilihat bahwa diferensia yang masuk dalam lingkungan esensi atau hakikat, masuk juga dalam lingkungan sifat maka dapat dinyatakan diferensia adalah sebagai sifat hakikat atau hakikat sifat dari sesuatu. Diferensia bukan suatu zat dan bukan aksidensi. Oleh karena itu diferensia adalah suatu sifat pembeda atau sifat pemisah.
KEGIATAN
BELAJAR 3
Definisi
atau Penjelasan
Setelah
mempelajari cara mengadakan analisis beserta klasifikasi maka perlu dipelajari
juga tentang definisi yang merupakan satu rangkaian pembahasan untuk menentukan
batas-batas pengertian atau konsep yang dimaksudkan.
Dalam
analisis dijelaskan tentang proses memerinci sebuah genus, pengertian
umum atau golongan menjadi bagian-bagian yang secara logika menyusunnya
sampai mencapai spesies yang terendah. Proses ini berjalan lebih
lanjut ketika bagiannya itu sebagai spesies yang diketahui perbedaannya
sebagai bawahan sebuah genus dan diketahui memiliki diferensia
yang khusus dipunyai oleh spesies-spesies tersebut. Hal ini pada hakikatnya
adalah sama dengan definisi karena untuk mengetahui apakah sesuatu
golongan objek itu termasuk atau tidak termasuk dalam suatu subbagian
tertentu maka hakikatnya harus diketahui, maksudnya harus didefinisikan
atau dirumuskan batas-batasnya.
Definisi juga merupakan unsur atau bagian dari
ilmu pengetahuan yang merumuskan dengan singkat dan tepat mengenai objek atau
masalah. Definisi sangat penting bagi seseorang yang menginginkan sanggup berpikir
dengan baik, membuat definisi terlebih dahulu bukanlah hal memperpanjang
persoalan tetapi justru membuktikan pendidikan seseorang bahwa dia tahu
kerangka masalahnya.
Definisi
adalah sangat penting dalam bidang ilmiah, sesuai dengan hakikat ilmu itu sendiri
adalah merupakan bentuk pengetahuan yang telah ditentukan batas-batasnya
sehingga jelas batas antara ilmu satu dengan ilmu yang lain. Demikian dalam
suatu perbincangan supaya ada kesepakatan perlu di beri penjelasan atau
definisi terlebih dahulu sehingga masing-masing mempunyai pengertian atau
konsep yang sama. Perlu juga diketahui tidak semua hal dapat didefinisikan,
sejauh akal manusia dapat memikirkan hal itu dapat didefinisikan, tetapi jika
akal manusia tidak mampu memikirkan maka tidak mampu pula memberi definisinya,
memang hanya itulah kemampuan manusia.
Definisi berasal dari kata Latin "definire" yang berarti menandai batas-batas
pada sesuatu, menentukan batas, memberi ketentuan atau batasan arti, Definisi
berasal dari kata Latin "definire" yang berarti menandai batas- jadi
definisi dapat diartikan sebagai penjelasan apa yang dimaksudkan oleh sesuatu term atau dengan kata lain definisi ialah sebuah pernyataan yang memuat penjelasan tentang arti suatu term
Pernyataan yang memuat penjelasan arti atau definisi harus terdiri atas dua bagian. Dua bagian ini harus ada jika tidak bukanlah suatu definisi, yaitu :
Bagian pangkal disebut dengan "definiendum" yang berisi istilah yang harus diberi penjelasan atau hal yang didefinisikan, dan bagian pembatas disebut dengan "definiens" yang berisi uratan mengenal arti dari bagian pangkal atau hal yang untuk mendefinisikan.
Misalnya, definisi tentang manusia: "manusia" adalah "makhluk yang berakal budi". Istilah atau kata "manusia" disebut definiendum, sedang keterangan "makhluk yang berakal budi" disebut definiens.
Definisi atau batasan arti banyak macam-macamnya, yang disesuaikan dengan berbagai langkah, lingkungan, sifat, dan tujuannya. Dalam modul ini, tidak diuraikan secara terperinci, hanya ditinjau garis besar saja sebagai kerangka dasar macam-macam definisi pada umumnya. Secara garis besar definisi dibedakan atas tiga macam, yakni definisi nominalis, definisi realis, dan definisi praktis.
Definisi nominalis ialah penjelasan sebuah istilah dengan kata lain yang lebih umum dimengerti. Jadi, sekadar menjelaskan istilah sebagai tanda bukan menjelaskan hal yang ditandai, misalnya nirwana adalah surga Definisi nominalis terutama dipakai pada permulaan sesuatu pembicaraan diskusi, perdebatan, dengan maksud menunjukkan apa yang menjadi pokok pembicaraan, diskusi, perdebatan. Definisi nominalis ada enam macam :
1. Definisi sinonim, yakni penjelasan dengan memberikan persamaan kata atau memberikan penjelasan dengan kata yang lebih dimengerti misalnya dampak adalah pengaruh yang membawa akibat, arca adala patung, kendala adalah halangan, nirwana adalah surga, lahan adalah tanah terbuka. Definisi ini paling singkat dan yang digunakan di dalam kamus.
2. Definisi simbolik, yakni penjelasan dengan cara memberikan persan pernyataan berbentuk simbol-simbol. Definisi ini banyak digunakan dalam bidang matematika termasuk juga logika untuk member penjelasan secara simbolik, misalnya:
(p => q) <=> ~ (p ^ ~ q):
Dibaca:
Jika p maka q, didefinisikan non (p dan nonq).
(A⊂ B) <=> ∀ x (x ∈ A => x ∈ B):
Dibaca: A
bagian dari B, didefinisikan untuk semua x jika x anggota A maka
x anggota B.
3. Definisi etimologik, yakni penjelasan dengan cara memberikan asal mula istilahnya, misalnya demokrasi dari asal kata "demos" berarti rakyat, "kratoskratein" berarti kekuasaan/berkuasa, jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau rakyat yang berkuasa. Contoh lain, filsafat berasal dari kata Yunani "Philosophia", yang berasal gabungan antara istilah "philia" berarti cinta, dan "sophia" berarti kebijaksanaan sehingga filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Contoh lain, definisi tentang metamorphose, yang didefinisikan metamorphose adalah perubahan bentuk.
4. Definisi semantik, yakni penjelasan suatu tanda dengan arti atau makna yang telah terkenal, misal:
tanda △ berarti: maka, atau jadi
tanda => berarti: jika....... maka.........
tanda <=> berarti: bila dan hanya bila / jika hanya.... maka ....
5. Definisi stipulatif, yakni penjelasan dengan cara pemberian nama atas dasar kesepakatan bersama, misalnya planet tertentu disebut "mars". Definisi seperti ini banyak digunakan dalam lapangan ilmu pengetahuan, terutama dalam penemuan hal-hal baru, misal pemberian nama lembah-lembah yang ada di bulan, pemberian nama tumbuh-tumbuhan baru hasil perkembangan, pemberian nama suatu komet yang baru diketahui oleh seorang ahli.
6. Definisi denotatif, yakni penjelasan istilah dengan cara menunjukkan atau memberi contoh suatu benda atau hal yang termasuk dalam cakupan stilah tersebut, misalnya tanaman adalah seperti jagung, padi, kedelai, kacang, dan sebangsanya. Definisi denotatif ini ada dua macam yakni sebagai berikut.
a. Definisi ostensif, yakni memberi batasan sesuatu istilah dengan memberikan contoh, misalnya mendefinisikan apakah itu batu kerikil, dengan mengambil batu kerikil dan kemudian berkata inilah batu kerikil".
b. Definisi emomeratif, yakni memberi batasan sesuatu istilah deng memberikan perincian satu demi satu secara lengkap menge hal-hal yang termasuk dalam cakupan istilah tersebut, misalny Propinsi di Indonesia adalah Jawa Tengah, Daerah Istimew Yogyakarta, Jawa Barat, dan seterusnya sampai terakhir Tim Timur.
Definisi denotatif ini lebih khusus serta lebih konkret berguna dalam corak pemberitaan elementer, namun dalam hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan serta uraian yang teknis definisi ini kurang berguna.
Syarat-syarat Definisi Nominalis. Dalam membuat definisi nominalis ada tiga syarat yang perlu diperhatikan ialah berikut ini.
1. Apabila sesuatu kata hanya mempunyai sesuatu arti tertentu, hal ini harus selalu dipegang. Demikian juga kata-kata yang sangat biasa diketahui umum, hendaknya dipakai juga menurut arti dan pengertiannya yang sangat biasa.
2. Jangan menggunakan kata untuk mendefinisikan jika tidak tahu, artinya secara tepat dan terrumus jelas. Bilamana muncul keragu-raguan mengenai sesuatu istilah, harus diberi terlebih dahulu definisinya dengan teliti dan hati-hati.
3. Apabila arti dan pengertian sesuatu istilah menjadi suatu objek pembicaraan, definisi nominalis atau definisi taraf pertamanya harus sedemikian rupa sehingga dapat secara tetap diakui oleh kedua pihak yang berdebat.
Definisi realis ialah penjelasan tentang hal yang ditandai oleh sesuatu istilah. Jadi, bukan sekadar menjelaskan istilah, tetapi menjelaskan isi yang dikandung oleh suatu istilah. Definisi realis banyak digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan serta hal-hal yang bersifat teknis. Definisi realis ada dua macam yaitu sebagai berikut.
1. Definisi Esensial, yakni penjelasan dengan cara menguraikan bagian bagian dasar yang menyusun sesuatu hal. Bagian-bagian ini antara sa dengan yang lain dapat dibedakan secara nyata atau hanya beda dalam akal pikiran. Oleh karena itu, definisi esensial dapat dibedakan atas da macam, yaitu definisi analitik dan definisi konotatif.
a. Definisi analitik, yakni penjelasan dengan cara menunjukkan bagian-bagian sesuatu benda yang mewujudkan esensinya, Definisi ini disebut juga definisi esensial fisik karena dengan cara analisis fisik. Misalnya, "manusia" dapat didefinisikan: "suatu substansi yang terdiri atas badan dan jiwa atau "manusia" adalah jiwa dan raga. Air adalah H₂O."
b. Definisi konotatif, yakni penjelasan dengan cara menunjukkan isi dari suatu term yang terdiri atas genus dan diferensia. Definisi ini disebut juga definisi esensial metafisik, yakni memberikan jawaban yang terdasar dengan menunjukkan predikabel substansinya, misalnya manusia adalah hewan yang berakal, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa. Bentuk definisi semacam ini adalah sangat ideal, tetapi sayang tidak semua hal dapat didefinisikan semacam ini. Definisi konotatif dicapai dengan melalui tiga langkah berikut ini.
1) Memperbandingkan hal yang hendak didefinisikan dengan semua hal-hal lain.
2) Menunjukkan jenis atau golongan yang memuat hal tersebut.
3) Menunjukkan ciri-ciri yang memperbedakan hal tersebut dari
semua hal-hal lain yang termasuk golongan yang sama.
2. Definisi Deskriptif, yakni penjelasan dengan cara menunjukkan sifat-sifat yang dimiliki oleh hal yang didefinisikan. Sifat-sifat ini khusus pada halnya yang dapat membedakan hal-hal lain yang terdapat dalam golongan yang sama. Definisi ini dibedakan atas dua macam, yaitu definisi aksidental dan definisi kausal.
a. Definisi aksidental, yakni penjelasan dengan cara menunjukkan jenis dari halnya dengan sifat-sifat khusus yang menyertai hal tersebut, atau dengan rumusan lain, yakni penjelasan dengan cara menunjukkan genus dan propriumnya, misalnya manusia adalah hewan yang berpolitik, manusia adalah hewan yang menggunakan simbol-simbol, manusia adalah makhluk sosial, bangsa adalah sekelompok manusia yang pada umumnya memiliki watak-watak sosial tertentu.
b. Definisi kausal, yakni penjelasan dengan cara menyatakan bagaimana sesuatu hal terjadi atau terwujud. Hal ini berarti juga memaparkan asal mula atau perkembangan dari hal-hal yang ditunjuk oleh suatu term. Definisi ini disebut juga definisi genetik,
misalnya awan adalah uap air yang terkumpul di udara karena penyinaran laut oleh matahari, murtad adalah orang yang berpinda dari suatu agama ke agama lain, jam adalah suatu benda denga daya upaya untuk menunjukkan waktu.
C. DEFINISI PRAKTIS
Definisi praktis ialah penjelasan tentang sesuatu hal ditinjau dari kegunaan atau tujuan. Definisi praktis dapat juga dinyatakan gabungan antara definisi nominalis dan definisi realis, namun tidak dapat dimasukkan dalam salah satu di antara keduanya, misalnya filsafat adalah berpikir ilmiah mencari kebenaran hakiki atau filsafat adalah pemikiran secara kritik dan sistematik untuk mencari hakikat atau kebenaran sesuatu. Definisi praktis in ada tiga macam, definisi operasional, definisi fungsional, dan definis persuasif. Persuasif sebenarnya bukan suatu definisi, hanya dinyatakan seperti definisi. Ketiga definisi tersebut diuraikan sebagai berikut :
1. Definisi operasional, yakni penjelasan suatu term dengan can menegaskan langkah-langkah pengujian khusus yang harus dilaksanakan atau dengan metode pengukuran serta menunjukkan bagaimana hasil yang dapat diamati, sistem ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut.
a. Operasional kualitatif berdasarkan isi dan kekuatan hal yang diamati, misalnya magnet adalah logam yang dapat menarik gugusan besi, emas adalah logam jika diuji secara fisis dan kimiawi ternyata mengandung unsur yang bernilai.
b. Operasional kuantitatif berdasarkan banyak atau jumlah hal diamati, misalnya panjang adalah jumlah kali ukuran standar memenuhi jarak. yang
2. Definisi fungsional, yakni penjelasan sesuatu hal dengan cara menunjukkan kegunaan atau tujuannya, misalnya negara adalah suatu persekutuan besar yang bertujuan kesejahteraan bersama bersifa pragmatis, bahasa adalah pernyataan pikiran atau perasaan sebagai alat komunikasi manusia, filsafat adalah pemikiran secara kritik dan sistematik untuk mencari hakikat atau kebenaran sesuatu.
3. Definisi persuasif, yakni penjelasan dengan cara merumuskan suatu pernyataan yang dapat memengaruhi orang lain, misalnya lux adalah sabun bintang-bintang film, tepat waktu adalah keutamaan dan orang-orang modern, sosialisme adalah demokrasi sosial ekonomi, kecermatan adalah kebajikan orang-orang terpelajar. Definisi in kelihatannya menjelaskan arti dari sesuatu kata atau istilah, tetapi sesungguhnya secara tidak langsung menyarankan kepada pihak lain supaya menyetujui atau menolak sesuatu hal. Dengan demikian, definisi persuasif pada hakikatnya merupakan alat untuk membujuk atau teknik untuk menganjurkan dilakukannya perbuatan tertentu atau dapat juga untuk membangkitkan emosi seseorang
D. SYARAT-SYARAT DEFINISI
Dalam merumuskan definisi ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan supaya definisi yang dirumuskan itu baik dan betul-betul mengungkapkan pengertian yang didefinisikan secara jelas dan mudah dimengerti. Syarat-syarat yang akan dikemukakan di sini merupakan syarat secara umum berlaku untuk semua definisi terutama sekali definisi realis, di samping juga ada syarat khusus untuk definisi nominalis.
Perlu diperhatikan di sini, tidak semua hal dapat didefinisikan karena akal manusia terbatas, sejauh akal manusia dapat memikirkan hal tersebut dapat didefinisikan, tetapi jika akal manusia tidak mampu memikirkannya maka hal tersebut tidak dapat didefinisikan. Di samping itu, dapat juga satu hal didefinisikan dengan cara yang bermacam-macam, namun definisi yang tepat dan jelas pada dasarnya hanya satu, hal ini juga tergantung masalahnya, mana bentuk definisi yang paling tepat untuk hal tersebut.
Syarat-syarat definisi secara umum dan sederhana ada lima syarat, namun ada juga yang merumuskan lebih dari lima, yang sebenarnya hanya merupakan penjelasan berikutnya. Syarat-syarat tersebut atau sering juga disebut dengan hukum-hukum definisi adalah merupakan persyaratan untuk menyusun definisi yang tepat dan baik jika dilanggar maka definisinya tidak dapat memberi penjelasan yang baik. Lima syarat yang dimaksudkan adalah bagai berikut.
1. Sebuah definisi harus menyatakan ciri-ciri hakiki dari apa yang didefinisikan, yakni menunjukkan pengertian umum yang meliputinya beserta ciri pembedanya yang pokok. Syarat ini penting dalam definisi ilmiah, sebagaimana untuk mendefinisikan tentang hewan, tumbuh- tumbuhan, organisme. Misal : Mendefinisikan kuda adalah equus caballus, equus adalah himpunan umum (genus) meliputi kuda, dan caballus adalah ciri pembeda (diferensia) yang membedakan kuda dari keledai, zebra anggota dari golongan yang sama. Contoh lain, hewan adalah organisme berindra, organisme merupakan hakikat zat dani hewan, sedangkan berindra merupakan hakikat sifat hewan
2 Sebuah definisi harus merupakan suatu kesetaraan arti hal yang didefinisikan dengan yang untuk mendefinisikan, maksudnya tidak terlampau luas dan tidak terlampau sempit. Syarat ini melahirkan 2 anak syarat sebagai berikut.
a. Definiens tidak lebih luas dari yang didefinisikan. Oleh karena itu, harus mengeluarkan setiap yang tidak termasuk ke dalam lingkungan yang didefinisikan, atau eksklusif. Mendefinisikan sebuah meja sebagai "perabot rumah tangga" adalah terlampau luas. Manusia adalah "organisme yang berindra" juga terlalu luas.
b. Definiens tidak lebih sempit dari yang didefinisikan. Oleh karena itu, harus menarik ke dalam lingkungan pengertian setiap diri yang termasuk didefinisikan atau inklusif. Mendefinisikan kursi sebagai "barang yang sekarang diduduki" adalah terlampau sempit.
3. Sebuah definisi harus menghindarkan pernyataan yang memuat istilah yang didefinisikan, artinya definisi tidak boleh berputar-putar memuat secara langsung atau tidak langsung subjek yang didefinisikan atau tidak mengulang istilah yang didefinisikan. Syarat ini sering kali dilanggar dan dengan tidak diketahui karena definisi tersebut dinyatakan dalam kata-kata yang ditinjau secara etimologi seasal dengan istilah-istilah yang didefinisikan.
Misal: Keracunan adalah hasil akibat minum racun, obat tidur adalah bahan yang mengandung sifat-sifat yang dapat menidurkan, pengetahuan adalah hal-hal yang diketahui dalam ingatan, hukum waris adalah hukum yang mengatur harta warisan, filsafat Pancasila adalah filsafat yang mempelajari Pancasila.
4. Sebuah definisi sedapat mungkin harus dinyatakan dalam bentuk rumusan yang positif, yakni tidak boleh dinyatakan secara negatif jika dapat dinyatakan dengan kalimat positif karena membuat definisi ialah untuk mengatakan apakah barang sesuatu itu dan bukannya untuk mengatakan bukan apakah barang sesuatu itu. Akan tetapi, memang benar bahwa dalam banyak hal jika mempunyai pengertian yang jelas tentang bukan apakah barang sesuatu itu maka dapat dengan lebih mudah menangkap ciri-cirinya yang positif.
Misal: Pelanggaran terhadap syarat ini ialah kebebasan akademik ialah tidak dipengaruhi pembatasan-pembatasan dalam berbicara dan menulis, dinyatakan kaya apabila orang itu tidak miskin. Syarat ini perlu mendapatkan perhatian yang istimewa karena banyak hal yang hanya dapat didefinisikan dengan mengandung pengertian negatif, misalnya bujangan adalah lelaki dewasa yang belum kawin, perawan adalah wanita dewasa yang belum kawin, roh adalah bukan badan.
5. Sebuah definisi harus dinyatakan secara singkat dan jelas terlepas dari rumusan yang kabur atau bahasa kiasan karena maksud membuat definisi ialah memberi penjelasan serta menghilangkan perwayuhan-arti (makna ganda) maka dengan dipakainya istilah-istilah yang kabur dapat meng- halangi maksud tersebut.
Misal: Mendefinisikan aluminium adalah suatu jenis logam tertentu yang bercahaya. Contoh ini pernyataannya tidak terlalu luas, namun dengan mengatakan suatu jenis tertentu, masih mengandung kelemahan karena masih kabur tidak memberikan keterangan yang jelas. Contoh lain, definisi yang dibuat oleh Herbert Spencer tentang "evolusi" meskipun tidak niscaya kurang tepat, namun karena dalam membicarakan bahannya secara abstrak maka akibatnya definisi yang diajukan juga agak kabur, yakni "evolusi" adalah integrasi antara materi dengan lenyapnya gerakan yang bertepatan waktunya, pada waktu mana materi beralih dari homogenitas yang tidak tertentu serta tidak berhubungan menjadi heterogenitas yang tertentu serta berhubungan, dan pada waktu mana gerakan yang tersisa mengalami transformasi yang paralel.
MODUL 4
Proposisi Kategorik
PENDAHULUAN
Dalam Modul 2 telah dibicarakan tentang konsep dan tem, konsep bersifat kerohanian,dan ungkapan konsep dalam bentuk bala do term. Konsep maupun term merupakan unsur dasar penalaran, dari konsep inilah dapat disusun dalam bentuk pendapat atau dari term dapat di dalam bentuk proposisi. Oleh karena term merupakan ungkapan dan konse dalam bentuk bahasa maka proposisi dapat juga dinyatakan sebagai ungkap pendapat dalam bentuk bahasa.
Proposisi
berdasarkan bentuk hubungannya atau berdasarkan bentuk logiknya sebagaimana
dibicarakan dalam Modul 1 ada 3 macam, yakn proposisi tunggal, proposisi
kategorik, dan proposisi majemuk. Di antara tiga macam proposisi yang akan
diuraikan dalam modul keempat ini adalah khusus proposisi kategorik. Proposisi
kategorik adalah merupakan pangkal pikir penalaran kategorik yang merupakan
hubungan dua term yang dapat diungkapkan dalam bentuk diagram himpunan. Diagram
himpunan merupakan bentuk formal yang dapat menentukan bagaimana hubungan
antara kedua term dalam suatu proposisi sehingga diagram himpunan dapat juga
digunakan sebagai alat formal pembuktian sah tidaknya suatu penalaran
Proposisi
kategorik secara sederhana dibedakan antara 4 macam sebagaimana yang diuraikan
dalam logika pada umumnya, yaitu proposi universal afirmatif, proposisi
universal negatif, proposisi partikular afirmatif dan proposisi partikular
negatif. Dalam Modul 4 ini, proposisi yang akan diuraikan di samping 4 macam
proposisi tersebut diuraikan juga yang lebih terperinci karena berdasarkan
bentuk hubungan yang diungkapkan atas dasar kenyataan yang ada atau atas dasar
bentuk hubungan antara kedua term sehingga menjadi 7 macam proposisi kategorik.
Hubungan
2 term dalam proposisi inilah yang menentukan bentuk- bentuk proposisi
kategorik yang merupakan ungkapan dari kenyataan yang ada sehingga kebenaran bentuk pasti sesuai dengan kebenaran isi - terkandung dalam proposisi. Tidak seperti logika silogistik pada umumnya yang menyatakan kebenaran bentuk belum tentu sesuai dengan isi. Hal ini tidak berlaku untuk logika modern yang akan diuraikan dalam modul-mod berikutnya karena jika hanya benar bentuk tidak sesuai dengan isi, untuk ap belajar logika jika tidak dapat menentukan kepastian isinya. yang
Dengan dasar uraian di atas, baik 4 macam proposisi kategorik maupun 7 macam yang terurai, masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri dalam pangkal pikir penalaran sehingga kedua macam bentuk akan diuraik secara rinci dalam modul ini.
KEGIATAN BELAJAR 1
Unsur Dasar Proposisi
Dasar proposisi adalah term, term merupakan istilah untuk mengungkapkan suatu konsep sehingga keduanya merupakan satu kesatuan. Proposisi yang akan dibahas adalah proposisi kategorik, yaitu pernyataan yang terdiri atas hubungan 2 term sebagai subjek dan predikat serta dapat dinilai benar atau salah. Hubungan ini berbentuk pengiyaan atau pengingkaran, misalnya "Semua organisme berkembang biak, Rakyat Indonesia tidak boleh mengikuti ajaran komunis. Sebagian rakyat Indonesia adalah keturunan asing. Ada rakyat Indonesia yang tidak berketuhanan Yang Maha Esa."
Contoh "semua organisme berkembang biak", yang sebagai subjek adalah term "organisme", sebagai predikat adalah term "berkembang biak". Pemyataan demikian disebut dengan proposisi kategorik. Contoh lain, "Indonesia adalah negara berdasar atas hukum", subjek adalah term "Indonesia" dan predikat adalah term "negara berdasar atas hukum".
A. EMPAT UNSUR PROPOSISI
Proposisi kategorik ini terdiri atas 4 unsur, dua di antaranya merupakan materi dari proposisi yang merupakan hal pokok, sedangkan dua yang lain sebagai hal yang menyertainya. Empat unsur yang dimaksudkan adalah sebagai berikut.
1. Term sebagai subjek, yaitu hal yang diterangkan dalam pernyataan sering disimbolkan dengan "S".
2. Term sebagai predikat, yaitu hal yang menerangkan dalam pernyataan. yang sering disimbolkan dengan "p".
Kedua unsur sebagai subjek dan predikat inilah yang merupakan materi pokok proposisi kategorik.
3. Kopula, yaitu hal yang mengungkapkan adanya hubungan antara subjek dan predikat, dapat mengiyakan atau mengingkari, afirmatif atau negatif yang menunjukkan kualitas pernyataan. Hal ketiga ini sebagai pemberi bentuk dan sering juga kopula tidak diperlihatkan khusus yang afirmatif atau positif, serta tidak mengubah makna, hanya diperkirakan saja, misalnya "Semua rakyat Indonesia adalah berketuhanan Yang Maha Esa, sama saja bila dinyatakan: Semua rakyat Indonesia berketuhanan Yang Maha Esa." 4. Kantor, yaitu pembilang yang menunjukkan lingkungan yay! dimaksudkan oleh subjek, dapat berbentuk universal atau partikular yang sekaligus juga menunjukkan kuantitas pernyataan.
Hal keempat ini juga sering tidak diperlihatkan, yaitu dalam p universal atau menunjukkan pengertian kesemuanya yang dimaksudka subjek, misal Semua bangsa Indonesia ber-Pancasila. Kata "semua adalah kuantor universal, dan kata "semua" dapat dihilangkan tanpa mengubah makna yang dimaksudkan, yakni dinyatakan: "Bangsa Indonesia ber Pancasila."
Proposisi dalam logika dapat benar dapat juga salah, tidak dapat dinila kedua-duanya. Contoh-contoh di atas kebetulan mempunyai nilai betar semua karena sesuai dengan kenyataan. Contoh lain, "Manusia adalah keturunan kera." Pernyataan ini mungkin benar mungkin juga salah, menuru penelitian sampai sekarang ini pernyataan tersebut dianggap salah, tidak dapat setengah benar atau setengah salah. Jika benar ya benar jika salah ya salah sehingga tegas perbedaan antara keduanya.
Proposisi disebut juga sebagai bentuk lahir dari pendapat, sedangkan term yang merupakan unsur proposisi adalah bentuk lahir dari konsep ata pengertian sehingga sering juga dalam logika dinyatakan, pendapat sebagi unsur dari penalaran. Proposisi dan pendapat merupakan satu kesatuan sebagai bentuk dan isi. Pendapat dapat dinyatakan sebagai berikut.
Pendapat adalah hubungan dua konsep yang mempunyai nilai benar atau salah.
Jadi, suatu pendapat mempunyai dua kemungkinan, mungkin be mungkin salah. Benar salahnya suatu pendapat atau benar salahnya su proposisi dihubungkan dengan hal yang dibicarakannya. Jika ya dibicarakan tentang benda-benda alamiah maka kebenarannya adalah ha sesuai dengan kenyataannya (mengikuti teori korespondensi) dan jika yan dibicarakan hal atas dasar persetujuan bersama maka kebenarannya harus sesuai dengan hasil persetujuan tersebut (mengikuti teori koherensi). Jad benar salahnya suatu proposisi itu dihubungkan dengan isinya.
Unsur yang merupakan materi pokok proposisi kategorik adalah term sebagai subjek dan term sebagai predikat, yang keduanya merupakan hal Yang harus ada. Jika salah satu tidak ada maka pernyataan tersebut tidak dapat disebut sebagai proposisi kategorik, hanya sebagai proposisi tunggal yang Akan tetapi, apabila proposisi kategorik dianggap sebagai satu kesatuan term, dapat juga disebut dengan istilah proposisi tunggal. Proposisi kategorik dapat juga sebagai bagian dari proposisi majemuk sehingga proposisi majemuk adalah pernyataan yang terdiri atas hubungan 2 bagian yang dapat dinilai benar atau salah (lihat Modul 1, Kegiatan Belajar 2). Demikian juga istilah bagian dalam proposisi majemuk dapat juga berupa pernyataan majemuk.
1. Term sebagai Subjek
Term sebagai subjek selalu berhubungan dengan sejauh mana term itu dapat dikenakan dan merupakan kuantitas proposisi. Term sebagai subjek biasa disingkat dengan S, yaitu diambilkan dari huruf pertama kata "Subjek". Subjek secara sederhana dibedakan antara subjek universal dan subjek partikular. Adapun subjek yang kolektif ditinjau dari segi kuantitasnya dapat dinyatakan sebagai subjek universal. Untuk subjek yang singular jika ditinjau dari segi kuantitasnya dapat dinyatakan partikular, tetapi jika ditinjau dari segi kualitasnya subjek singular ini dapat dinyatakan sebagai subjek universal dalam arti untuk keseluruhan diri.
a Subjek universal
Subjek universal, mencakup semua yang dimaksud oleh subjek, misalnya "semua mahasiswa Indonesia", "peserta kuliah logika", "setiap rakyat Indonesia". Subjek universal berdasarkan bentuk logikanya cukup diabstraksikan dengan rumusan "semua S", dan dinyatakan dalam bentuk simbol-simbol:
vx.Sx atau (x)Sx, dibaca: "untuk semua x di mana S berlaku untuk x", atau "semua x, x bersifat S" atau secara singkat cukup dibaca "semua S", "setiap S".
Simbol V yang selalu disertai dengan x menunjukkan sifat universal dan bentuk x disebut "kuantor universal" atau "pembilang universal", dibaca: "untuk semua x" atau "untuk semua x berlakulah" (lihat term berdasarkan denotasi). Adapun huruf S adalah menunjukkan x itu disebut apa yang menjadi subjek dalam proposisi. Kuantor universal ini apabila diterapkan term "semua manusia" maka proses perubahannya dalam pengabstraksiannya adalah sebagai berikut.
Semua sesuatu di mana sesuatu itu adalah manusia:
"untuk semua x, di mana x itu adalah manusia".
"untuk semua x, di mana x adalah S".
Kata "semua" dalam subjek universal dapat dihilangkan tanpa mengubah makna. Dengan demikian, kuantor universal Vx dapat juga hanya dinyatakan atau disimbolkan dengan (x) saja, misalnya Vx.Sx dapat ditulis (x)Sx. Pernyataan: "semua rakyat Indonesia", sama maknanya dengan pernyataan
"rakyat Indonesia", sama dalam arti luasnya atau denotasinya.
Subjek partikular, yaitu hanya mencakup sebagian dari keseluruhan yang disebutkan oleh subjek, misalnya "ada mahasiswa Indonesia", "sebagian peserta kuliah logika", "beberapa rakyat Indonesia". Subjek partikular ini sering dirumuskan secara abstrak dengan "sebagian S" atau "ada S", dan dinyatakan dalam bentuk simbol-simbol:
3x.Sx, dibaca: "ada x di mana 5 berlaku untuk x" atau "sebagian x, x bersifat S" atau secara singkat cukup dibaca "sebagian S" atau juga "ada S".
Simbol 3 yang selalu disertai dengan x menunjukkan sifat partikular dan bentuk 3x disebut "kuantor eksistensial" atau "pembilang partikular", dibaca: "ada suatu x" atau "terdapatlah suatu x sedemikian" (lihat term berdasarkan denotasi). Kuantor eksistensial apabila diterapkan term "sebagian manusia" maka proses perubahan dalam pengabstraksiannya adalah sebagai berikut:
Ada sesuatu di mana sesuatu itu adalah manusia:
"ada x, di mana x adalah manusia.
"ada x, di mana x adalah S.
Dalam subjek partikular, kata "sebagian" dapat dinyatakan juga "" tanpa mengubah makna, dalam arti maknanya sama, misalnya "sebagian makhluk" sama bila dinyatakan "ada makhluk", "ada" berarti "sebagian" sebagian yang tidak tertentu jumlahnya.
2. Term sebagai Predikat
Term sebagai predikat selalu berhubungan dengan isinya dan merupakan balitas proposisi, hal ini biasa disingkat dengan P, yaitu diambilkan dari huruf pertama kata "Predikat". Term sebagai predikat dibedakan antara predikat afirmatif dan predikat negatif.
a. Predikat afirmatif
Predikat afirmatif, yaitu sifat mengiyakan adanya hubungan predikat dengan subjek, atau sifat mengakui hubungan subjek dengan predikat, dirumuskan dengan "adalah P", misal: semua peserta kuliah logika "rajin belajar", rakyat Indonesia "adalah berketuhanan Yang Maha Esa". Predikat afirmatif disimbolkan dengan:
Px, dibaca: "sifat P berlaku untuk x" atau "x bersifat p" atau secara singkat cukup dibaca "adalah p". Simbol tersebut apabila diterapkan dalam term predikat "adalah P”.
Simbol tersebut apabila diterapkan dalam term predikat “adalah organisme" maka proses perubahan dalam membacanya adalah sebagai berikut.
Sesuatu yang disebut organisme, menjadi:
"x yang disebut organisme".
"x bersifat P".
"adalah P".
b. Predikat negarif
Predikat negatif, yaitu sifat mengingkari adanya hubungan predikat dengan subjek atau sifat meniadakan hubungan subjek dengan predikat, drumuskan dengan "bukan P", misalnya sebagian peserta kuliah logika idak rajin belajar", ada rakyat Indonesia "yang tidak beragama Islam" Predikat negatif disimbolkan dengan
-Px, dibaca: "sifat non P berlaku untuk x" atau "x bersifat non p", atau secara singkat cukup dibaca "bukan P".
Simbol tersebut apabila diterapkan dalam term predikat “bukan organisme" maka proses perubahan dalam membacanya adalah sebagai berikut
Sesuatu yang bukan organisme, menjadi:
Unsur dasar proposisi kategorik adalah term sebagai subjek dan term sebagai predikat dan masing-masing tidak dapat dihilangkan, keduanya harus ada jika tidak ada salah satu maka akan menjadi proposisi tunggal bukan proposisi kategorik yang termnya hanya sebagai predikat sehingga proposta kategorik didefinisikan sebagai "pernyataan yang terdiri atas hubungan dua term sebagai subjek dan predikat serta dapat dinilai benar atau salah". Oleh karena dapat dinilai benar atau salah maka proposisi kategorik ditinjau dari segi bahasa adalah merupakan kalimat deklaratif atau kalimat berita, sebagaimana diuraikan dalam Modul 1 Kegiatan Belajar 2.
Subjek dan predikat yang masing-masing ada dua macam, subjek universal dan subjek partikular serta predikat afirmatif dan predikat negatif jika keduanya dihubungkan terwujud empat macam proposisi kategorik, yaitu proposisi universal afirmatif, proposisi universal negatif, proposisi partikular afirmatif, dan proposisi partikular negatif.
1. Subjek Universal dan Predikat Afirmatif disebut dengan Nama Proposisi Universal Afirmatif
Semua rakyat Indonesia berketuhanan Yang Maha Esa
Indonesia adalah negara berdasar atas hukum.
Semua peserta ujian logika dapat nilai baik.
Pancasila menyeimbangkan dua sifat kodrat manusia.
Dirumuskan: Vx(Sx⇒ Px) atau (x)(Sx => Px).
Dibaca: Untuk semua x jika S berlaku untuk x maka P berlaku untuk X.
atau dibaca secara singkat:
Atau: Untuk x, jika x adalah S maka x mempunyai sifat P, secara singkat dibaca:
"S adalah P".
2. Subjek Universal dan Predikat Negatif, disebut dengan Nama Proposisi Universal Negatif
Misal :
Semua rakyat Indonesia tidak berpaham komunis.
Manusia bukanlah keturunan kera.
Peserta kursus logika bukan seorang guru.
Ajaran Pancasila bukan berpaham liberalis.
Dirumuskan: Vx(SxPx) atau (x)(Sx =>~Px).
Dibaca: Untuk semua x jika S berlaku untuk x maka non P berlaku untukx, atau cukup dibaca:
"semua S bukan P",
"setiap S tidak P".
Atau: Untuk x, jika x adalah S maka x mempunyai sifat non P, cukup dibaca:
"S bukan P",
3. Subjek Partikular dan Predikat Afirmatif disebut dengan Nama Proposisi Partikular Afirmatif
Misal :
Sebagian rakyat Indonesia adalah keturunan asing.
Ada mahasiswa Indonesia yang belajar di Amerika.
Beberapa peserta ujian logika dapat nilai baik.
Ada negara yang beraliran sosialis.
Dirumuskan: 3x(Sx ^ Px).
Dibaca: Ada x di mana S berlaku untuk x dan P berlaku untuk x, atau cukup dibaca:
"ada S yang P",
"sebagian S adalah P,
"beberapa S adalah p
4. Subjek Partikular dan Predikat Negatif, disebut dengan Nama Proposisi Partikular Negatif
Misal:
Sebagian rakyat Indonesia tidak beragama Islam.
Ada negara yang tidak berpaham liberalis.
Beberapa anggota legislatif tidak korupsi.
Ada gempa yang tidak menimbulkan kerusakan.
Dirumuskan: 3x(Sx ^ ~Px).
Dibaca: Ada x di mana S berlaku untuk x dan non P berlaku untuk x,atau cukup dibaca:
Empat macam proposisi kategorik inilah yang menjadi pangkal-pikir dalam penalaran kategorik Namun, untuk penalaran yang lebih mudah dipahami dan mudah dibuktikan dengan diagram himpunan, dari 4 macam proposisi tersebut diperinci lagi berdasarkan materi yang dikandung oleh proposisi tersebut sehingga penalarannya antara materi dan bentuk-logiknya sama. Perincian 4 macam proposisi kategorik berdasarkan diagram himpunannya menjadi 7 macam proposisi kategorik (akan diuraikan dalam Kegiatan Belajar 2 modul ini). Tujuh macam atau tujuh bentuk inilah yang akan menjadi pangkal-pikir baik dalam penyimpulan langsung maupun dalam penyimpulan tidak langsung.
KEGIATAN BELAJAR 2
Empat Macam Proposisi
Materi proposisi kategorik yang disebut dengan term sebagai subjek dan Belajar 1, apabila dikombinasikan, antara subjek universal dan subjek partikular dengan predikat afirmatif dan predikat negatif maka terwujud 4 macam proposisi kategorik, (lihat Kegiatan Belajar 1 modul ini), yaitu:
Proposisi universal afirmatif, yaitu pernyataan umum mengiyakan.
Proposisi universal negatif, yaitu pernyataan umum mengingkari.
Proposisi partikular afirmatif, yaitu pernyataan khusus mengiyakan.
Proposisi partikular negatif, yaitu pernyataan khusus mengingkari.
Dari 4 macam proposisi kategorik tersebut dapat diperinci lagi berdasarkan denotasi atau luas term yang dihubungkan, menjadi 7 macam proposisi kategorik. Empat macam proposisi kategorik beserta penjabarannya yang ada tujuh macam ini akan diuraikan satu persatu secara terperinci, yang merupakan dasar dari penalaran kategorik. Oleh karena itu, perlu diuraikan secara jelas dan rinci beserta diagramnya, serta memerlukan perhatian khusus.
Catatan: Tanda (x) dalam diagram himpunan merupakan yang dimaksudkan suatu pernyataan itu atau juga yang dimaksudkan kesimpulan dari penalaran.
A. PROPOSISI UNIVERSAL AFIRMATIF
Proposisi universal afirmatif ialah pernyataan bersifat umum yang mengiyakan adanya hubungan subjek dengan predikat, biasa disebut dengan proposisi A (dari huruf pertama kata Latin "Affirmo" mengiyakan), misalnya "Semua rakyat Indonesia berketuhanan Yang Maha Esa. Semua peserta bimbingan tes Perintis ingin masuk Perguruan Tinggi, yang Setiap warga negara mendapat kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan, Indonesia adalah negara berdasar atas hukum.”
Contoh di atas term yang pertama sebagai subjek disingkat S, dan term yang kedua sebagai predikat disingkat P, diabstraksikan menjadi: semua S adalah P. dan dirumuskan secara simbolik:
vx (Sx => Px) : Untuk semua x jika S berlaku untuk x maka P berlaku untuk x, atau dibaca secara singkat "semua S adalah P"
Simbol → dibaca: "jika maka ...". Rumusan simbolik ini apabila dikembalikan pada salah satu contoh di atas maka dapat dibaca: Untuk semua sesuatu jika sesuatu itu rakyat Indonesia maka sesuatu itu adalah berketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan simbolik di atas dapat juga dinyatakan:
(x) (Sx => Px): Untuk x, jika x adalah S maka x mempunyai sifat P, secara singkat dibaca "S adalah P".
Proposisi universal afirmatif jika dianalisis berdasarkan perbandingan atau hubungan luas term, dapat dibedakan 2 macam, yaitu universal afirmatif ekuivalen dan universal afirmatif implikasi.
1. Proposisi Universal Afirmatif Ekuivalen
Proposisi universal afirmatif ekuivalen ialah pernyataan umum mengiyakan yang antara subjek dan predikat merupakan suatu persamaan, yakni semua anggota subjek adalah anggota predikat dan semua anggota predikat adalah anggota subjek, misalnya "Semua warga negara Indonesia adalah rakyat Indonesia, Semua manusia adalah berakal budi, Semua rakyat Indonesia harus ber-Pancasila." Dalam pernyataan pertama antara term "rakyat Indonesia" dan term "warga negara Indonesia", apabila diper- bandingkan luasnya atau denotasinya adalah sama atau identik, yaitu "semua rakyat Indonesia adalah warga negara Indonesia dan semua warga negara Indonesia adalah rakyat Indonesia," jadi keanggotaannya adalah sama atau identik, dirumuskan semua S adalah P dan semua P adalah S, disimbolkan (S P), dibaca "S identik dengan P" (lihat diagram).

Dalam diagram itu, semua anggota himpunan S merupakan anggota himpunan P. dan tidak ada satu pun anggota himpunan P yang bukan anggota himpunan S, jadi sama luas antara S dan P, disebut juga himpunan persamaan.
2. Proposisi Universal Afirmatif Implikasi
Proposisi universal afirmatif implikasi ialah pernyataan umum mengiyakan yang semua subjek merupakan bagian dari predikat, yakni semua anggota subjek menjadi himpunan bagian dari predikat, misalnya "Setiap warga negara Indonesia berketuhanan Yang Maha Esa." Dalam pernyataan ini jika dianggap benar maka antara term "warga negara Indonesia" dan term "yang berketuhanan Yang Maha Esa" luas himpunannya tidak sama, yaitu "semua warga negara Indonesia adalah berketuhanan Yang Maha Esa, tetapi tidak semua yang berketuhanan Yang Maha Esa adalah warga negara Indonesia, yang berarti ada yang berketuhanan Yang Maha Esa yang bukan warga negara Indonesia," dirumuskan semua S adalah P dan sebagian P adalah S, disimbolkan (SP), dibaca "S bagian dari P", (lihat diagram).
Dalam diagram itu, semua anggota himpunan S termasuk dalam himpunan P, tetapi hanya sebagian anggota himpunan P yang menjadi anggota himpunan S, P lebih luas dari S, dan S bagian dari P. Diagram himpunan tersebut disebut juga himpunan bagian.
B. PROPOSISI UNIVERSAL NEGATIF
Proposisi universal negatif ialah pernyataan bersifat umum yang mengingkari adanya hubungan subjek dengan predikat, biasa disebut dengan proposisi E (dari huruf kedua kata Latin "nEgo" yang berarti: mengingkari). misalnya "Rakyat Indonesia tidak boleh mengikuti aliran komunis, Sema manusia bukan keturunan kera, Manusia bukanlah benda mati. Badan benda mati tidak ada yang dapat bergerak. Benda hidup bukanlah benda mati."
Dalam contoh di atas term yang sebagai subjek disingkat S dan term predikat disingkat P, diabstraksikan menjadi semua S bukan P. dan duskan secara simbolik:
Vx (Sx=>~Px) : Untuk semua x jika S berlaku untuk x maka non P berlaku utuk x, atau cukup dibaca "semua S bukan P".
Rumusan simbolik ini apabila dikembalikan pada salah satu contoh di atas maka dapat dibaca: Untuk semua sesuatu, jika sesuatu itu rakyat Indonesia maka sesuatu itu tidak boleh mengikuti aliran komunis. Rumusan bolik di atas dapat juga dinyatakan:
(x) (Sx=>~Px) : Untuk x, jika x adalah S maka x mempunyai sifat non P, cukup dibaca "S bukan P".
Proposisi universal negatif jika dianalisis berdasarkan perbandingan atau hubungan luas term maka hanya ada satu bentuk, yaitu berbentuk eksklusif, ngkapnya proposisi universal negatif eksklusif.
Proposisi Universal Negatif Eksklusif
Proposisi universal negatif eksklusif jika didefinisikan secara lengkap adalah pernyataan umum mengingkari yang berarti antara subjek dan predikat tidak ada hubungan. Dari definisi ini dapat dijelaskan bahwa semua ggota subjek tidak ada satu pun yang menjadi anggota predikat, demikian haliknya tidak ada anggota predikat yang menjadi anggota subjek. Contoh "rakyat Indonesia" dan term "yang mengikuti aliran komunis" jika perbandingkan luasnya maka antara keduanya itu tidak ada hubungan sama kali. Oleh karena itu, himpunan S berada di luar himpunan P. demikian Jaga himpunan P berada di luar himpunan S, tiada satu pun anggota S yang menjadi anggota P, semua S bukan P dan semua P bukan S, disimbolkan (S 8P), dibaca "S tidak ada hubungan dengan P atau hubungan S dan P adalah kosong" (lihat diagram), artinya kosong tidak ada hubungan
Dalam diagram itu, luas kedua himpunannya tidak dapat diketahui secara jelas mana yang lebih luas karena tidak ada hubungan, yaitu keduanya terlepas tidak ada hubungan sehingga disebut juga himpunan lepas.
C. PROPOSISI PARTIKULAR AFIRMATIF
Proposisi partikular afirmatif ialah pernyataan bersifat khusus yang mengiyakan adanya hubungan subjek dengan predikat, biasa disebut dengan proposisi 1 (dari huruf keempat kata Latin "affirmo" yang berarti: mengiyakan), misalnya "Sebagian rakyat Indonesia adalah keturunan asing. Sebagian Sarjana Hukum ahli politik, Ada peserta bimbingan tes Perintis Yogyakarta yang ingin masuk ke Institut Teknologi Bandung, Sebagian makhluk adalah manusia, Ada mahasiswa Indonesia yang belajar di Amerika."
Dalam contoh-contoh di atas term sebagai subjek disingkat S dan term sebagai predikat disingkat P, diabstraksikan menjadi: "sebagian S adalah P" atau "ada S yang P" atau sering juga dinyatakan "beberapa S adalah P" dan dirumuskan secara simbolik:
3x (Sx Ʌ Px): Ada x di mana S berlaku untuk x dan P berlaku untuk x, atau cukup dibaca "ada S yang p" atau "sebagian S adalah P".
Simbol ^ dibaca: "dan". Rumusan simbolik ini jika diterapkan pada salah satu contoh di atas maka dapat dibaca: Ada sesuatu, sesuatu itu rakyat Indonesia dan sesuatu itu adalah keturunan asing.
Proposisi partikular afirmatif ini jika dianalisis berdasarkan perbandingan luas term, dapat dibedakan antara dua macam, yaitu: partikular afirmatif inklusif dan partikular afirmatif implikasi.
1. Proposisi Partikular Afirmatif Inklusif
Proposisi partikular afirmatif inklusif ialah pernyataan khusus mengiyakan yang sebagian subjek merupakan bagian dari predikat, yakni ada anggota subjek yang menjadi bagian predikat dan ada anggota predikat yang menjadi bagian subjek, misal: Sebagian rakyat Indonesia adalah keturunan asing. Dalam pernyataan ini term "rakyat Indonesia" bila dibandingkan dengan term "keturunan asing", ada sebagian rakyat Indonesia yang
keturunan asing dan ada bagian yang lain bukan keturunan asing, demikian juga ada sebagian keturunan asing yang menjadi rakyat Indonesia dan bagian yang lain bukan rakyat Indonesia, dirumuskan ada sebagian S yang P dan ada sebagian P yang S, disimbolkan (S n P), dibaca "S berpotongan dengan p" (lihat diagram).
Dalam diagram itu, sebagian anggota himpunan S menjadi bagian himpunan P, perpotongan antara S dan P sehingga disebut dengan himpunan perpotongan.
2. Proposisi Partikular Afirmatif Implikasi
Proposisi partikular afirmatif implikasi ialah pernyataan khusus mengiyakan yang sebagian dari subjek merupakan suatu predikat, yakni ada sebagian anggota subjek yang menjadi himpunan predikat, misalnya "Sebagian rakyat Indonesia adalah warga Partai Demokrasi Indonesia." Dalam pernyataan ini term "rakyat Indonesia" jika dibandingkan dengan term "warga Partai Demokrasi Indonesia" maka term "rakyat Indonesia" lebih luas dan term "warga Partai Demokrasi Indonesia" berada di dalamnya, di samping itu ada bagian lain yang bukan "warga Partai Demokrasi Indonesia" termasuk dalam term "rakyat Indonesia", dirumuskan sebagian S adalah P dan semua P adalah S, disimbolkan (S P), dibaca "S meliputi P" atau "sebagian S adalah P" (lihat diagram).

Dalam diagram itu, sebagian anggota himpunan S adalah himpunan P. dan himpunan P menjadi bagian himpunan S, S meliputi P, disebut juga dengan superhimpunan
Proposisi yang bersifat afirmatif yang berbentuk implikasi dapat dinyatakan secara partikular dan dapat juga dinyatakan secara universal tampa mengubah makna yang dikandungnya dengan menukar kedudukan subjek dan predikat. Cara menyatakan ini apabila keduanya dihubungkan dapat juga disebut sebagai suatu penyimpulan yang dirumuskan
Pernyataan (S⊃P) mempunyai nilai logik yang sama dengan (P⊂S) Penyimpulan ini akan dibicarakan secara jelas pada sistem penalaran konversi.
D. PROPOSISI PARTIKULAR NEGATIF
Proposisi partikular negatif ialah pernyataan bersifat khusus yang mengingkari adanya hubungan antara subjek dengan predikat, biasa disebut dengan proposisi O (dari huruf keempat kata latin "negO" yang berarti mengingkari), misalnya "Sebagian Sarjana Hukum bukan ahli politik, Sebagian rakyat Indonesia bukan keturunan asing. Ada peserta bimbingan tes Perintis Yogyakarta yang tidak ingin masuk Universitas Gadjah Mada, Sebagian makhluk bukan manusia."
Dalam contoh-contoh di atas, term sebagai subjek disingkat S, dan term sebagai predikat disingkat P, diabstraksikan menjadi: sebagian S bukan P atau ada S yang bukan P, dan dirumuskan secara simbolik:
3x (Sx ^~Px) : Ada x di mana S berlaku untuk x dan non P berlaku untuk x, atau cukup dibaca "ada S yang bukan P" atau "sebagian S bukan p".
Rumusan simbolik ini jika diterapkan pada salah satu contoh di atas maka dapat dibaca: Ada sesuatu, sesuatu itu rakyat Indonesia dan suatu itu bukan keturunan asing..
Proposisi partikular negatif ini jika dianalisis berdasarkan perbandingan luas term, dapat dibedakan antara dua macam, yaitu partikular negatif inklusif dan partikular negatif implikasi.
1. Proposisi Partikular Negatif Inklusif
Proposisi partikular negatif inklusif ialah pernyataan khusus mengingkari sebagian subjek tidak merupakan bagian dari predikat, yakni ada sebagian subjek yang tidak termasuk predikat dan ada sebagian predikat yang yang dak termasuk subjek, misalnya "Sebagian Sarjana Hukum bukan ahli politik Dalam perbandingan kedua term antara subjek dan predikat sebagaimana contoh ini, ada sebagian Sarjana Hukum yang ahli politik dan ada sebagian Sarjana Hukum yang bukan ahli politik, demikian juga ahli politik ada yang Sarjana Hukum dan ada yang bukan Sarjana Hukum, dirumuskan ada sebagian S yang bukan P dan ada bagian P yang bukan S, disimbolkan (S-P), dibaca "selisih perpotongan S dan P" (lihat diagram).
Dalam diagram itu, sebagian anggota himpunan S tidak termasuk himpunan bagian P, selisih S berpotongan dengan P, disebut juga dengan himpunan selisih, yaitu selisih potongan S dengan P atau selisih S potongan dengan P.
Proposisi partikular yang berbentuk inklusif baik afirmatif maupun negatif sebenarnya satu himpunan yang dibedakan antara dua kelompok saling berbalikan. Oleh karena itu, dua proposisi ini, yaitu (S∩P) dan (S-P) selalu berhubungan jika ada proposisi (S∩P) pasti ada proposisi (S-P), demikian juga sebaliknya jika ada proposisi (S-P) pasti ada proposisi (S∩P), dan keduanya tidak dapat terlepaskan yang satu membatasi yang lain dalam satu himpunan.
2. Proposisi Partikular Negatif Implikasi
Proposisi partikular negatif implikasi ialah pernyataan khusus mengingkari yang sebagian dari subjek tidak merupakan suatu predikat, yakni ada sebagian subjek yang bukan anggota predikat dan semua anggota predikat merupakan bagian dari subjek, misalnya "Sebagian manusia bukan bangsa Indonesia." Dalam perbandingan kedua term antara subjek dan predikat sebagaimana contoh ini, ada sebagian manusia yang tidak berbangsa Indonesia dan ada sebagian manusia yang berbangsa Indonesia, sebaliknya semua bangsa Indonesia termasuk dalam pengertian manusia, dirumuskan sebagian S bukan P dan semua P merupakan bagian dari S, disimbolkan (S 𝟃 P), dibaca "selisih S meliputi P" (lihat diagram).
Dalam diagram itu, sebagian anggota himpunan S bukan anggota himpunan P yang himpunan P ini merupakan bagian dari himpunan S, selisih dari S meliputi P, disebut juga himpunan selisih, yaitu selisih superhimpunan S meliputi P.
Proposisi partikular berbentuk implikasi baik afirmatif maupun negatif juga merupakan satu himpunan yang terdiri dua kelompok saling berbalikan, keduanya saling berhubungan dan saling membatasi tidak dapat terlepaskan satu dengan yang lain. Dengan demikian, apabila ada proposisi (S⊃P) pasti ada proposisi (S 𝟃 P), sebaliknya jika ada proposisi (S 𝟃 P) pasti ada proposisi (S⊃P) sehingga keduanya dapat saling menyimpulkan.
E. IKHTISAR PROPOSISI KATEGORIK
Empat macam proposisi kategorik sebagai bentuk dasar proposisi, yaitu proposisi universal afirmatif atau proposisi A, proposisi universal negatif atau proposisi E, proposisi partikular afirmatif atau proposisi 1, dan proposisi partikular negatif atau proposisi O, yang semua dapat dibedakan atas tujuh macam proposisi kategorik dapat dilihat dengan jelas dalam bagan sebagai ikhtisar proposisi kategorik halaman berikut (lihat bagan proposisi kategorik). Dalam bagan tersebut dikemukakan 4 macam proposisi dasar. yang kemudian diperinci menjadi 7 macam proposisi kategorik, beserta bentuk-bentuk diagram himpunannya, sebagai bentuk logik yang konkret.
Tujuh macam proposisi kategorik pada dasarnya berpangkal pada materi proposisi yang diungkapkan dalam bentuk diagram sehingga diagram himpunan merupakan bentuk logik dari materi yang ada. Tujuh macam proposisi yaitu: universal afirmatif ekuivalen, universal afirmatif implikasi, versal negatif (eksklusif), partikular afirmatif inklusif, partikular afirmatif implikasi, partikular negatif inklusif, dan partikular negatif implikasi.

KEGIATAN BELAJAR 3
Negasi Proposisi Kategorik
Proposisi kategorik yang dibedakan 4 macam, masing-masing dap diingkari, demikian juga dari 4 macam proposisi kategorik terseb diperinci lagi berdasarkan denotasi atau luas term yang dihubungkan menjadi tujuh macam proposisi kategorik dapat juga diingkari. Emp proposisi kategorik yang diingkari yaitu sebagai berikut.
1. Proposisi universal afirmatif menjadi negasi universal afirmatif, yait ingkaran pernyataan umum mengiyakan.
2. Proposisi universal negatif menjadi negasi universal negatif, yaitu ingkaran pernyataan umum mengingkari.
3. Proposisi partikular afirmatif menjadi negasi partikular afirmatif, yaitu ingkaran pernyataan khusus mengiyakan.
4. Proposisi partikular negatif menjadi negasi partikular negatif, yait ingkaran pernyataan khusus mengingkari.
Empat macam negasi proposisi kategorik beserta penjabarannya yang ada 7 macam ini akan diuraikan satu per satu secara rinci, hanya saja diagram yang dimaksudkannya lebih dari satu pengertian, yang diagramnya satu pengertian hanya satu, yaitu negasi ekuivalen.
A. NEGASI UNIVERSAL AFIRMATIF
Proposisi negasi universal afirmatif ialah pernyataan ingkaran yang mengiyakan adanya hubungan subjek dengan predikat, misalnya "Bukan semua rakyat Indonesia berketuhanan Yang Maha Esa, Tidak semu umum peserta bimbingan tes masuk Perguruan Tinggi, Tidak setiap warga negar mendapat kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan, Bukia Indonesia adalah negara berdasar atas komunis, Bukan manusia berakal budi."
Semua pernyataan ini diabstraksikan menjadi: tidak semua S adalah P dan dirumuskan secara simbolik
~Vx (Sx=>Px) : Tidak semua x jika S berlaku untuk x maka P berlaku untuk x atau dibaca secara singkat "tidak semua S adalah P"
Rumusan simbolik di atas dapat juga ditulis tanpa kuantor universal (Vx sama dengan (x));
~ (x) (Sx => Px) : Bukan untuk x, jika x adalah S maka x mempunyai sifat P, secara singkat dibaca "bukan S adalah P"
Proposisi negasi universal afirmatif, jika dianalisis dapat dibedakan 2 macam, yaitu negasi universal afirmatif ekuivalen dan negasi universal afirmatif implikasi.
1. Proposisi Negasi Universal Afirmatif Ekuivalen
Proposisi negasi universal afirmatif ekuivalen ialah pernyataan ingkaran mum mengiyakan yang antara subjek dan predikat merupakan suatu persamaan, yakni tidak semua anggota subjek adalah anggota predikat dan tidak semua anggota predikat adalah anggota subjek, misalnya "Bukan semua warga negara Indonesia adalah rakyat Indonesia, Bukan semua manusia adalah berakal budi, Tidak semua rakyat Indonesia ber-Pancasila." Dalam pernyataan pertama antara term "rakyat Indonesia" dan term "warga negara Indonesia", diingkari semuanya sehingga di luar persamaan atau di luar identik, yaitu dirumuskan bukan semua S adalah P dan bukan semua P adalah $, disimbolkan (SP), dibaca "bukan S identik dengan P" (lihat diagram).
Dalam diagram itu, hanya satu pernyataan: x, bukan S dan bukan P. berarti "bukan semua warga negara Indonesia adalah bukan rakyat Indonesia", jadi non S sama dengan non p.
2. Proposisi Negasi Universal Afirmatif Implikasi
Proposisi negasi universal afirmatif implikasi ialah pernyataan bukan pum mengiyakan yang semua subjek merupakan bagian dari predikat kni bukan semua anggota subjek menjadi himpunan bagian dari predikat misalnya "Tidak setiap warga negara Indonesia berketuhanan Yang Maha Eaa." Dalam pernyataan ini jika dianggap benar maka antara term "warga hegara Indonesia" dan term "yang berketuhanan Yang Maha Esa" luas himpunannya tidak sama, yang kemudian diingkari menjadi: "Tidak w warga negara Indonesia adalah berketuhanan Yang Maha Esa," dirumuskan tidak semua S adalah P dan tidak sebagian P adalah S, disimbolkan ~(S ⊂ P), dibaca "tidak S bagian dari P. (lihat diagram)
Dalam diagram itu, ada dua pengertian: x,, bukan S tapi dalam P, berarti "bukan warga negara Indonesia berketuhanan Yang Maha Esa"; x2, bukan S dan bukan P, berarti "bukan warga negara Indonesia yang tidak berketuhanan Yang Maha Esa"..
B. NEGASI UNIVERSAL NEGATIF
Proposisi negasi universal negatif ialah pernyataan ingkaran umum yang mengingkari adanya hubungan subjek dengan predikat, misalnya "Baka rakyat Indonesia tidak boleh mengikuti aliran komunis, Tidak semua manusia bukan keturunan kera, Tidaklah manusia bukan benda mati, Bukan badan benda mati tidak ada yang dapat bergerak, Bukan benda hidup bukanlah benda mati."
Semua pernyataan ini diabstraksikan menjadi: tidak semua S bukan P.dan dirumuskan secara simbolik:
~ Vx (Sx => ~Px) : Tidak semua x jika S berlaku untuk x maka non P berlaku untuk x atau dibaca secara singkat "tidak semua S bukan P".
Rumusan simbolik di atas dapat juga dinyatakan:
~(x) (Sx => ~Px) : Bukan untuk x jika x adalah S maka x mempunya sifat non P, secara singkat dibaca "bukan S tidak P"
Proposisi negasi universal negatif jika dianalisis berdasarkan perbandingan luas term maka hanya ada satu bentuk, yaitu berbentuk eksklusif, lengkapnya proposisi negasi universal negatif eksklusif.
Proposisi negasi universal negatif eksklusif ialah pernyataan ingkaran umum mengingkari yang berarti ingkaran antara subjek dan predikat tidak ada hubungan, yakni bukan semua anggota subjek tidak ada satu pun yang menjadi anggota predikat. Contoh term "rakyat Indonesia" dan term "yang nengikuti aliran komunis" jika diperbandingkan luasnya maka antara induanya itu tidak ada hubungan sama sekali, kemudian ini diingkari. Oleh karena itu, mengingkari himpunan S berada di luar himpunan P, demikian juga mengingkari himpunan P berada di luar himpunan S, disimbolkan 450P), dibaca "bukan S tidak ada hubungan dengan P" (lihat diagram).
Dalam diagram itu, ada dua pernyataan: x₁, bukan S tetapi masuk dalam P, berarti "bukan rakyat Indonesia yang mengikuti aliran komunis"; X2, bukan S dan bukan P, berarti "bukan rakyat Indonesia yang tidak mengikuti aliran komunis".
C. NEGASI PARTIKULAR AFIRMATIF
Proposisi negasi partikular afirmatif ialah pernyataan ingkaran khusus yang mengiyakan adanya hubungan subjek dengan predikat, misal: Tidak sebagian rakyat Indonesia adalah keturunan asing. Bukan sebagian Sarjana Hukum yang ahli politik, Tidak ada peserta bimbingan tes Perintis Yogyakarta yang ingin masuk ke Institut Teknologi Bandung, Bukan sebagian makhluk adalah manusia, Tidak ada mahasiswa Indonesia yang belajar di Amerika, Tidak ada terorisme belajar merakit bom di Amerika.
Semua pernyataan ini diabstraksikan menjadi : “tidak sebagian S adalah P” atau “tidak ada S yang P”, dan dirumuskan secara simbolik :
∃x (Sx ^ Px): Tidak ada x di mana S berlaku untuk x dan P berlaku untuk x, atau cukup dibaca "tidak ada S yang P" atau "tidak sebagian S adalah P”.
Proposisi megasi partikular afirmat ini jika dianalisis berdasarkan perbandingan luas term, dapat dibedakan antara 2 macam, yaitu negasi partikular afirmatif inklusif dan negasi partikular afirmatif implikasi
1. Proposisi Negasi Partikular Afirmatif Inklusif
Proposisi negasi partikular afirmatif inklusif ialah pernyataan ingkaran khusus mengiyakan yang sebagian subjek merupakan bagian dari predikat, yakni ada anggota subjek yang menjadi bagian predikat dan ada anggota predikat yang menjadi bagian subjek, misalnya "Bukan sebagian rakyat Indonesia adalah keturunan asing." Dalam pernyataan ini, ada sebagian rakyat Indonesia yang keturunan asing dan ada sebagian keturunan asing yang menjadi rakyat Indonesia, yang kemudian diingkari sehingga dirumuskan tidak ada sebagian S yang P dan tidak ada sebagian P yang S, disimbolkan (SP), dibaca "bukan S berpotongan dengan p" (lihat diagram).
Dalam diagram itu, ada 3 pernyataan, yaitu x1, anggota S yang bukan P, berarti "ada rakyat Indonesia yang bukan keturunan asing"; x2, bukan anggota S tapi masuk dalam P, berarti "tidak ada rakyat Indonesia yang keturunan asing"; serta x3, bukan S dan bukan P, berarti "tidak ada rakyat Indonesia yang bukan keturunan asing".
2. Proposisi Negasi Partikular Afirmatif Implikasi
Proposisi negasi partikular afirmatif implikasi ialah pernyataan ingkaran khusus mengiyakan yang sebagian dari subjek merupakan suatu predikat yakni tidak ada sebagian anggota subjek yang menjadi himpunan predikat, misalnya "Tidak ada sebagian rakyat Indonesia adalah warga Partai Demokrasi Indonesia." Dalam pernyataan ini term "rakyat Indonesia" lebih luas dan term "warga Partai Demokrasi Indonesia" berada di dalamnya. kemudian pernyataan ini diingkari, dirumuskan bukan sebagian S adalah P dan bukan semua P adalah S, disimbolkan (SP), dibaca "bukan S meliputi P" atau "bukan sebagian S adalah P" (lihat diagram).

Dalam diagram itu, ada 2 pernyataan, yaitu x, anggota S yang bukan P, Aarti "sebagian rakyat Indonesia bukan warga Partai Demokrasi Indonesia"; A bukan S yang bukan P, berarti "bukan rakyat Indonesia yang bukan warga Partai Demokrasi Indonesia".
D. NEGASI PARTIKULAR NEGATIF
Proposisi negasi partikular negatif ialah pernyataan ingkaran khusus yang mengingkari adanya hubungan subjek dengan predikat, misalnya Tidak ada Sarjana Hukum bukan ahli politik, Tidak sebagian rakyat Indonesia bukan keturunan asing. Tidak ada peserta bimbingan tes Perintis Yogyakarta yang tidak ingin masuk Universitas Gadjah Mada, Tidak sebagian makhluk bukan manusia."
Semua pernyataan ini diabstraksikan menjadi: "tidak sebagian S bukan P" atau "tidak ada S yang bukan P" dan dirumuskan secara simbolik:
3x (Sx ^ ~Px): Tidak ada x di mana S berlaku untuk x dan non P berlaku untuk x, atau cukup dibaca "tidak ada S yang bukan P" atau "tidak sebagian S bukan P".
Proposisi negasi partikular negatif ini jika dianalisis berdasarkan perbandingan luas term, dapat dibedakan antara dua macam, yaitu: negasi partikular negatif inklusif dan negasi partikular negatif implikasi.
1. Proposisi Negasi Partikular Negatif Inklusif
Proposisi negasi partikular negatif inklusif ialah pernyataan ingkaran khusus mengingkari yang sebagian subjek tidak merupakan bagian dari predikat, yakni ada sebagian subjek yang tidak termasuk predikat dan ada sebagian predikat yang tidak termasuk subjek, misalnya "Bukan sebagian Sarjana Hukum bukan ahli politik." Dalam contoh ini, ada sebagian Sarjana Hukum politik yang ahli politik dan ada sebagian Sarjana Hukum yang bukan ahli yang kemudian diingkari sehingga dirumuskan tidak ada sebagian S yang bukan P dan tidak ada bagian P yang bukan S, disimbolkan (S-P), dibaca "bukan selisih perpotongan S dan P" (lihat diagram).
Dalam diagram itu, ada 3 pernyataan, yaitu x₁, anggota S dan anggota P berarti "sebagian Sarjana Hukum yang ahli politik"; x2, bukan S tetapi anggota P, berarti "bukan Sarjana Hukum yang ahli politik"; x3, bukan S dan bukan P, berarti "bukan Sarjana Hukum yang bukan ahli politik".
2. Proposisi Negasi Partikular Negatif Implikasi
Proposisi negasi partikular negatif implikasi ialah pernyataan ingkaran khusus mengingkari yang sebagian dari subjek tidak merupakan suatu predikat, yakni tidak ada sebagian subjek yang bukan anggota predikat misal: Tidak sebagian manusia bukan bangsa Indonesia. Dalam perbandingan kedua term antara subjek dan predikat sebagaimana contoh ini, ada sebagian manusia yang tidak berbangsa Indonesia dan ada sebagian manusia yang berbangsa Indonesia, kemudian pernyataan ini diingkari, dirumuskan bukan sebagian S bukan P dan bukan semua P merupakan bagian dari S, disim- bolkan (SP), dibaca "bukan selisih S meliputi P" (lihat diagram).
Dalam diagram itu, ada dua pernyataan: x), anggota S dan anggota P. berarti "sebagian manusia adalah bangsa Indonesia"; X2, bukan anggota S dan bukan anggota P, berarti "semua bukan manusia adalah bukan bangsa Indonesia".